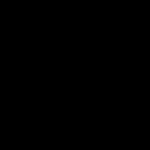Menutup sesi pemutaran dan pembahasan Neorealisme Italia di Senin Sinema Dunia #3 (SSD) Forum Lenteng, Jurnal Footage menghadirkan bahasan estetik panjang André Bazin yang menjadi latar gerakan sinema pasca Perang Dunia II. Tulisan ini pernah dimuat dalam Footage Internal—yang dibagikan secara terbatas kepada anggota Forum Lenteng—Nomor 7, April 2008, Tahun I yang diterjemahkan oleh Mirza Jaka Suryana dari bahasan, “An Aesthetic of Reality: Neorealism (Cinematic Realism and the Italian School of the Liberation)”, dalam What is Cinema? Volume II, Kumpulan Esai Pilihan, terjemahan Hugh Gray, University of California Press, Berkeley dan Los Angeles, 1971, h. 16-40. Jurnal Footage menambahkan beberapa keterangan (judul filem, keterangan nama, dan catatan kaki) untuk memudahkan pembaca memahami konteks tulisan yang inspiratif ini.
Selamat membaca.

André Bazin
Kepentingan historis atas filem Paisà (1946), Rossellini telah sepenuhnya diperbandingkan dengan sejumlah mahakarya filem klasik. Tanpa ragu, George Sadoul menyebutnya sejajar Nosferatu (FW. Murnau,1922), Die Nibelungen (Fritz Lang, 1924), atau Greed (Von Stroheim,1924). Saya tunduk setulusnya pada pujian tinggi ini, selama penyebutannya bersama ekspresionisme Jerman itu dipahami untuk merujuk tingkat kebesaran filem dan bukan sifat kedalaman estetik pembuatnya. Perbandingan yang lebih baik bisa pula diajukan bersama filem Potemkin di tahun 1925. Selebihnya, realisme filem-filem Italia masa kini sudah seringkali dihadapkan dengan estetikisme Amerika dan sebagian, dengan hasil-hasil produksi Prancis. Bukankah sejak awal, filem-filem tersebut telah meremukan realisme yang mencirikan filem-filem Rusia ala Eisenstein, Pudovkin, dan Dovzhenko sebagai karya revolusioner baik dalam seni maupun politik, atau sebaliknya, kepada estetikisme filem-filem Ekspresionis Jerman serta pengagungan terhadap Hollywood? Paisà, Sciuscià (Vittorio de Sica, 1946) dan Roma Città Aperta (Rosselini, 1946), seperti juga Potemkin, telah mengawali pertentangan berlarut-Iarut antara realisme dengan estetikisme di dalam filem. Namun sejarah takkan berulang; kita mesti menerangkan bentuk tertentu pertikaian estetik itu ditinjau pada saat ini, sebuah jalan-keluar tempat neorealisme Italia berutang kejayaan di tahun 1947.


Still dari filem Paisà
Para Perintis
Berseberangan dengan hasil karya yang sangat Italia serta letupan gairah dari kejutan yang diciptakannya, mungkin kita bisa menyisihkan langkah lebih mendalam kepada asal-mula kelahiran kembali ini, dan memilih melihatnya lebih sekadar kebangkitan seketika yang timbul laksana kawanan lebah dari jasad-jasad busuk fasisme dan perang. Tidak diragukan bila pembebasan dan bentuk-bentuk sosial, moral dan ekonomi Italia dipandang telah memainkan peran menentukan dalam produksi filem. Kita akan kembali ke soal ini nanti. Nyata sudah bila kurangnya informasi mengenai sinema Italia telah memperangkap kita pada kepercayaan akan keajaibannya yang tiba-tiba.
Demikianlah kini agaknya, untuk menilai dari kepentingan dan kualitas hasil filemnya tatkala Italia adalah negeri tempat pemahaman filem sedang tinggi-tingginya, Centro Sperimentale[1] di Roma sudah ada sebelum Institut des Hautes Etudes Cinematographiques (Paris) kita sendiri, dan di atas segalanya, pertaruhan kaum cendikia di Italia—tidak seperti di Prancis—tak berdampak bagi penciptaan filem. Jurang menukik antara kritik (kritikus) dan penyutradaraan (sutradara) lebih tak terlihat dalam sinema Italia daripada yang terjadi dalam dunia sastra Prancis.

Centro Sperimentale, Roma
Terlebih lagi fasisme (ideologi politik khas Italia), tidak seperti Nazisme, mengizinkan eksistensi kemajemukan artistika, khususnya pemikiran sinema. Kita boleh ragu soal hubungan Festival Filem Venesia dengan kepentingan politik Kaum Bangsawan meski tak bisa disangkal gagasan festival filem internasional itu lalu terselenggara dengan bagus, dan kini bisa diukur gengsinya lewat kenyataan bahwa lima atau enam negara Eropa saling bersaing merebut penghargaan. Setidaknya, kaum kapitalis dan penguasa Fasis telah menawarkan Italia studio-studio filem yang modern. Bila yang muncul adalah fiem-filem gaya melodramatik konyol dan keterlaluan yang dibuat-buat, itu tak menghalangi sejumlah pribadi cendikia untuk cukup cerdas membidik filem-filemnya dengan tema-tema ‘kekinian’ tanpa melakukan sama sekali kesepakatan dengan kekuasaan untuk penciptaan filem-filem bermutu tinggi yang melatari kerja kekinian mereka.
Semasa perang, kita tidak sangat menduga—meski tentu saja boleh—filem-filem Rossellini seperti SOS 103 atau La Nave Bianca (1941) bisa lebih mempesona kita. Apalagi saat kaum kapitalis dan politik dungu telah mengendalikan produksi komersial, kecendiakawanan, kebudayaan dan percobaan penelitian beroleh naungan di dalam gedung-gedung arsip filem dan dalam pembuatan filem-filem pendek. Pada 1941, sutradara filem II Bandito (1946), Alberto Lattuada, yang kala itu kepala arsip kota Milan, tidak bisa menghindari penjara saat menunjukkan versi lengkap filem La Grande IlIusion.[2]
Lebih dari Itu, sejarah sinema Italia belum dikenal. Kita hela-jeda pada Le Notti di Cabiria (Fellini, 1956) dan Quo Vadis (Mervyn LeRoy, 1951), untuk menemukan segenap bukti terbaru luar biasa yang kita perlu pada filem La Corona di Ferro (Alessandro Balsetti, 1941) dalam mengandaikan tak berubahnya ciri filem-filem yang dibuat di balik Pegunungan Alpen itu: sebuah selera, yakni selera rendahnya untuk mengidealisir aktor-aktor utama, tekanan kekanakan pada pengadeganan, kendurnya mise-en-scène (penyutradaraan), penonjolan perlengkapan (paraphernalia) bel canto dan opera, yang naskah-naskah konvensionalnya dipengaruhi teater serta drama cinta sedih hingga chanson de geste-nya (epik) menciut ke sekadar cerita pertualangan. Tak sangsi lagi, terlalu banyaklah filem Italia telah paling baik berlaku membenarkan semacam karikatur dan sebagian besar sutradara—termasuk yang terbaik—telah berkorban dengan terkadang merendahkan diri kepada kepentingan komersial. Tentu saja hasil filem besar semacam Scipio Africanus[3] (Carmine Gallone, 1937) itulah ekspor utamanya. Ada lagi lapisan artistik lain yang tak dipungkiri hampir secara eksklusif direlakan demi pasar dalam negeri. Kini saat gemuruh para gajah jinak Scipio sekadar mengerang samar-samar, lebih baik kita pinjam-dengar kecemasannya lewat lantunan merdu buatan filem Quatro Passi fra Ie Nuvole (Alessandro Balsetti, 1942).
Pembaca atau setidaknya yang pernah melihat filem berikut ini, tak ragu lagi akan se-terperangah kita saat menyimak bahwa komedi dengan segenap lubuk-rasa bebasnya ini berlimpahan puisi, tangkapan santai realisme sosialis yang terkait langsung dengan sinema kini Italia di tahun 1942, dua tahun setelah La Corono di Ferro yang masyhur itu dan buatan sutradara yang sama, Alessandro Blasetti, yang kepadanya serentak pula kita berutang pada filem Un’avventura di Salva tor Rosa (Balsetti, 1939) dan yang terbaru, filem Sciuscia, Vittorio de Sica, selalu menimbang penampilan komedi-komedi manusiawi dan mengharukan yang marak dengan realisme, di antaranya pada tahun 1942, I Bambini ci guardano (de Sica, 1944). Sejak 1932, Mario Camerini telah membuat filem kekerasan Gli uomini che Mascalzoni yang seperti Roma Città Aperta, Rossellini, telah bertempatkan di jalanan-jalanan ibukota, serta Piccolo Mondo Antico (Mario Soldati, 1941) yang tak kurang ke-Italia-annya.
Sungguh tak banyak nama-nama baru sutradara Italia sekarang. Yang termuda, seperti Rossellini, mulai membuat filem di awal perang (Perang Dunia II). Para sutradara yang lebih tua seperti Blasetti dan Mario Soldati, sudah lama dikenal sejak masa awal yang tadi telah dibicarakan.
Tetapi mari kita tidak saling melangkah pada dua kutub yang berbeda dan menyimpulkan bahwa sebenarnya tak pernah ada apa yang dinamakan sebagai mazhab baru Italia. Kecenderungan realisnya, kedomestikannya, satirisnya, dan deskripsi sosial kehidupan sehari-harinya, ujaran sensitif dan pultiknya, yang sebelum perang merupakan kualitas-kualitas sempalan, begltu saja marak pucat membiru di kaki produksi raksasa (giant sequoias production). Tampaklah sejak awal perang, seberkas cahaya mulal dicercahkan belantara papier-mâche. Gaya filem La Corona di Ferro seperti mengejek diri. Rossellini, Lattuada, Blasetti telah berpayah-payah demi kepentingan mendunia realisme. Meskipun demikian, ‘pembebasan’-lah pencipta kecenderungan-kecenderungan estetik ini terbentang sampai membiarkannya berkembang di bawah takdir kondisi-kondisi baru guna menerima andil mereka dalam menyuntikkan perubahan hakiki pada penyutradaraan dan pemahaman.
Pembebasan: Pecahan dan Kalahiran Kembali
Beberapa komponen mazhab baru Italia yang muncul menjelang ‘pembebasan’: awak kerja, teknik dan kecenderungan estetik. Tetapi pecampurbauran yang tiba-tiba dari sejarah, sosial, dan ekonomi mereka jugalah yang telah menghasilkan sintesa unsur-unsur baru yang menegaskan keberadaan mereka.
Selama lebih dua tahun terkahir, ‘pemberontakan’ dan ‘pembebasan’ telah menawarkan tema-tema penting, namun tidak sebagaimana Prancis —dan tentu saja bisa dikatakan tidak sebagaimana sinema Eropa umumnya— filem-filem Italia tidak terbatas pada tema-tema ‘pemberontakan’. Di Prancis, tema ‘pemberontakan’ segera menjadi masyhur. Demikianlah, di masa ‘pembebasan’, sesungguhnya ‘pemberontakan’ sudah menjadi milik kerajaan sejarah. Jerman mengalami kematian, lantas kehidupan dimulai kembali. Sebaliknya di Italia, ‘pembebasan’ tidak menandakan ada yang kembali ke suatu kebebasan lama ataupun baru; ia mengartikan revolusi politik, pendudukan Sekutu serta guncangnya ekonomi dan sosial. Pembebasan berlangsung lamban di hari-hari tanpa akhir. Berdampak besar pada kehidupan ekonomi, sosial dan moral bangsa.
Lalu tidak sebagaimana kerusuhan Paris, ‘pemberontakan’ dan ‘pembebasan’ di Italia bukan sekadar ucapan akan isyarat sejarah. Ketika RosselIini membuat filem Paisà, naskahnya memang terkait dengan permasalahan yang terjadi masa itu. Il Bandito memperlihatkan betapa pelacuran dan pasar-gelap tumbuh di atas sol tentara yang menderap-derap dekat, dan betapa pengangguran dan rasa kecewa telah mengubah narapidana bebas menjadi penjahat. Kecuali pada filem-filem ‘pemberontakan’ tanpa cacat seperti Vivere in Pace (Luigi Zampa, 1947) atau Il Sole Sorge Ancora (Aldo Vergano, 1946), sinema Italia dicatat karena perhatiannya pada kejadian nyata sehari-hari. Kritikus Prancis tidak gagal dalam menekankan (meski selalu dengan rasa terperangah, baik pujian maupun kecaman yang tulus) sejumlah acuan spesifik di masa pasca perang ketika dengan sengaja telah memperkenalkan Marcel Carne[4] dengan filem terakhirnya. Bila sutradara dan penulis telah berupaya keras membuat pemahaman kita, soalnya ialah selama satu dasawarsa ini 19 dari 20 filem Prancis tidak tercatat. Selain itu, bahkan saat gambaran utama naskahnya tak berkaitan dengan kejadian nyata, filem-filem Italia itu sangat condong kepada pewartaan. Sikap ini tak bisa diluaskan hanya dari konteks sosial tertentu dan lepas secara historis, sebagian lagi abstrak seolah penyutradaraan tragedi, seperti yang dalam berbagai tingkatan, kerap terjadi dalam sinema Amerika, Prancis, atau Inggris.
Alhasil, filem-filem Italia memiliki mutu dokumenter yang cemerlang yang hanya bisa disisihkan dari naskah jika menghilangkan seluruh situasi sosial tempat akar-akarnya tertanam begitu dalam.
Kesetiaan penuh dan wajar akan aktualitas ini dibenarkan dan diteguhkan dari dalam oleh ikatan spiritual di masa itu. Tidak diragukan, gelombang sejarah Italia masa kini tidak berbalikarah. Perang dialami bukan sebagai masa jeda melainkan akhir suatu masa. Dalam artian itu, Italia baru genap tiga tahun. Tapl dampak lain bisa diakibatkan dari sebab yang sama. Apa yang kekal menakjubkan sebagai penjamin sinema Italia meraih penonton moral yang luas di belahan negeri-negeri Barat adalah tawaran pentingnya atas’penggambaran aktuaiitas. Di dunia yang kembali terobsesi oleh teror dan kebencian, di mana realitas dengan sendirinya sudah demikian langka diinginkan selain dilontarkan atau dikeluarkan sebagai perlambang politik, sinema Italia, di tengah zaman yang ditampilkannya adalah satu-satunya yang memelihara humanisme revolusioner.
Cinta dan Penolakan Realitas
Filem-filem terbaru Italia setidaknya pra-evolusioner. Secara dalaman dan luaran, seluruhnya menampik realitas kegunaan melalui humor, satir atau puisi, tidak soal seberapa teguh pegangan pendiriannya, selain kesemua itu amat dikenal dalam menyikapi realitas sebagai medium atau tatanan penutup. Mengecamnya –bukan berarti tidak yakin. Sederhananya, filem-filem itu tidak lupa bahwa dunia ini telah ada sebelum menjadi laknat. Hal konyol ini barangkali sepolos pujian Beaumarchais[5] soal airmata karena melodrama. Tetapi tidakkah seseorang, sepulangnya darl filem Italia, merasa lebih baik dalam memiliki dorongan untuk mengubah tatanan masalah seandainya memungkinkan dengan mempengaruhi orang-orang, setidaknya yang bisa dipengaruhi, di mana kebutaan, prasangka, dan kemalangan sajalah yang membawa kehancuran kaum sejawatnya?
Itu sebabnya saat kita membaca sejarahnya, skenario banyak filem Italia terbuka bagi kelakar. Mempersempit alur cerita, seringkali semua itu hanya mengesahkan melodrama, namun di layar, semua orang di dalam filem sungguh-sungguh nyata. Tidak seorang pun diciutkan ke kondlsi menjadi sebuah objek maupun perlambang yang akan membiarkan klta membenci kaum serba nyaman tanpa lebih dulu menjalani cobaan kemanusiaan mereka. Saya mempersiapkan diri untuk meninjau humanisme sejati filem-filem Italla masa kini sebagai nilai utama.[6] Seluruh filem menawarkan peluang citarasa revolusioner yang melegakan di mana teror masih belum berperan, menjelang menit tamatnya berakhir bagi kita.
Percampuran Pemeran
Apa yang mula-mula secara wajar mengejutkan khalayak adalah ketinggian mutu pengadeganan. Roma Città Aperta memperkaya filem dunia dengan penampilan tak terlupakan dari pentas perdana Anna Magnani[7] sebagai gadis tengah mengandung, Fabrizzi sang pendeta, Pagliero si anggota Pemberontak, dan lain-lainnya dengan penampilan yang saling bersaing dalam retrospeksi perwatakan pada filem masa silam paling menggugah. Reportase dan pemberitaan media massa yang diterima, wajarlah bermaksud memberitahu kita bahwa filem Sciuscià berisikan banyak penjahat jalanan, tempat Rossellini secara acak membidik kerumunan untuk gambar pengadeganan, di mana si tokoh wanita di kisah awal Paisa adalah gadis buta-huruf yang ditemukan didermaga. Anna Magnani mengaku dirinya profesional meskipun berasal dari dunia cafe-concert. Maria Michi, ya, cuma gadis mungil pekerja produksi kecil filem.
Meski pemain semacam ini tidak lazim di dalam filem, hal itu tidak baru. Sebaliknya, pemakaian selanjutnya dengan beragam mazhab realistik sudah sejak awal masa Lumière ini menunjukkan bahwa kaidah sejati sinema inilah yang disepakati mazhab Italia untuk mempersilakan kita merumuskan sendiri dengan seyakinnya. Juga dalam masa-masa lalu sinema Rusia, kita mengagumi pilihannya untuk peran-peran keseharian para aktor non-profesionalnya di dalam filem. Kenyataannya, suburlah legenda seputar filem-filem Rusia. Teater berpengaruh kuat pada mazhab-mazhab tertentu Soviet meski filem-filem awal Eisenstein yang tanpa aktor-aktor sama realisnya dengan filem The Road to Life (Nikolai Ekk, 1931) yang ternyata diperankan oleh para profesional teater, hingga sejak itu para aktor filem-filem Soviet seterusnya menjadi profesional seperti di negara-negara lain.
Tanpa mempunyai sekolah sinematografi yang besar selama masa 1925, sinema Italia sekarang dapat menampilkan tiadanya para aktor, meskipun filem di luar arus kelaziman ini dari masa ke masa bisa mengingatkan kita akan untungnya tidak memakai mereka. Filem semacam ini akan selalu dikhususkan hanya agak disisihkan dari dokumen sosial. Misalnya dua filem L’Espair (André Malraux, Boris Peskine, 1945) dan La Derniere Chance (Leopold Lindtberg, 1945). Di sekitar kedua filem itu subur pula legenda.
Para pemeran utama filem Malraux itu tidak semua aktor senggang yang dipanggil sesaat untuk memerankan diri mereka sendiri sehari-hari. Beberapa saja dari mereka memang benar adanya tetapi bukan tokoh-tokoh utama. Si Petani itu misalnya, adalah aktor lawak tenar di Madrid. Sepintas, para serdadu La Derniere Chance memang penerbang sungguhan yang ditembak jatuh di Swiss, tapi si wanita Yahudi adalah aktris panggung. Cuma hasil-hasil karya filem semacam Tabu (F.W Murnau, 1931) yang seluruhnya tanpa aktor profesional —tapi dalam hal ini seperti pada filem kanak-kanak— kita berhadapan dengan satu genre khusus di mana aktor profesional hampir tak terbayangkan. Yang terbaru, Rouquier dalam Farrebique (Georges Rouquier, dokumenter, 1946) telah mengawali puncak perannya. Sambil menyimak keberhasilannya, baiklah kita juga mencatat bahwa filem ini sangat unik dan bahwa permasalahan yang dihadirkan oleh suatu filem petani, sejauh dengan pertimbangan pengadegan, tidak ada bedanya dengan semua filem jenis eksotik. Sejauh merupakan teladan, Farrebique adalah hal tersendiri dan sama-sekali tidak menggugurkan dalil yang diusulkan untuk menyebutnya kaidah campuran. Bukan soal tidak tampilnya aktor-aktor profesional yang dalam sejarahnya adalah jaminan realisme sosial dan jaminan filem Italia. Di samping itu khususnya, penolakan konsep bintang ini dan percampuran antara yang profesional dengan yang hanya beradegan kadang-kadang saja, adalah biasa. Pentinglah untuk menghindari pemain profeslonal karena peran yang sudah dikenali. Khalayak tak semestinya terbebani segala prasangka. Pentinglah kiranya bila si petani dalam Espoir (André Malraux, Boris Peskine, 1945) adalah sang komedian teater, dan Anna Magnani pelantun Iagu-Iagu masyhur, serta Fabrizzi badut bangsal musika. Bahwa seorang adalah aktor, tidak berarti ia tak bisa dipakai. Sebaliknya malah.

Still dari filem Farrebique
Tetapi profesionalismenya mesti diartikan pengabdian belaka selama hal itu membolehkan dirinya lebih luwes tanggap pada kepentingan penyutradaraan serta guna menangkap pemeranan dengan sebaik-baiknya. Para pemeran non-profesional sewajarnya dipilih karena kesesuaian peran. Entah karena cocok fisik atau sekian kesamaan antara peran dan kehidupannya sendiri. Saat percampuran terjadi —tapi pengalaman menunjukkan, itu takkan berlaku kecuali sejumlah pesan “moral” dipertemukan di dalam naskah— hasilnya ialah perasaan takjub sungguhan akan kebenaran yang kita capai pada filem-filem Italia masa sekarang. Kesetiaan para pemeran pada naskah yang kian mengedepankan mereka dan memperkedil kepura-puraan teatrikal, telah membuat semacam persenyawaan di antara para pemain. Kehijauan teknis para amatir tertolong oleh pengalaman para profesional sekaligus menguntungkan para profeslonal sendiri dari situasi umumnya yang sahih.
Meskipun demikian, amat disayangkan jika manfaat sebuah metode seni filem sekadar diterapkan sana-sini sebab di dalamnya sendiri menyimpan benih kehancurannya. Persenyawaan kimiawi diperlukan demi ke-tak-stabilan, dan tiada apapun yang bisa mencegahnya berkembang ke titik tempatnya mengenali kembali dilema estetik yang dahulu pernah dipecahkannya —yaitu ketergantungan pada sang bintang dan sifat dokumenter tanpa aktornya. Ketidak-paduan ini segera dapat jelas teramati pada filem kanak-kanak atau filem-filem yang memakai warga di lokasi. Si Rari Kecil pada filem Tabu, dikatakan berakhir sebagai pelacur di Polandia; kita semua tahu bagaimana si anak yang dibesarkan sebagai sang bintang dengan filem pertamanya. Meski ini adalah hal lain, dengan sangat baik si anak akan menjadi pemain belia ajaib. Masih hijau dan tanpa pengalaman, jelas sekali tak terbantahkan si anak takkan dapat bertahan terhadap pengulangan-pengulangan. Tak bisa kita bayangkan keluarga Farrebique muncul dalam serangkaian enam filem hingga akhirnya dikontrak Hollywood. Sementara bagi para pemain profesional bukan bintang, alur perpecahan ini agak berbeda kerjanya. Kesalahan ada pada khalayak. Sementara sang bintang pujaan diterima sebagaimana adanya di mana-mana, sukses sebuah filem dipakai buat memberi arti bagi pemain biasa pada pemeranannya di dalam filem itu. Hanya saja kaum produser terlalu suka mengulang sebuah sukses dengan mencicip sajian terkenal kesukaan khalayak menonton bintang-bintang idaman dalam peran-peran mapannya. Jika seorang pemain cukup peka untuk menghindar dari penjara pemeranan tunggalnya, masih ada kenyataan wajah dan tingkah polah kebiasaannya dalam pengadeganan yang sudah dikenali akan mencegah percampuran dengan digantikan oleh pemain bukan profesional.

Still dari filem Tabu
Estetikisme, Realisme dan Realitas
Kesetiaan pada kehidupan sehari-hari dalam skenario, kejujuran pemeranan, bagaimanapun sekadar bahan-bahan dasar estetika filem Italia.
Kita mesti menyadari saling-silang penyerapan estetika dengan beberapa kementahan, sekian efektivitas seketika berasal dari suatu realisme yang sekadar puas dengan kehadiran realitas. Saya memandang nilai filem Italia pada kehadirannya akan tiap realisme dalam seni awalnya mengandung kedalaman estetik. Kita selalu merasa begitu, meski gaung tuduhan sihir sebagian kita kini terhadap para pemain mencurigai adanya perjanjian setan berupa seni untuk seni, kita cenderung telah melupakannya. Pembayangan realitas di dalam seni adalah pertimbangan si seniman sendiri. Dibanding kebebasan imajinasi, darah dan daging realitas tak lebih mudah direngkuh dalam jalinan kesusasteraan maupun sinema. Atau dengan cara lain bisa dikatakan, bahkan saat penciptaan dan kompleksitas bentuk-bentuk tak lagi bisa diterapkan ke dalam muatan aktual karya demi berpengaruh pada efektivitas pranata, semua itu tak berhenti hingga begitu saja. Karena sinema Soviet amat mengabaikan soal ini, sinemanya tergelincir dari peringkat pertama duapuluh tahunnya ke peringkat terakhir di negara-negara penghasil besar filem. Potemkin telah menjungkirbalikkan dunia sinema tidak hanya oleh pesan politiknya, tidak pula oleh penggantian latar tempel studio penataan yang sebenarnya dengan sang bintang utama bersama suatu kerumunan tak bernama, namun karena Eisenstein teorisi montase terbesar pada zamannya karena kerjasamanya dengan Tisse, kamerawan terbaik masanya dan oleh karena Rusia adalah puncak ketinggian pemikiran sinematografi —ringkasnya, karena filem-filem “realis” Rusia lebih mengenal estetika ketimbang seni sinema ekspresionisme Jerman dengan segala latar dan penampilan serta pencahayaan dan tafsir artistiknya.
Sama saja kini dengan sinema Italia. Bukan retrogresif (gerak balik) estetik atas Neorealismenya, sebaliknya kemajuan akan ekspresi lah kejayaan evolusinya dalam bahasa sinema, suatu kelanjutan gaya bahasanya.
Mari kita lebih menukik ke dalam sinema untuk melihat kedudukannya sekarang. Sejak tamatnya bid’ah kaum ekspresionis (expressionist heresy)[8], terutama setelah adanya suara, kita boleh mengira bila kecenderungan umum sinema yakni menuju realisme. Baiklah kita penuh sepakat bahwa filem ingin memberi penonton ilusi kenyataan sesempurnanya dalam batas-batas logika kepentingan narasi sinematografi darn dalam batas-batas teknik kekiniannya. Karena itu sinema tegak berseberangan dengan puisi, lukisan, teater, dan lebih dekat pada novel. Di sini saya tak berniat membenarkan kecenderungan dasar estetik sinema modern ini, biarpun pada teknis, psikologis atau dasar-dasar ekonominya. Saya hanya sesekali menyatakan ini tanpa berprasangka baik validitas intrinsik sejenis evolusinya maupun tingkat pencapai akhirnya. Namun realisme dalam seni hanya tercapai dengan satu cara —yakni melalui tipuan (artifice).
Setiap bentuk estetika harus memilih antara apa yang penting dipertahankan dan apa yang harus ditanggalkan serta apa yang seharusnya tidak boleh diandaikan. Namun ketika tujuan-tujuan estetik ini pada dasarnya demi menciptakan ilusi realitas sebagaimana dilakukan sinema, pilihan ini menghasilkan pertentangan mendasar yang serempak dengan itu tak dapat diterima namun diperlukan: diperlukan, karena seni hanya dapat hadir saat pilihan demikian dilakukan. Tanpa itu, dengan mengira sinema secara sempurna berada di sini dan secara teknis kini dimungkinkan, kita akan semata-mata kembali kepada realitas. Ini tidak bisa diterima oleh karena hal itu tentu saja dilakukan dengan mengorbankan realitas tempat sinema menawarkan diri untuk secara keseluruhan memperbaikinya. Karena itu kaburlah kiranya menampik setiap perkembangan terbaru teknik yang bertujuan menambah realisme sinema, misalnya suara, warna, dan stereoscopy. Sungguh ‘seni’ sinema dihidupkan dengan kontradiksi ini. la meraih hasil kebanyakan kemampuan abstraksi dan simbolismenya yang tersedia oleh keterbatasan yang ada pada adegan, tetapi pemanfataan sisa-sisa konvensi yang luput oleh teknik dapat dengan baik bekerja untuk kebaikan atau kerugian realisme. la bisa memuaikan atau menetralkan efektivitas unsur-unsur realitas yang ditangkap kamera. Kita dapat, jika bukan mengklasifikasi sesuai kepentingan, mengelompokkan ragam gaya sinematografi dalam arti perluasan realitasnya. Kita akan memaknainya sebagai ‘realis’, hingga kemudian segenap pranata naratif cenderung membawa pelebaran realitas ke dalam layar. Realitas tidak secara kuantitatif dipungut. Peristiwa yang sama, objek yang sama, dapat dihadirkan dalam beragam cara. Tiap-tiap representasi menanggalkan atau mempertahankan beragam kualitas yang mempersilakan kita mengenali objek di dalam layar. Masing-masing pengenalan, demi alasan-alasan didaktik maupun estetik, abstraksi-abstraksinya kurang-Iebih bekerja secara merusak dan dengan itu tak mengizinkan keaslian tampil seutuhnya. Kesimpulannya, kerja ‘kimiawi’ tak terhindarkan dan penting ini disebabkan realitas permulaan di situ telah tergantikan oleh suatu ilusi realitas yang tercipta dari sekumpulan abstraksi (hitam dan putih, permukaan datar), dari konvensi-konvensi (aturan montase, contohnya), dan dari realitas otentik. Inilah ilusi yang perlu itu namun yang dengan segera mendorong hilangnya kesadaran akan realitas itu sendiri yang telah terartikan di dalam benak penonton seiring representasi sinematografinya. Dan bagi pembuat filem yang untuk sesaat telah berwenang melindungi ketaksadaran ini kepada penonton, lama-kelamaan ia terbujuk untuk mengabaikan realitas. Dari kebiasaan dan kemalasannya meraih kedudukan saat dirinya sendiri tak lagi mampu mengisahkan asal-mula dusta-dusta itu dimulai dan berakhir. Di situ takkan pernah ada pertanyaan untuk menjuluki dirinya sebagai pendusta karena seninya mengandung kedustaan. Ia hanya tak lagi memegang kendali seninya. Dirinya sendirilah kedunguan itu, dan karena itu ia dikeluarkan kembali dari kuasa lebih lanjutnya akan realitas.

Still dari filem Citizen Kane
Dari Citizen Kane hingga Farrebique
Tahun-tahun terakhir ini dengan sejelasnya telah membawa evolusl estetika sinema ke arah realisme. Dua kejadian terpenting evolusi sejarah sinema sejak 1940 ini ialah Citizen Kane dan Paisà. Meski berbeda alurnya, kedua filem itu menandai lompatan menentukan menuju realisme. Jika saya mengemukakan filem Orson Welles itu sebelum menganalisis gaya bahasa filem Italia, hal ini lebih dikarenakan dapat mempersilakan kita untuk menempatkan filem yang kedua itu ke dalam perspektif asalinya. Orson Welles telah mengembalikan ilusi sinematografi kepada kualitas mendasar realitas —yaitu kelangsungannya. Penyuntingan klasik yang diturunkan dari Griffith, memisahkan realitas ke dalam bidikan-bidikan gambar suksesif yang hanya berupa satu rangkaian, baik cara pandang logis maupun subjektif atas satu kejadian. Seorang pria terkunci di selnya menunggu kedatangan si algojo. Matanya tersiksa pada pintu selnya. Saat si algojo baru saja akan masuk, bisa kita pastikan sutradara akan melakukan pemotongan pada ambilan gambar jarak-dekat gagang pintu yang bergerak melambat. Tangkapan dekat ini secara psikologis terbenarkan melalui konsentrasi korban kepada lambang penderitaan mautnya itu. Tata ambilan-ambilan gambar ini merupakan ujicoba konvensional terhadap jangkauan realitas yang sejatinya membentuk bahasa sinematografi zaman itu.
Konstruksi tersebut kemudian memperkenalkan kejelasan unsur abstrak di dalam realitas. Karena kita demikian terbiasa pada abstraksi semacam itu, kita tidak lagi merasakannya. Orson Welles merintis revolusinya melalui cara sistematis penempatan kedalaman fokus yang selama ini tak pernah digunakan. Sementara lensa kamera secara suksesif biasanya memusatkan perhatian pada bagian-bagian yang berbeda pada layar, kamera Orson Welles dengan ketajaman yang merata menangkap seluruh permukaan pandang yang termuat secara simultan pada ruang dramatik. Masalahnya bukan lagi pada pilihan penyuntingan atas apa yang kita lihat, yang dengan begitu memberikan padanya satu signifikansi a priori (sebelumnya/awal), yakni pikiran penonton yang dipaksa memilah-milahkan sebagaimana halnya dalam semacam parallelepiped[9] realitas bersama layar sebagai sisi pandangnya, spektrum dramatik yang sesuai pada layar. Kecerdasan inilah lompatan spesifik pemanfatannya di mana Citizen Kane berutang kepada realisme. Syukurlah, kedalaman fokus lensa telah mengembalikan Orson Welles pada kelangsungan visualnya.
Kita telah jelas melihat dengan apa unsur-unsur realitas sinema memperkaya dirinya. Tapi dari titik pandang lain, jelas juga kalau itu bergerak keluar dari realitas, atau setidaknya itu tak kian lebih mendekatkan dibanding yang dilakukan estetika klasik. Dalam batas-batasnya, disebabkan kompleksitas tekniknya, segenap jalan keluar pada alam adalah telanjang, tata Iingkungannya,[10] ruang-ruang luarnya, sinar matahari serta para pemain non-profesionalnya, Orson Welles menolak kualitas-kualitas dokumenter otentik yang tak tergantikan itu dan yang —seakan bagian dari realitas— dengan sendirinya mengukuhkan sebentuk realisme. Mari kita bandingkan Citizen Kane dan Farrebique —yang disebut terakhir adalah determinasl sistematik untuk mengeluarkan semua yang bukan material alami, tepatnya terutama merupakan alasan mengapa Rouquier gagal di bidang kesempurnaan teknik.
Maka, yang paling nyata pada seni ialah berbagi takdir bersama. Seni tak dapat menjelmakan realitas seutuhnya karena realitas sungguh-sungguh harus menghindari itu pada titik tertentu. Tak sangsi lagi, suatu perkembangan teknik yang telah diterapkan secara cerdas akan mempersekecil lubang jaring, meskipun kita dipaksa memilih antara satu jenis realitas atau lainnya. Kepekaan ini mengingatkan kita pada kepekaan retina. Pusat saraf yang mendata warna dan kekuatan cahaya tidak semuanya sama, kebasnya seorang yang terbiasa dengan nalar saling terbalik. Mahluk yang tanpa kesulitan membentuk permainan dalam gelap ini hampir pasti buta warna.
Di antara beragam realisme murni yang saling-silang namun mirip yang diwakili pada Farrebique di satu sisi dan Citizen Kane di sisi lain, terdapat keluasan bentuk bagi peluang penyatuan. Selebihnya, bagian yang kurang pada apa yang nyata, implisit di setiap pilihan realis, seringkali membiarkan seniman lewat pemakaian konvensi estetik manapun yang hendak diterapkannya ke ruang bidang yang dibiarkan hampa demi meninggikan efektivitas bentukan realitas pilihannya. Tentu ada contoh luar biasa tentang ini dalam sinema Italia masa kini. Dengan tiadanya alat-alat teknis, sutradara-sutradara Italia itu jadi punya keharusan merekam suara dan dialog seusai pembuatan filem yang sebenarnya. Hasilnya adalah realisme yang kalah. Meski begitu, sutradara-sutradara itu dibebaskan memakai kamera tanpa mikrofon, dan lalu diuntungkan oleh kejadian dimuaikannya bingkai adegan kamera dan mobilitasnya lewat peningkatan langsung koefisiensi realitas sebagai hasilnya.
Kemajuan teknik di masa depan bisa membiarkan penemuan perangkat-perangkat nyata (seperti warna dan stereoskopi) sekadar mampu melebarkan jarak antara dua kutub realis yang kini berlangsung pada ruang bidang Farrebique dan Citizen Kane. Kualitas ambilan-ambilan gambar ruang-dalam nyatanya akan terbebani pada seperangkat alat-alat yang rumit dan kaku. Beberapa patokan realitas kerap harus dikorbankan dalam upaya mencapainya.
Paisà
Bagaimana Anda tempatkan filem Italia ke dalam spektrum realis? Setelah menjajaki batas-batas geogratis sinema ini, penunjukkannya pada latar-belakang sosial demikian dalam menancap, demikian teliti dan sadar akan pilihan rerincian otentik dan signifikannya, menyisakan pada kita kini pemahaman geologi estetiknya.
Terang sekali kita mendusta diri manakala berupaya mereduksi hasil-hasil Italia masa kini pada kebiasaan tertentu yang dengan gampang mengartikan ciri-ciri pengenaan pada semua sutradara. Secara sederhana kita akan mengenali ciri-ciri itu dalam penerapan terluasnya, menyisihkan kebenaran di saat hadirnya kejadian demi memberi batas pertimbangan kita pada filem-filem yang terpenting. Karena itu pula kita mesti memilih dan mengaturnya sebab filem-filem besar Italia sedang mengalami penurunan minat hanya seputar lingkaran-lingkaran terpusat pada filem Paisà, Rossellini, karena menyimpan rahasia-rahasia paling estetiknya.
Teknik Narasi
Seperti pada novel, estetika tersembunyi dalam sinema tersingkap dalam teknik narasinya. Sebuah filem selalu dihadirkan sebagai suksesi (serangkaian) pecahan-pecahan gambaran kenyataan pada permukaan rectangular (bidang empat sisi) dalam proporsi-proporsi tertentu, penataan gambar-gambar berikut durasinya pada layar menentukan muatannya.
Sifat objektif novel modern dengan mereduksi aspek tata bahasa baku gaya pembahasaanya yang diperkecil telah begitu saja menaruh rahasia dari inti gaya.[11] Kualitas-kualitas tertentu bahasa Faulkner, Hemmingway atau Malraux tentu saja takkan hadir melalui penerjemahan, meski kualitas hakiki dari gaya bahasa mereka takkan menderita sebab gaya mereka hampir selalu serupa dengan teknik bertuturnya—penataan di dalam waktu pecahan-pecahan realitas. Gaya itu menjadi dinamika dalam prinsip narasi, agak mirip hubungan antara energi ke material atau fisika spesifik sebuah karya sebagaimana adanya. Inilah yang menyebarkan realitas-realitas fragmenter (keterpecahan) memintas spektrum estetika naratif, yang mengutubkan muatan fakta-fakta tanpa mengubah komposisi kimiawinya. Suatu Faulkner, suatu Malraux, suatu Dos Passos, masing-masing memiliki semesta personalnya sendiri yang dimaknai oleh sifat fakta-fakta yang disampaikan selain juga oleh hukum gravitasi yang menahannya di puncak perusakkan. Dengan demikian, bergunalah kiranya mencapai satu definisi gaya Italia berdasarkan skenarionya, berdasarkan asal-muasalnya, dan berdasarkan bentuk-bentuk penjelas yang mengikutinya. Sayangnya, hantu melodrama yang tampak kurang mampu dilepaskan oleh para pembuat filem Italia kadangkala merasuki tubuh untuk selanjutnya memaksa satu kebutuhan dramatik dalam adegan-adegan yang terlalu diperdekat jarak pandangnya. Tapi itu cerita lain. Yang jadi masalah ialah alur kreatif itu, suatu cara istimewa tempat situasinya menjadi hidup. Kebutuhan inheren di dalam narasi lebih biologis sifatnya ketimbang dramatik.

Still dari filem Il Bandito
Sebaran dan perkembangannya beriring dengan hiruk-pikuk kehidupan.[12] Kita tak boleh menyimpulkan bahwa metode di depan ini kurang estetik dibanding rencana awal yang lamban dan hati-hati. Namun prasangka lama bahwa waktu, uang serta pilihan-pilihan punya nilainya sendiri yang berurat-akar sehingga kita lupa mengaitkannya pada karya maupun senimannya. Van Gogh melukis ulang sepuluh kali gambar yang sama segegasnya, sementara Cézanne kembali kepada waktu melukis yang demikian itu terus-menerus sepanjang tahun. Genre-genre tertentu perlu gegas sebab karya itu dikerjakan pada ‘saatan’ (momen) panas matahari, namun pendedahannya mesti dilaksanakan dengan sentuhan besar kepastian demi ketepatan yang lebih besar lagi. Hanya dengan nilai semacam inilah filem Italia memperoleh suasana dokumenternya, suatu kewajaran yang lebih dekat pada terang ujaran daripada tulisan, pada sketsa dibanding lukisan. la menyeru ketenteraman dan kepastian pandang Rossellini, Lattuada, Vergano dan De Santis. Di tangan mereka, kamera dianugerahi kedahsyatan sinematografi yang dengan baik termaknai, antena paling peka yang membolehkan para sutradara itu dengan sekali hentak meraih tepat pencarian mereka. Dalam Il Bandito, si tahanan sepulang dari Jerman mendapati rumahnya porak-poranda. Bangunan kokoh yang dulu tegak di situ kini tinggal tumpukan batu berkepung puing-puing tembok. Kamera memperlihatkan pada kita wajah si pria. Lalu mengikuti gerak matanya, kamera berputar 360 derajat sehingga memberi kita keseluruhan pandang. Bidikan gambar panning (melingkar) ini dua kali lipat dari yang sebenarnya. Sebab pertama ialah, pada awalnya kita berjauhan dengan sang aktor karena kita melihatnya dalam tipuan secara kamera, tapi selama ambilan gambar bergerak kita lalu menjadi teridentifikasi dengannya pada titik rasa terkejut kita saat putaran 360 derajat itu telah selesai, dan kita kembali pada wajah dengan raut kengeriannya itu. Kedua, karena kecepatan bidikan gambar panning subjektif ini beragam. Dimulai dengan gerak jatuh yang lama hingga lalu menjeda, dan perlahan-Iahan mengamati tembok-tembok hangus dan hancur dengan irama yang mirip tatapan mata manusia, seolah bakal langsung teranjur oleh konsentrasinya.
Saya harus berada pada bagian tertentu dari sedikit contoh ini guna menghindari afirmasi yang benar-benar abstrak terkait apa yang saya amati, dalam artian hampir psikologis sebagai “tact/persepsi” sinematik. Ambilan gambar seperti ini dalam pengaturan gerak dinamisnya adalah milik gerak tangan membuat sketsa, menyisakan ruang dan menggurisnya di sana-sini atau menggambar sekeliling subjeknya dan melepaskannya di sana-sini. Saya memikirkan gerak lamban dalam filem dokumenter tentang Matisse yang membiarkan kita mencermatl kelangsungan dan keseragaman hentakan arabesque-nya, berbagai keraguan pada tangan sang seniman. Dalam perkara semacam itu gerak kamera menjadi penting. Kamera harus siap sedia bergerak atau diam. Ambilan-ambilan gambar yang menjelajah dan memutar jangan sampai mencirikan sosok dewa seperti yang mirip telah dihasilkan oleh kamera derek Hollywood. Seluruh ambilan gambar harus sejajar mata atau diambil dari satu cara pandang yang konkret seperti dari loteng atau jendela. Bicara mengenai teknis, segenap puisi tak terlupakan tentang kanak-kanak penunggang kuda putih pada Sciuscià, De Sica, bisa disematkan ke sudut bawah kamera yang menjadikan para penunggang itu secara tampilan tegak bagai patung penunggang kuda. Dalam Sortilege (1945), Christian Jacques punya kesulitan lebih banyak soal kuda hantunya. Tetapi segenap nilai sinematiknya tak mencegah si hewan agar beroleh tampilan prosaik dari sebuah kereta kuda yang porakporanda. Kamera Italia mengandung kualitas tertentu kamera newsreel Bell dan Howell, yakni proyeksi tangan dan mata yang nyaris merupakan bagian yang hidup dari penjelmanya dan langsung bersesuaian dengan kesadarannya.
Bell dan Howell kamera newsreel
Sementara pada fotografi, pencahayaan hanya memainkan sedikit andil ekspresifnya. Pertama, karena pencahayaan perlu bagi studio, dan kebanyakan pemfileman dilakukan di ruang luar atau di lokasi yang benar-benar nyata. Kedua, karena kerja kamera dokumenter dimaknai dalam benak kita melalui kualitas newsreel kelabunya. Akan kontradiksi lah jadinya untuk bersusah-payah dengan itu atau membuat sentuhan ulang tambahan pada kualitas plastis (mutu lentukan) suatu gaya.
Sebagaimana lalu kita demikian jauh telah mencoba perikan, gaya filem-filem Italia akan tampil secara sesuai dengan tinggi-rendah tingkat penguasaan dan keterampilan teknik maupun kepekaannya kepada keluarga mirip jurnalisme agak-sastra, kepada seni yang cerdas, menggembirakan dan hidup bahkan menyentuh, namun pada dasarnya merupakan seni yang terpencil/sendirian. Kadangkala benar hal ini kiranya, meski boleh saja dibuat peringkat-peringkat genre yang agak tinggi di dalam hirarki estetik. Maka tak adil dan tak jujurlah untuk melihat penilaian semacam itu sebagai tolok ukur terakhir atas teknik yang khusus ini. Sama kiranya pada sastra, sebuah reportase dengan etika objektivitasnya (mungkin lebih tepat menyebut etika penglihatan objektivitas) sekadar menyediakan sebuah landasan bagi estetika baru novel, menjadikan teknik para pembuat filem Italia menghasilkan filem-filem terbaiknya terutama pada Paisà dengan estetika naratifnya yang kompleks dan orisinal.[13]

Still dari filem Paisà
Paisà jelas merupakan filem pertama yang mendekatkan ingatan kita pada sekumpulan cerita pendek. Sampai saat ini kita semata-mata mengenali filem itu sebagai jalinan sketsa-sketsa —sejenis filem begundal, andai jenis ini memang ada. Dalam rangkaian itu Rossellini menyatakan pada kita, enam cerita Pembebasan Italia. Unsur kesejarahan di sini merupakan satu-satunya kesamaan dari cerita-cerita itu. Tiga di antaranya, yang pertama, keempat dan terakhir, dipetik dari masa Resistensi (Pemberontakan). Lainnya adalah episoda-episoda lucu-menyedihkan-tragis yang terjadi di perbatasan penghancuran Tentara Sekutu, Pelacuran, selundupan dan nilai-nilai Fransiskan menyediakan bahan cerita. Tidak ada kemajuan lain di luar tata kronologis cerita yang dimulai dengan mendaratnya pasukan Sekutu di Sicilia. Namun landasan sosial, historis dan kemanusiaan di situ menawarkan semua itu satu kepaduan yang memadai untuk menciptakan sekelompok yang nyata-nyata seragam dalam keberagaman di situ. Di atas segalanya, daya jangkau tiap-tiap cerita, bentuknya, muatannya, serta durasi estetikanya, untuk pertama kali mengesankan secara tepat pada klta, sebuah cerita pendek. Bagian cerita para begundal Napoli —ahli pasar gelap, penjual baju serdadu Negro yang mabuk— adalah kisahan luar-biasa Saroyan (novelis moderen dari Amerika Serikat). Cerita lainnya membuat kita terbayang Hemmingway, sedangkan satu lagi lainnya (yang pertama), Faulkner. Saya tak sekadar mengacu pada -suasana atau subjeknya, melainkan secara mendalam pada gaya. Sayangnya tak ada yang dapat menempatkan sekuen filem ke dalam tanda kutipan bak dalam suatu alinea hingga karenanya tiap paparan sastrawi sang sastrawan takkan utuh. Bagaimanapun, inilah episoda cerita terakhir yang kini mengingatkan saya pada Hemmingway dan juga pada Faulkner:
1). Segerombolan kecil kelompok politik Italia dan para serdadu Sekutu tengah dipasok makanan oleh satu keluarga nelayan yang tinggal di satu rumah dusun di jantung padang paya-paya Po (sungai Po). Setelah dibekali sekeranjang belut, mereka semua lalu pergi. Tak lama kemudian, patroli Jerman mengendus kejadian itu dan mengeksekusi para warga desa.
2). Sang opsir Amerika serta seorang partisan (pejuang, pengikut partai politik) berjalan di rawa-rawa pada saat senja. Terdengar tembakan di kejauhan. Dari senarai percakapan yang sangat tidak langsung, kita mengetahui bahwa si Jerman telah menembak sang nelayan.
3). Jasad para pria dan wanita kaku terbujur di muka pondok ternak. Sore harinya, si bayi separuh bugil merengek tiada henti.
Bahkan dengan rasa perih singkat semacam ini, penggalan cerita itu menguakkan lingkaran semesta —atau malahan, lubang-Iubang besar. Rangkaian sekumpul adegan tersebut tereduksi ke dalam tiga atau empat fragmen pendek yang dengan sendirinya sudah cukup eliptis dibandingkan dengan realitas yang telah dipaparkan. Kita lewati saja penggal pertama yang benar-benar deskriptif. Peristiwa kedua disampaikan kepada kita lewat sesuatu yang hanya diketahui oleh para partisan itu —suara tembakan di kejauhan. Yang ketiga, dihadirkan kepada kita secara bebas bersama kehadiran para partisan. Tidak juga jelas bilakah di sana terdapat saksi-saksi atas kejadian itu. Si bayi menangis di sisi jasad ayah-bundanya. Itu faktanya. Bagaimana si Jerman tahu kalau kedua orangtua itu bersalah? Bagaimana mungkin si bayi masih hidup? Untuk filem, ini bukan masalah, apalagi seluruh jalinan kelindan adegan diungkapkan dengan cara tertentu. Terlepas dari itu, pembuat filem biasanya tidak memperlihatkan semua hal kepada kita. Soal itu memang mustahil-tetapi hal-hal pilihan sutradara serta benda-benda yang diberkaskannya cenderung membentuk pola logika melalui alur pada nalar yang dengan mudahnya melangkah dari sebab menuju akibat. Teknik Rossellini ini, tak sangsi lagi memelihara rangkaian adegan hingga bisa dipahami, meskipun hal itu tidak terkait bagai rantai terikat pada roda. Nalar mesti melompati tiap-tiap antar satu kejadian adegan bagai seorang yang melompat dari batu ke batu saat menyeberangi sebuah sungai. Bisa terjadi kaki berpijak pada dua batu atau hilang keseimbangan lalu tergelincir. Akal bekerja sejalan dengan itu. lnti sebenarnya bukanlah pada batu yang mempersilakan kita melintasi sungai-sungai tanpa harus basah kaki, lebih dari itu ialah membagi satu buah Melon yang tersedia dan mempersilakan sang kepala keluarga membaginya rata. Fakta adalah fakta, dan imajinasi kita memanfaatkannya, tetapi fakta-fakta itu tidak hadir inheren bagi tujuan ini. Dalam skenario, biasanya ambilan gambar fakta-fakta (merujuk proses yang mirip pada bentuk novel klasik) muncul dari amatan kamera, dipecah, dianalisis, lalu ditempatkan kembali serempak tanpa menghilangkan sifat faktual keseluruhannya; tapi ambilan paling belakangan itu —anggaplah—terbungkus oleh abstraksi seperti sepotong bata terbungkus oleh tembok yang belum lagi ada tapi kelak akan membiak eratkan susunan-susunannya. Bagi Rossellini, fakta-fakta itu mengartikan namun bukan semacam perangkat fungsional yang sudah duluan menentukan bentuknya. Fakta-fakta itu saling menguntit, dan benak kita dipaksa mengamati kesamaannya; dengan demikian, seraya saling mengingat pada yang lain, fakta-fakta itu usai dengan saling memaknai sesuatu yang inheren di dalam dirinya sendiri serta apa yang, katakanlah, merupakan moral cerita—pesan yang tak gagal dicerna akal sebab ia dijumput dari realitas itu sendiri. Dalam episoda Florentine, si wanita melintasi kota yang masih dikuasai segerombolan Jerman dan kelompok-kelompok Fasis Italia; bertemankan pria yang juga tengah mencari anak-isterinya, dia sedang di perjalanan ke tunangannya, pemimpin bawah tanah Italia. Perhatian kamera mengikuti langkah demi langkah keduanya meskipun akan berbagi semua kesulitan yang ditemui, segala bahaya, yang bagaimana juga akan terungkapkan di tengah pengalarnan para tokohnya berikut serba-keadaan yang mesti hadapi. Sungguh, segenap kejadian dalam episoda Florensia pada perjuangan Pembebasan itu sama-sama penting. Pengalaman-pengalaman pribadi kedua individu (‘aku’) di situ melebur ke dalam pengalaman-pengalaman massa (‘aku-aku’) lainnya, sama seperti saat seseorang mencoba menuntun jalan orang lain ke tengah kerumunan untuk menemukan kembali sesuatu yang hilang dari diri orang itu. Dengan cara menciptakan suatu jalur, orang melihat di mata kerumunan itu menyisihnya bayang-bayang pertimbangan lain, hasrat-hasrat lain, bahaya-bahaya lain, mengiringi dirinya sendiri yang mungkin saja sungguh menyedihkan. Pada akhirnya secara kebetulan, si wanita mengetahui dari partisan yang terluka bila pria tercarinya itu telah tewas. Tapi pernyataan saat dia tahu kabar itu tak langsung tertuju kepadanya —melainkan menimpanya bak peluru nyasar. Kesempurnaan dialog yang mengiringi narasi di sini tak meminjam pada bentuk-bentuk klasik yang merupakan bakuan bagi cerita semacam ini.

Still dari filem Paisà
Perhatian tak pernah terpusatkan artifisial pada si tokoh wanita. Kamera tidak menciptakan pandangan subjektif secara psikologis. Kita berbagi keharuan lebih besar pada tokoh utama karena telah memudahkan kita memahami perasaan mereka; di samping karena aspek keharuan pada episoda ini tidak diturunkan dari fakta bahwa si wanita sudah kehilangan pria tercintanya, melainkan dari ruang istimewa genggaman drama ini di antara beribu-ribu lainnya terlepas dari —meski tetap juga bagian— keutuhan drama Pembebasan Florensia. Kamera, yang seolah ingin memberi laporan pandangan mata terbatas dalam mengikuti pencarian si wanita terhadap prianya dan menyeret beban tersendiri pada kita dalam memahami perasaannya dan berbagi duka.
Pada episoda akhir mengesankan tentang para partisan yang terkepung di padang paya-paya Po, gambar membentang ke keluasan cakrawala hingga cukup tinggi untuk menyembunyikan si pria merangkak ke lambung sampan dan daur ombak menghantam pohonan, yang kesemua itu mengikatkan lokasi sama pentingnya dengan manusia. Andil dramatik yang ditampilkan melalui rawa-rawa ini banyak meminjam kualitas-kualitas terencana di dalam fotografi. Maka cakrawala di situ selalu berada pada ketinggian yang sama. Membiarkan kesamaan proporsi antara perairan dan langit di setiap ambilan gambarnya, terungkaplah salah satu ciri hakiki panorama ini. Di bawah kondisi-kondisi kebutuhan pada layar, kesamaannya itulah yang berasal dari lubuk rasa pengalaman manusia yang tinggal di antara langit dan perairan, dan hidup dalam belas kasih alun terkucil (infinitesimal) dihubungkan dengan cakrawala. Ini menunjukkan betapa detil raut wajah dapat mengungkapkan ruang-ruang luar pada kamera di tangan sang sinematograf Paisà.

Still dari filem Paisà
Satuan naratif sinematik pada Paisà bukanlah ‘ambilan gambar’ yakni pandangan abstrak tentang sebuah realitas yang sedang dianalisis, melainkan ‘fakta’. Satu kepingan realitas konkret pada dirinya sendiri tergandakan dan sepenuhnya mendua di mana arti hanya muncul setelah fakta, berbaik pada tekanan fakta-fakta lain spasial/terjeda di mana akal menguatkan kaitan-kaitan tertentunya. Tak sangsi, sang sutradara telah memilih ‘fakta-fakta’ ini secara teliti seraya di saat itu juga menghargai integritas faktualnya. Bidikan gambar-dekat gagang pintu yang teracu pada adegan awal, sekurangnya adalah sebuah fakta ketimbang sebuah perlambang yang membawakan bantuan arbitrer (kesewenangan) melalui kamera, dan tak lebih bebas semantik (tanda) ketimbang preposisi pada sebaris kalimat. Kebalikannya dari itu, dibenarkan atas upaya-upaya dan kematian para petani.
Tetapi sifat dari ‘fakta-fakta gambar’ tak sekadar memelihara fakta-fakta gambar lain, hubungan-hubungan yang dibentuk oleh akal. Semuanya ini ada dalam terpahaminya benda-benda sentrifugal (efek putaran) pada gambar-gambar —yakni semua yang memungkinkan terciptanya narasi. Tiap-tiap gambar dengan sendirinya hanyalah satu kepingan realitas yang tampak sebelum arti apapun, sehingga bidang sepenuh layar harus menjelaskan tingkat ke-konkritan yang sama. Kembali di sini kita memegang kebalikan dari layar ‘gagang pintu’ semacam ini, pada warna enamel-nya, lekatan debu sekujurnya, kilauan logamnya, tampilan kacau-balau yang hanya terdiri dari begitu banyak fakta tanpa guna, sungguh benalu-benalu abstraksi yang pantas disingkirkan.

Still dari filem Paisà
Pada Paisà (saya ulangi bahwa yang saya maksud di sini seluruh filem Italia dalam beragam tingkatan) bidikan gambar-dekat gagang pintu itu dapat diganti tanpa kehilangan kualitas tak biasanya yang merupakan bagian darinya, melalui ‘fakta gambar’ sebuah pintu yang ciri-ciri konkretnya akan sama saja terlihat. Untuk alasan itu pulalah para pemain takkan terpikir untuk memisahkan penampilan mereka dari dekorasi dan dari penampilan rekan main lainnya. Manusia sendiri sekadar sepotong fakta di antara yang lain-lain, bagi siapa kepongahan akan kedudukan tak semestinya a priori diserahkan. Itu sebabnya para pembuat filem Italia sendiri mengenal betul bagaimana caranya berhasil membidik gambar bis-bis, truk atau kereta, karena panorama ini tepatnya dipadukan demi terciptanya penghayatan mendalam pada bagan kerja yang mereka kenali betul cara memperlihatkan suatu adegan tanpa memisahkannya dari isi serta tanpa menghilangkan kualitas unik manusia yang merupakan kesatupaduannya. Kerincian dan kelenturan gerak di dalam ruang-ruang tak beraturan ini, kewajaran tingkah-Iaku tiap-tiap orang di tempat ambilan gambar, menjadikan pembuatan gambar-gambar ini saat-saat menakjubkan yang luar biasa bagi sinema Italia.
Realisme Sinema ltalia dan Teknik Novel Amerika
Tak tertulisnya samasekali pendataan filem, mungkin saja terjadi berlawanan dengan kejelasan pemahaman atas apa-apa yang sudah saya tuliskan sejauh ini. Saya telah tiba pada titik pencirian yang sama antara gaya Rossellini pada Paisà dengan Orson Welles pada Citizen Kane. Lewat pertentangan diametrik jelujur/jalinan teknik masing-masing hingga skenario dengan prakira pendekatannya yang sama kepada realitas —yaitu kedalaman fokus Welles serta kecenderungan atas realitas pada Rossellini. Pada keduanya, kita mendapati ketergantungan yang sama dari pemerannya yang berkaitan dengan tata letakan, kesamaan akting realistiknya, yang diperlukan pada setiap pemeran dalam segala kepentingan dramatik adegan mereka. Meski gaya keduanya demikian berbeda, pada dasarnya tetap lebih baik narasi mengkuti pola yang sama pada Citizen Kane atau Paisà.

Still dari filem Citizen Kane
Singkatnya, meski mereka berdua memakai teknik-teknik bebas tanpa sedikitpun kemungkinan saling pengaruh penyutradaraan di antara keduanya, dengan temperaman masing-masing yang tak bisa saling dipadankan, Rossellini dan Welles —dengan serba maksud dan tujuannya— memiliki kesamaan dasar objektif estetika, yakni konsep estetik realisme yang sama.
Saya punya waktu memadai kala menonton filemnya guna membandingkan narasi Paisà dengan sejumlah novelis dan para cerpenis moderen. Apalagi, kemiripan antara teknik Orson Welles dengan novel Amerika terutama karya Dos Passos (John Roderigo Dos Passos, Amerika Serikat), bagi saya kini cukup terang untuk menjelaskan tesis saya. Estetika sinema Italia, setidaknya dalam pengejawantahan paling rumitnya dan dalam karya seorang sutradara yang sangat sadar akan medium seperti halnya Rossellini, begitu setara dengan filem novel Amerika.
Mari kita pahami dengan jelas bila di sini kita berhadapan dengan sesuatu yang berlainan daripada adaptasi biasa. Pada kenyataannya, Hollywood tak henti-hentinya mengadaptasi novel-novel Amerlka untuk difilemkan. Kita tahu apa yang dilakukan Sam Wood dengan For Whom the Bell Tolls [novel “Demi Siapa Genta Bergema”-nya Hemmingway]. Pada dasarnya, keinginannya ialah mengisahkan kembali alur cerita. Bahkan meskipun dia sangat ketat pada aslinya, kalimat demi kalimat, dia tidak akan —untuk bicara apa adanya— memindahkan apapun dari novel ke dalam layar. Bisa dihitung jari satu tangan, filem-filem yang berhasil menerjemahkan gaya novel ke dalam gambar-gambar, dan dengan demikian saya maksudkan bahan utama narasi, hukum gravitasi yang mengatur tata fakta-fakta, pada Faulkner, Hemmingway, dan Dos Passos. Kita mesti menanti Orson Welles untuk menunjukkan seperti apakah kiranya sinema novel Amerika itu.[14]

Still dari filem For Whom the Bell Tolls
Maka kemudian, sementara Hollywood mengadaptasi wiracarita demi wiracarita, serentak itu pula ia bergeser menjauh dari semangat sastrawi ini, pada Italia lah tentu yang dengan mudah mencegah serba gagasan tentang pembebasan dan peniruan terencana, tempat sinema sastra Amerika menjadi nyata. Tidak disangsikan, kita tak bisa merendahkan ketenaran novelis Amerika di Italia, tempat karya-karya mereka diterjemahkan lalu teradaptasi dengan sendirinya jauh sebelum di Prancis, dengan misalnya pengaruh Saroyan pada Vittorini (Elio Vittorini, Italia) yang bukan lagi rahasia. Sertamerta akan saya petikkan dengan mengacu pada kaitan sebab-akibat yang tak menentu ini, rasa sejawat luar biasa dua peradaban ini sebagaimana terungkapkan dalam pendudukan Sekutu. Sang G.I. (General lnfantery = Jenderal lnfanteri) merasa seolah di rumah sendiri begitu sampai di Italia, dan si paisan langsung punya saling pengertian dengan sang G.I. hitam maupun putih. Maraknya pasar gelap dan di mana-mana muncul prostitusi ke manapun serdadu Amerika pergi, tak sekadar contoh kecil yang meyakinkan hubungan timbal-balik kedua peradaban. Bukan tanpa maksud, bila serdadu-serdadu Amerika merupakan sosok-sosok penting di banyak filem terbaru Italia, tempat mereka lantang bersuara layaknya di kandang sendiri.
Meski sudah terbuka sejumlah jalan oleh sastra dan pendudukan, fenomena ini tak dapat diterangkan pada tataran ini saja. Filem-filem Amerika kini dibuat di Italia, meski tak pernah filem Italia semacam langsung menjadi lebih Italia. Sosok-sosok acuan yang saya sebutkan, dengan agak bertikai, telah mengesampingkan kemiripan, misalnya ‘cerita’ Italia, commedia dell’arte dan teknik fresco (Iukisan dinding). Lebih dari saling pengaruh, ini adalah harmonia antara sinema dan sastra berdasarkan pada pendalaman data-data estetiknya, pada kesamaan konsepsinya antara seni dan realitas. Cukup lama sudah sejak novel moderen menciptakan revolusi realismenya karena penggabungan paham perilakunya, suatu teknik kewartawan berikut etika kekerasan. Jauh dari sinema yang memiliki dampak sekecil apapun pada evolusi ini sebagaimana kini kukuh tergenggam, filem seperti Paisà membuktikan bahwa sinema berada duapuluh tahun di belakang novel masa kini. Sinema Italia tidaklah kecil nilainya manakala sanggup menemukan kesetaraan sinematik yang sejati bagi revolusi sasterawi terpenting pada zaman kita.
André Bazin (1918-1958)
Belajar sastra di École Normale Supérieure de Saint-Cloud, Prancis. Pada tahun 1947 mendirikan La Revue du Cinéma yang kemudian menjadi Les Cahiers du Cinéma bersama dengan Jacques Doniol-Valcoze tahun 1950. Seringkali berseberangan dengan rekannya François Truffaut serta berbagai penulis lainnya di Les Cahiers. Sampai saat kematiannya dia tidak mampu menyelesaikan sebuah karya tentang Renoir.
Catatan Kaki
[1] Centro Sperimentale di Cinematografia: pusat pendidikan sinematografi yang berdiri pada tahun 1935 di masa Mussolini. Sedangkan Institu des Hautes Etudes Cinematographiques, pendidikan tinggi sinematografi didirikan di Paris pada 1943.
[2] Filem karya sutradara perintis dari Prancis, Jean Renoir, yang besar dan tak terbantahkan pengaruhnya poda sinema Italia. Ia hanya dapat dibandingkan dalam hal segenap pendekatannya dengan sutradara lain filem Prancis, René Clair.
[3] Filem Scipione Africanus (1937) adalah sebuah filem sejarah yang bercerita tentang Fablius Cornelius Scipio dari diangkatnya dia sebagai diktator hingga kekalahannya atas Hannibal pada Perang Zama pada tahun 202 SM. Filem dibiayai oleh Benito Mussolini untuk propaganda fasisme di Afrika Utara. Satu devisi tentara Italia dikerahkan untuk menjadi figuran pada filem ini.
[4] Marcel Carne adalah sutradara filem Prancis yang sering digolongkan pada kelompok sutradara Fantastic Tragedy. Bersama penyair Jacques Prévert, ia mengembangkan realisme puitik. Salah satu filem terbaiknya adalah Les Enfants du paradis (Children of Paradise, 1945) yang pada tahun 1990an mendapatkan penghargaan Best French Film of the Century dari para kritikus filem Prancis. Pada tahun 1950an, ia mulai meredup. Para kritikus Cahiers du Cinéma mengkritik habis Carme dan mengatakan ia hanya dimanfaatkan oleh Prévert. Filem terakhirnya diproduksi pada tahun 1976, La Bible.
[5] Pengarang drama The Barber of Seville dan Figaro, di mana yang terakhir menyingkap kemampuan Beaumarchais mengkritik masyarakat Prancis di saat-saat akhir ancient regime (rezim kuno) secara cerdas dan satir. Di malam Perang Dunia II, Jean Renoir secara sadar dan berhasil menghubungkan Beaumorchais dalam filemnya, La Regie du jeu.
[6] Saya amat terbuka bahwa kecerdasan andil politik lebih-kurang ditutupi secara sadar di bawah sumbangsih komunikatif ini. Kelak bisa saja terjadi, sang pastor dalam Roma Città Aperta dan si Komunis bekas anggota Pemberontak tidak seiring-sejalan lagi. Bisa saja terjadi, sinema Italia segera menjadi politis dan partisan. Pada semuanya ltu, bisa saja ada sekian kecll dusta yang disembunyikan di suatu tempat. Kecerdasan filem Paisà yang pro-Amerika itu ambilan gambarnya oIeh kaum Kristen Demokrat dan Komunis. Namun Ini bukanlah suatu kebodohan, sekadar soal kepekaan menerima karya sebaga iadanya. Saat ini sinema Italia iebih sosiologis ketimbang politis. Dengan ini saya artikan bahwa realitas-realitas sosial konkriet itu sebagai kemiskinan, di mana pasar gelap, pemerintahan, prostitusi dan pengangguran tak tampak diberi tempat dalam kesadaran umum nilai-nilai a priori poIitik. Filem-filem Italia jarang mengatakan pada kita partai politik sang sutradara maupun kepada siapa ia bermaksud menyanjungnya. Kondisi ini tak sangsi lagi diturunkan dari temperamen etnik, tapi juga diturunkan dari situasi politik Italia serta apa yang menjadi kebiasaan dalam partai Komunis di semenanjung tersebut. Memisahkan asosiasi poIitiknya, sinema humanisme revolusioner ini memiliki sumber-sumber yang setara dengan pertimbangan tertentu bagi individu; massa itu tidak lebih dari sesuatu yang jarang dipertimbangkan sebagai daya sosial positif. Massa lazim disebut-sebut dengan niat menunjukkan watak perusak dan buruk mereka vis-à-vis tokoh-tokoh utama: tema seorang manusia di tengah kerumunan (aku-massa). Dari pijak pandangan lni dua filem penting terbaru Italia, Caccia Tragica (de Santis, 1947) dan Il Sole Sorge Ancora (Aldo Vergano, 1946), merupakan pengecualian yang signifikan, mungkin menandakan satu kecenderungan baru.
Sutradara De Santis yang bekerja erat dengan Vergano sebagai asistennya di Il sofe sorge ancora adalah satu-satunya sutradara yang pemah mengambil sekelompok orang, sebuah kolektlf, sebagai protagonis drama.
[7] Awalnya adalah penyanyi terkenal di Trastevere –Roma, tempat yang sepadan Montmartre -Paris atou Cockney -London.
[8] Bid’ah oleh karena realitas tidak dicerminkan sebagaimana mestinya dilakukan sinema. Cukup aneh Eisenstein dan Bazin seiya mengecam ekspresionisme meski gagasan realisme sinematik keduanya tak sepenuhnya sama. Eisenstein mengatakan, “Aku bukan seorang realis, aku seorang materialis: (catatan Hugh Gray, penerjemah edisi bahasa Inggris atas esai André Bazin)
[9] Prisma enam bidangyang tiap bentuk permukaannya seperti berlian. Anggapannya, di sini Bazin berharap menawarkan metafora konkret bagi kansepsinya soal ruang filem sebagai entitas (wujud) paling nyata dengan batasan-batasan yang bisa divisualisasikan secara ketat.
[10] Masalahnya merumit saat kita berhadapan dengan penataan kota. Di sini orang-orang Italia berpihak pada nilai kegunaan mutlak. Kota Italia, kuno atau moderen, luar biasa fotogenik. Karena keantikannya, perencanaan kota Italia tetaplah teaterikal dan dekoratif. Kehidupan kotanya adalah hiasan, sebuah commedia dell’arte di mana panggung orang-orang Italia menjadi tempat kesenangan sendiri. Bahkan wilayah-wilayah termiskin kotanya, kelompok perumahan bak karangnya, untunglah teras-teras beserta balkon-balkonnya, menawarkan banyak kemungkinan luar biasa bagi mata. Pekarangannya merupakan rangkalan gaya zaman Elizabeth di mana pertunjukan dilihat dari bawah, dan para penonton di galeri menjadi aktor-aktor drama komedi dokumenter puitis yang dipertunjukkan di Venezia seluruhnya berisikan dari satu kelompokan ambilan-ambilan gambar pekarangan-pekarangan. Apa lagi yang bisa Anda katakan saat fasad-fasad teatrikal palazzi menggabungkan kerja efek-efek itu bersama arsitektur mirip panggung dari rumah-rumah orang miskin? Tambahkan di sini sinar mentari dan tak adanya mendung (musuh utama pengambilan gambar luar ruang), maka Anda bisa terangkan mengapa ruang-ruang luar urban dalam filem-filem Italia lebih menakjubkan dibanding yang lain.
[11] Dalam L’Etranger (Orang Asing) Camus, misalnya, Sartre dengan jelas menunjukkan hubungan antara metafisika sang pengarang dengan penggunaan berulang aturan sasterawi lama sebagai sekalimat modal singular (tunggal) kemiskinan.
[12] Hampir semua ucapan terimakasih setiap filem Italia tertulis di bawah tajuk lusinan nama baik “skenario”, ini mendesakkan bukti adanya kolaborasi yang tak perlu terlalu ditekankan. Ia dimaksudkan sebagai tawaran terbuka jaminan politis bagi para produser. Biasanya memuat seorang Kristen Demokrat dan seorang Komunis (sama seperti dalam filemnya, terdapat seorang Marixs dan seorang pendeta); penulis naskah yang ketiga punya reputasi bagi konstruksi cerita; yang keempat, pria pendiam; kelima, karena seorang penulis dialog yang bagus; keenam, karena dia punya perasaan mendalam pada kehidupan. Alhasil tidak lebih baik atau lebih buruk ketimbang bila cuma ada satu penulis naskah; tetapi gagasan Italia akan satu skenario yang cocok dengan konsep paternitas kolektif mereka didasarkan pada kontribusi gagasan masing-masing orang tanpa adanya kewajiban dalam peranan apapun yang akan dipakai oleh sang sutradara. Jauh dari metode himpunan para penulis skenario Amerika, kesalingtergantungan yang improvisasif ini mirip seperti pada commedio dell’arte atau jazz.
[13] Pada titik ini saya takkan mengarah pada alasan historis tentang muasal atau lataran ‘novel reportase’ abad kesembilan belas. Apalagi novel-novel Stendhal (nama lain; Marie-Henri Beyle, Prancis) atau para naturalis lainnya terkait dengan keterbukaan ekstremitas dan kecermatan pengamatan, bukannya dengan apa yang dengan tepat disebut objektivitas. Fakta: fakta itu sendiri belum memerlukan otonomi ontologis semacam ini, yang darinya terciptalah serangkaian monada yang terjaga, dan secara ketat dibatasi sendiri oleh kehadirannya.
[14] Pada beberapa kejadian, sinema di satu sisi telah sedemikian dekat dengan kebenaran-kebenaran ini, contohnya dalam hal Feuillade maupun Stroheim. Yang terbaru, Malraux sejelasnya memahami kaitan antara gaya novel tertentu dengan narasi filem. Akhirnya, secara naluriah dan berkat kecerdasannya, Renoir sudah menerapkan itu dalam filem La RegIe du jeu-nya, saripati gagasan kedalaman fokus dan presentasi simultan seluruh pemeran di dalam filem. la telah menjelaskan ini datam satu artikel profetik (visioner) pada 1938 di jumal Point.


Sampul depan dan belakang Footage Internal No. 7