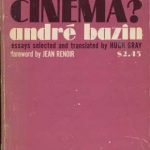(Pada 19 Januari–20 Februari 2012, Mahardika Yudha (Diki), salah satu redaktur Jurnal Footage mendapat kesempatan berkunjung ke Tokyo, Jepang dalam rangka Program Jenesys oleh Japan Foundation. Untuk ini, kami akan menampilkan seri laporan dan tulisan Diki selama dia berada di Jepang. Selamat membaca.)
Musim dingin di Jepang. Temperatur berkisar 6° sampai -4° C. Sebuah pengumuman berbahasa Jepang tanda masuk kerja terdengar di jalan-jalan kota Tokyo pada pukul 9 pagi. Semua orang berjalan kaki dengan cepat. Berpakaian tebal. Berjejal menuju subway—sistem angkutan cepat bawah tanah dikenal juga dengan Metro, Underground, T-Bane, MRT (Mass Rapid Transit), Tube, atau U-Bahn—. Walau keseharian mereka cukup ‘seni media’, karena hampir seluruh elemen hidupnya benar-benar ditunjang oleh teknologi, namun berjalan kaki telah menjadi budaya tersendiri yang telah berjalan ribuan tahun. Penciptaan alur sirkulasi kereta bawah, baik untuk kereta itu sendiri ataupun para penumpangnya telah terbentuk. Lajur-lajur yang diciptakan dalam sistem sirkulasi itu betul-betul dibuat dengan perhitungan yang matang dan tepat, bahkan cenderung matematis. Seperti lajur-lajur sistem dalam komputer. Sistem yang tidak memungkinkan bagi siapapun untuk melanggar karena akan menciptakan lubang atau scratch yang akan merugikan orang lain. Subway merupakan salah satu sistem yang merefleksikan bagaimana hidup mereka sangat teknologis. Pergerakan manusia-manusia itu berhenti sesaat di dalam kereta subway. Mereka serentak membuka telepon genggam ataupun membaca buku. Aneka tulisan kanji menempel di dinding-dinding dalam kereta subway. Bagi saya yang tak mengerti bahasa Jepang itu, tulisan-tulisan itu hanya menjadi sebuah gambar. Menulis kanji berarti juga menggambar. Mereka memiliki sejarah huruf yang visual sekali. Dengan kata lain, mereka memahami isi dari dunia ini sebetulnya bukan dari teks dalam artian tertulis, tetapi memaknai sebuah gambar. Terbukti, beberapa kali saya berbicara dalam Bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, sambil memperlihatkan hal yang saya inginkan dan mereka pun cepat sekali mengerti.

Tradisi gambar dan teknologi ini kemudian saya temui lagi di sebuah pameran tetap non-koleksi dari National Film Center Tokyo tentang perkembangan sinema Jepang sejak masa Toraku Kameya (Magic Lantern) hingga animasi yang dikatakan sebagai sinema terakhir di Jepang. Pameran Nihon Eiga: The History of Japanese Film telah berlangsung hampir setahun, yaitu sejak 8 Februari 2011. Pameran yang diselenggarakan oleh lembaga film negara pertama di Jepang (sejak 1952) ini dikemas berdasarkan kronologis perkembangan teknologi sinema. Sekitar abad ke-18, proyektor Lentera Ajaib produksi Lapierre hadir di Jepang. Dibawa oleh bangsa Belanda. Pertunjukannya sendiri dinamakan utsushi-e yang menggunakan suara-suara seperti drum, shamisen (seperti gitar atau banjo dengan tiga senar) dan nyanyian yang bercerita seperti joruri atau gidayu. Dalam kuratorialnya, utsushi-e dikatakan sebagai pengalaman pertama masyarakat Jepang terhadap media visual dengan teknik pengisahan melalui teknologi. Pertunjukan utsushi-e merupakan pengembangan dari kamishibai yang sudah terlebih dahulu ada sejak abad ke-12 yang juga menghadirkan pengalaman sinematik. Perbedaannya terdapat pada teknologi yang digunakannya saja. Kamishibai dilakukan dengan cara tradisional (manual) melalui gambar-gambar tangan yang dinarasikan oleh dalangnya. Di sisi kiri dari lokasi Toraku Kameya, terdapat televisi 14 inci yang menampilkan 29 rekaman Lumière Bersaudara di Jepang yang diproduksi rentang 1896-1897. Tak jauh dari televisi itu, terpasanglah poster pemutaran Vitascope Edison di Kinkikan Theater pada 6 Maret 1897. Di 1886, Vitascope Edison diperkenalkan di Jepang melalui seorang projectionist Daniel Krouse yang diundang oleh Arai Shokai dan Cinematograph Lumiere juga dipresentasikan pada tahun yang sama. Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang pertama kali memproduksi filem. Para sejarawan yakin, bahwa filem pertama Jepang dibuat pada tahun 1897. Sebuah dokumentasi Geisha yang menari dan kehidupan di jalan-jalan Tokyo. Filem cerita kemudian lahir pada 1898, seperti cerita penangkapan perampok dan komedi tentang seorang pria yang tidur di bangku taman.1 Setahun kemudian, sebuah pertunjukan Kabuki berjudul Game of Autumn Leaves yang direkam oleh Tsunekichi Shibata juga diproduksi.

Sebuah ilustrasi pertunjukan dengan Vitaskop di Teater Kabuki Kinkikan, terlihat jelas penonton terpisah dengan kelas duduk antara lelaki, perempuan dan anak-anak.
Utsushi-e
Filem Lumière

Pertunjukan Minwa za Group di The University of Chicago

Pertunjukan Minwa za Group di The University of Chicago
Pameran yang memadukan antara berbagai objek baik materi cetak seperti poster, selebaran, tiket, coret-coretan sutradara ataupun skenario asli, foto dokumentasi ataupun profil, hingga teknologi yang telah digunakan dalam sejarah besar sinema Jepang, seperti Pathe Professional Camera buatan Prancis, Le Parvo Camera (Model L), hingga kamera Askania yang digunakan Leni Riefenstahl untuk membuat filem dokumenter Olympia (1938) dalam Olimpiade Berlin 1938. Tak hanya itu, beberapa potongan seluloid yang direkam oleh Lumière Bersaudara dan diberikan kepada Shigeyoshi Suzuki juga tertampil.

Kiri: Suasana pameran, Kanan: Kamera Le Parvo
Olympia (1938), Leni Riefenstahl
Objek-objek yang tertampil instalatif itu semakin hidup ketika hadirnya footage, newsreel, dan potongan-potongan filem fiksi yang mewakili masanya. Potongan filem dokumenter ekspedisi ke Antartika pertama kali oleh negara Jepang, Nihon Nankyoku Tanken, yang dipimpin oleh Lt. Nobu Shirase pada 1910-1912 yang pertama kali dipertunjukan di Kokugikan pada Juni 1912. Filem ini diproduksi perusahaan Jepang M. Path yang dipimpin oleh Umeya Shokichi yang merupakan satu dari sekian banyak dokumenter yang diproduksi Jepang, dan mengilustrasikan tentang bagaimana filem dokumenter menjadi alat politik. Politikus Osumi Shigenobu menjadi penyandang dana dalam ekspedisi itu.2 Ada pula rekaman kebakaran besar saat terjadi gempa bumi Kanto di tahun 1923 yang diputar hanya 6 menit.
Dokumenter Gempa Kanto
Pameran ini semakin terasa sebagai pameran seni media ketika instalasi kinetoskop yang memutar filem-filem pertama Jepang dalam format seluloid yang membelah ruang pameran menjadi dua. Suara sakral putaran mesin proyektor seluloid yang hanya diputar delapan menit setiap 30 menit sekali itu cukup memberi perhatian para pengunjung. Filem-filem yang diputar antara lain Nio no Ukisu (1900), Hototogisu (tanpa tahun(tt)), Ai Aigasa (tt), Shoes (1916), Gen’ei no onna (1920), Gubi Jinso (1921). Pemutaran seluloid dalam ruang pamer ini juga memberikan semacam pernyataan kepada publik tentang pengarsipan filem yang dilakukan oleh National Film Center, tentang bagaimana benda-benda bersejarah yang telah berusia 100 tahun itu masih bisa ditayangkan.
Perjalanan sinema Jepang yang ditampilkan semakin menjadi luar biasa ketika arsip filem 3 menit (durasi sebenarnya 8 menit) dari pelopor filem eksperimental dan animasi Jepang Shigeji Ogino (1899-1991), En Expression yang dibuatnya pada 1935 dapat ditonton oleh pengunjung. Filem eksperimental yang bermain warna merah dan hijau dengan teknik Kinemacolor 32 fps menggunakan seluloid 9,5 mm itu merupakan pengembangan dari teknik pewarnaan yang mulai marak digunakan pula di Barat di tahun 30an. Seperti filem Legong: Dance of The Virgins (1935) buatan Henri de La Falaise yang hanya menggunakan dua warna.
Hampir keseluruhan periode perkembangan sinema Jepang diwakili melalui kehadiran teknologi (objek-objek benda dan filem). Periode sinema Jepang mulai dari filem bisu, realisme tahun 30an yang menginspirasi gerakan Neorealisme Italia (terutama untuk karya Yasujiro Ozu, An Inn in Tokyo (Tokyo no yado), 1935), periode filem propaganda yang marak di tahun 1940-1945, masa keemasan sinema Jepang di periode 1950-1960an melalui Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, dan Yasujiro Ozu. Lalu generasi Filem Merah Muda (Pink Generation) Nagisa Oshima yang meledak di tahun 1970an, hingga periode animasi yang dewasa ini semakin gencar di Jepang menjadi penutup lini masa pameran ini.

Magic Lantern
[1][2] Tadao Sato, An Introduction to Early Japanese Cinema, http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/reruns/rr0499/PUerr6.htm
[/tab_item]
[tab_item title=”EN”]
(Temporarily available only in Bahasa Indonesia)
[/tab_item]
[/tab]