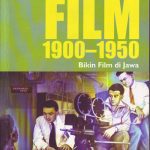Waktu akan tetap memperhatikannya (Konfiden-red.), konsistensi dan keseriusannya akan teruji, sejauhmana bisa bertahan dengan visi yang ada. Demikian juga sejauhmana jika terjadi perkembangan yang membuat para aktivisnya bisa bertahan pada visi dasar? Karena di Indonesia ini masih dominan pada pandangan orang yang melihat industri film yang lebih menitikberatkan pada produksi film panjang yang diproyeksikan di gedung.
–Gotot Prakosa, Film Independen di Tangan Konfiden, (Ketika Film Pendek Bersosialisasi, 2001)

Ada yang baru dalam perhelatan festival filem pendek Konfiden tahun ini, yaitu mencoba memberikan alternatif tontonan dengan metode kuratorial yang cukup baik. Program dibagi dengan konsep beberapa fokus yang menarik seperti program khusus Lagu Gambar Gerak, Bahasa yang Terlampau Baku, Sutradara yang Bukan Tuhan, Pijakan yang Tidak Kokoh dan Film Pendek Sinema Besar. Selain itu ada program kompetisi yang dipilah dalam tiga tema besar yaitu; Sejarah, Waktu dan Kenangan. Filem berjudul Anak-anak Lumpur karya Danial Rifki meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu Penghargaan Film Fiksi Terbaik dan Penghargaan Konfiden.
Pada 21 November 2009, saya sempatkan untuk menonton salah satu program Festival Film Pendek Konfiden 2009 di Kineforum Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kesan saya, festival ini masih punya harapan yang sangat besar untuk menjadi barometer perkembangan filem pendek di Indonesia. Dalam katalog tergambarkan, Konfiden meramu program dengan spesifikasi kuratorial yang cukup baik meski jumlah peserta dan karya yang layak untuk ikut dalam program kompetisi turun drastis. Namun, menonton salah satu program kompetisi di festival ini, saya berharap ajang ini akan lebih “berbunyi” dari gelaran sebelumnya.

Salah satu program kompetisi yang sempat saya lihat itu adalah Kompetisi 1: Sejarah, menampilkan tiga karya, Fronteira karya Emil Haradi (Produksi FFTV-IKJ), Sabotase karya Hadrah Daeng Ratu (Produksi FFTV-IKJ) dan Tan Malaka karya Erik Wirawan (Produksi FFTV-IKJ). Pada dua karya pertama, kita perlu berharap banyak kepada dua sutradara muda ini. Emil Haradi bermain dalam bahasa sinema yang cukup baik dalam menampilkan situasi dua kutub manusia yang berbeda posisi. Sutradara berhasil membangun ketegangan pada penonton dalam situasi terjepitnya dua tokoh tentara (Indonesia dan Timor Leste) di ladang ranjau. Pengembalian sisi manusia dalam tubuh para tentara dihadirkan oleh sutradara dalam dialog-dialog yang “cukup” menyengat. Namun, kekurangan masih tetap terlihat di sana-sini. Salah satunya kemampuan aktor yang masih kurang bisa mengekplorasi ekspresi. Dialog-dialog yang hadir masih terasa “klise” dalam konteks persoalan ketegangan Indonesia dan Timor Leste. Pada filem Sabotase, saya melihat Hadrah Daeng Ratu adalah salah satu calon sutradara andal. Filem ini berhasil membuka tabir “eksotisme” kemiskinan dalam bahasa filem yang sangat lugas. Sabotase dibuka dengan adegan ambilan gambar panjang—yang mendeskripsikan situasi salah satu daerah kumuh di Jakarta. Filem ini tidak memberikan pretensi yang menghakimi antara penguasa dan legalitas pemukim yang tinggal di daerah kumuh itu. Para aktor/aktris hadir sebagai potret lugas situasi masyarakat yang termarginalkan dalam perkembangan kota-kota di Indonesia. Pada filem ketiga, Tan Malaka karya Erik Wirawan, menurut saya sutradara masih harus belajar banyak tentang representasi bahasa filem dari seorang tokoh penting negeri ini. Dalam filem ini, Tan Malaka digambarkan seperti seorang yang kerjanya marah melulu. Selalu terkecewakan. Padahal kita tahu, yang paling tajam dari seorang tokoh sekelas Tan Malaka adalah kata-katanya (tulisannya). Saya tidak percaya dengan gambaran “keras” dalam filem Erik yang melihat Tan Malaka terlalu artifisial. Karena seorang tokoh dengan intelektual seperti Tan Malaka tidak akan menarik urat leher untuk menggambarkan kemarahannya. Ia adalah intelektual sejati, dan juga seorang pemusik ulung (pemain celo) yang menurut saya sangat halus dalam kesehariannya. Yang paling cukup mengecewakan saya dalam filem ini adalah penggambaran perjuangan Tan Malaka yang lebih ke “fisik”. Persis seperti stereotipe Orde Baru yang menggambarkan seorang pahlawan adalah orang yang berjuang dengan “angkat senjata.”



Terlepas dari kesan tiga karya di atas, saya bisa melihat Konfiden mulai memposisikan diri untuk dapat menjadikan festival filem pendek ini (yang dulunya terbesar di Indonesia), menjadi sebuah gerakan filem yang menyentuh ranah politik kultural yang selama ini terabaikan. Sebelumnya, kita tahu seremoni filem pendek ini sangat mempengaruhi generasi muda untuk memproduksi filem pendek di berbagai daerah. Namun, dalam rentang sepuluh tahun terakhir dengan banyaknya ajang serupa yang ada di berbagai daerah, festival filem pendek ini mulai tergerus dari berbagai sisi. Jumlah partisipan, kualitas karya, hingga jumlah penonton yang datang di ajang ini berkurang. Saya masih ingat beberapa tahun lalu saat hadir dalam festival filem pendek ini, berbagai komunitas dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk hadir di festival. Liputan media begitu besar, hingga festival ini menjadi barometer bagi para pembuat filem muda sebagai ajang aktualisasi diri dan karyanya.
Dari pengalaman di atas, kita bisa berpendapat (yang mungkin bisa diperdebatkan) bahwa; Festival Film Pendek Konfiden adalah yang paling berjasa membangun generasi baru sinema Indonesia. Jasa ini dapat dilihat dari bagaimana festival ini membentuk animo generasi muda untuk bangga pada karya mereka sendiri (karya anak bangsa) yang sebelumnya didominasi oleh filem-filem asing. Kebanggaan pada karya sendiri inilah yang menjadi modal besar dalam membangun industri filem Indonesia saat ini. Bagi saya, salah besar kalau Jero Wacik (pemerintah-red.) merasa bangga bahwa hidupnya dunia perfileman Indonesia saat ini atas jasa pemerintah. Pemerintah tidak sadar bagaimana peran komunitas-komunitas seperti Konfiden dan berbagai kelompok di daerah membangun jaringan bersama dalam mendistribusikan karya-karya filem pendek yang sekaligus membangun kesadaran pada kebanggaan pada karya bangsa sendiri.



Festival Konfiden Sekarang
Peran besar Konfiden dan festival filem pendeknya merupakan keniscayaan generasi tahun 2000an dalam membangkitkan kecintaan pada filem anak negeri. Namun, apakah peran itu masih bisa kita rasakan di festival kali ini? Dewan Program festival kali ini dalam pengantarnya menulis: “…Ibarat cerita-cerita produk audio visual Indonesia (sudah jatuh, tertimpa tangga dan tembok yang runtuh, lalu gedungnya terbakar), FFPK 2009 harus menghadapi kenyataan bahwa hanya 10 judul film yang lolos seleksi dari 121 judul film… Selain itu, tidak ada satupun film dokumenter dalam 10 judul film peserta kompetisi FFPK 2009”.
Saya pun tertegun membaca tulisan pengantar tersebut. Sebegitu tergeruskah peran festival ini bagi kemunitas-komunitas filem pendek di berbagai daerah di Indonesia? Siapa yang salah dalam hal ini?
Konfiden sebagai sebuah organisasi pelopor komunitas filem pendek/independen di Indonesia dan penyelenggara gelaran ini seharusnya yang paling bertanggungjawab. Sebagai ajang publik, festival ini seharusnya tetap menjadi barometer dan denyut perkembangan filem pendek di Indonesia. Dalam buku Ketika Film Pendek Bersosialisasi (2001), Gotot Prakosa menulis dengan harapan yang sangat optimis bahwa filem independen di tangan Konfiden. Sebuah pernyataan yang menempatkan posisi penting Konfiden dalam lingkaran filem (film-scene) di Indonesia. Bahkan dalam tulisannya, Prakosa menyamakan gerakan Konfiden dengan gerakan filem avant-garde Jepang, Image Forum.
Dalam tiga tahun terakhir setelah melakukan reorganisasi dalam tubuh Konfiden, organisasi ini mencoba untuk bangkit dengan gairah baru. Namun, apa yang baru? Saya memang belum melihat sesuatu yang baru dan signifikan dalam penyelenggaraan festival dalam tiga tahun terakhir. Festival ini masih dalam tahap kumpul-kumpul para pegiat filem pendek di Indonesia. Tidak ada pernyataan kultural (cultural statement) yang merupakan salah satu cara negosiasi kepada para pelaku (stakeholder) dunia perfileman di Indonesia.

Saya cukup merasa senang dengan “ketatnya” cara Dewan Program festival kali ini dalam memilih karya-karya yang layak masuk dalam kompetisi. Karena dari sinilah kita dapat melihat bagaimana sebuah festival melahirkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam sinema di Indonesia dari sineas-sineas muda kita. Dalam catatan Dewan Program pada katalog festival tertulis:
“…filem pendek harus menunjukkan adanya eksplorasi atas tema, bentuk, gaya bertutur, dan media… Eksplorasi menjadi penanda adanya semangat eksperimentasi atas media filem… Semangat dan upaya terus melakukan eksplorasi membuat film pendek tidak pernah mengenal kata ’rumus‘ atau ’resep‘ yang hanya memberi ruang sempit pada sifat mediokritas… eksplorasi saja tidak cukup, dan FFPK tidak menginginkan film pendek yang ’asyik dengan diri sendiri’… Film menyampaikan gagasan dengan pemahaman yang utuh pada konteksnya. Sebuah film tentang kemiskinan atau konflik budaya bila tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh atas konteksnya dapat menimbulkan kesalahpahaman atau melenceng dari tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya… Penekanan pada film pendek naratif dengan gaya penceritaan yang tidak lazim dan beragam menjadi sangat penting sebagai karya visual alternatif. Hal tersebut tidak akan tercapai bila film tidak bersifat komunikatif.”
Dari catatan Dewan Program, dapat dibaca Konfiden mencoba meletakkan landasan baru dalam melihat festival filem ini selain “hanya” sebagai ajang pertemuan sineas muda di Indonesia. Catatan Dewan Program festival ini perlu mendapat apresiasi karena banyaknya ajang serupa yang diadakan oleh berbagai komunitas lain di berbagai daerah. “Pemain” gerakan sinema alternatif dan filem pendek sudah menjamur di sana-sini. Jaringan di Indonesia dan internasional juga sudah sangat luas. Jadi, organisasi ini seharusnya lebih aktif membangun wacana sinema alternatif dan filem pendek. Karena kesempatan itu telah terbuang sia-sia beberapa tahun lalu saat hampir seluruh komponen pegiat filem pendek Indonesia bersandar ke Konfiden. Dan, sekarang telah diambil alih oleh pemilik modal dalam dunia sinema kita.

Melihat Festival Film Pendek Konfiden 2009, saya perlu memberi catatan terhadap tulisan Gotot Prakosa yang saya kutip pada pembuka tulisan ini. Kesadaran terhadap kelompok seharusnya juga membangun kesadaran terhadap pewacanaan dalam gerakan sinema alternatif dan filem pendek itu sendiri. Berkaca pada Festival Filem Pendek Oberhausen, Jerman, semangat manifesto Oberhausen tetap terasa pada setiap penyelenggaraannya, dengan mengusung isu-isu sosial politik yang berkembang di berbagai belahan dunia. Dalam sebuah tulisan Kemajemukan Karya Sinema Indonesia: Sebuah Cita-cita? (2001), Alex Sihar (salah seorang pendiri dan direktur Konfiden) menulis Kredo Konfiden; 1) Berpikir Merdeka; 2) Berkarya Mandiri; 3) Membangun Sinema Indonesia. Sudahkah tiga poin kredo ini diaplikasikan oleh Konfiden? Saya berharap sudah, karena banyak aktivitas yang diusung oleh kawan-kawan kita ini. Namun, sampai saat ini tidak “bunyi” dalam jaringan komunitas filem di Indonesia. Konfiden telah mengantar Alex Sihar menjadi anggota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta periode 2009-2012. Semoga dengan posisi ini, Alex dapat berkontribusi lebih besar dalam perkembangan filem pendek di Indonesia dengan pikiran yang merdeka, mandiri untuk sinema Indonesia.