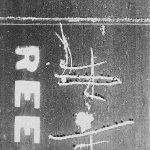Temporarily available only in Bahasa Indonesia
Peristiwa 1965 hampir tiap tahun direfleksikan oleh beberapa kalangan di Indonesia. Selama Orde Baru, satu-satunya akses sejarah dalam format audio visual tentang peristiwa itu adalah filem Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer. Ada juga buku wajib pelajaran sejarah yang tentunya kepanjangan tangan dari tafsir kekuasaan. Pasca Orde Baru, kegelisahan terhadap sejarah resmi tentang peristiwa 1965 terus mengalami perkembangan tafsir, yang dimungkinkan karena semangat reformasi memberikan peluang terhadap akses-akses dokumen dan buku sejarah. Juga kesaksian-kesaksian para pelaku, pengakuan-pengakuan (testimoni) para korban, sehingga membuka obyek baru dalam membaca sejarah, yang pada akhirnya ikut melahirkan pendekatan baru dalam memandang sejarah itu sendiri.
Perluasan penggunaan medium yang baru juga turut serta dalam menarasikan peristiwa 1965. Filem saat ini telah menjadi satu diantara siasat baru dalam menarasikan sejarah. Namun, apakah penggunaan filem hanya sekedar merayakan tafsir sejarah? Ataukah dapat juga memberikan perspektif baru dalam memandang sejarah, khususnya dalam perspektif medium?

Tjidurian 19 (2009), merupakan karya dokumenter Abduh Azis dan Lasja Susatyo yang ikut serta memperbincangkan peristiwa 1965 melalui subyek para anggota Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berdiri tahun 1950 dan aktif di Jalan Tjidurian 19, Cikini, Jakarta. Filem yang berdurasi 41 menit berusaha untuk menghadirkan dan memberikan pengalaman dinamika yang terjadi di kantor pusat lembaga kebudayaan realisme sosial ini.
Filem dibuka dengan penggunaan arsip visual yang bersumber dari Lembaga Arsip Indonesia tentang beberapa peristiwa politik di masa Presiden Soekarno. Konstruksi filem dokumenter seperti itu tentu sangat lazim kita temui pada dokumenter sejarah di televisi. Penggunaan visual hitam putih semakin menambah nuansa “kesakralan” peristiwa sejarah tersebut. Hal ini juga dilakukan pada filem Pengkhianatan G 30S/PKI yang diproduksi oleh Pusat Produksi filem Negara (PPFN) tahun 1984. Kesakralan inilah yang menjadi kegelisahan dan pertanyaan sendiri dalam memandang sejarah. Apakah sejarah selalu sakral? Hal ini ditambah lagi dengan semangat bahwa arsip menjadi tindakan yang mengandaikan kepastian peristiwa yang terekam. Sehingga arsip menjadi keniscayaan akan kebenaran peristiwa. Sehingga tidak membuka peluang adanya sebuah kenisbian peristiwa yang berasal dari frame (bingkai) atau penyuntingan.




Kecenderungan romantisme sejarah dalam penggunaan arsip tentu menjadi peluang yang terbuka lebar. Hal ini akan menutup semangat memaknai sejarah secara produktif. Pada Tjidurian 19, banyak menghadirkan potongan-potongan dokumentasi filem dan foto-foto yang ditampilkan dalam sela wawancara para subyek. Bagi para pembuat filem dokumenter, sering kita mendengar kebanggan tersendiri jika sebuah karya mampu mengakses arsip penting yang tidak mampu di akses oleh pihak lain.
Beberapa bagian pada Tjidurian 19 menghadirkan potongan-potongan dokumentasi peristiwa politik masa pemerintahan Presiden Soekarno diantaranya; footage upacara peringatan ulang tahun PKI (Partai Komunis Indonesia) di Stadion Senayan, footage penolakan dan anti PKI, dan footage peristiwa politik lainnya di tahun 1965. Kehadiran arsip-arsip tersebut dalam filem ini, dapat kita lihat tidak mampu diimbangi dengan bahasa visual yang inspiratif. Adegan keseharian para tokoh Lekra terasa hambar. Adegan-adegan ini pada dasarnya tidak memiliki signifikansi terhadap konstruksi sejarah yang berpihak pada korban. Salah satu contoh dalam adegan keseharian Martin Aleida. Disela wawancara, ia digambarkan seorang yang selalu naik komuter (kereta rel listrik) di Jakarta. Lalu, ada juga adegan Martin yang sedang berkaca di kamar. Di sela itu ia sempat berkomentar tentang kondisi transportasi KRL yang sesak dan mengatakan, “mengurus benda mati saja tidak bisa”. Tidak jelas relevansi pernyataan terakhir itu dengan konstruksi filem yang ingin dihadirkan oleh sutradara.


Pada Tjidurian 19, penggunaan arsip masih berhenti sebagai arsip itu sendiri. Ia belum sanggup sampai pada kaidah arsip sebagai bagian dari sumber sejarah yang dapat dihadirkan dengan lebih bernilai estetis. Penggunaan foto-foto dan kliping koran koleksi para anggota Lekra, masih sebatas semangat memberikan image penguat terhadap keberadaan Lekra di masa lalu. Penggunaan slide projector di latar para tokoh saat diwawancara perlu diapresiasi. Tapi, setelah beberapa lama menjadi hambar, karena tidak terbangun relasi yang dramatik dari slide-slide tersebut dengan pernyataan-pernyaatan yang hadir dari para tokoh. Seperti di sela-sela wawancara Martin Aleida, diselipi dokumentasi foto masa mudanya beraktivitas di jalan Tjidurian 19. Juga slide potongan koran tulisan-tulisan Antagama di sela-sela wawancara beliau. Semuanya sangat linier. Sangat mudah ditebak. Hal yang hampir sama terjadi pada wawancara tokoh lainnya seperti Amrus, dan Putu Oka.


Terlepas dari ketidakberhasilan sutradara menghadirkan dokumentasi arsip visual yang digabung dengan kekinian pada Tjidurian 19, setidaknya filem ini cukup memberikan informasi penting yang berasal dari pengalaman pribadi para pelaku-pelakunya. Sebagai pengetahuan dan pengalaman teks, Tjidurian 19 tentu memberikan informasi baru bagi para penontonnya. Filem ini belum memberikan perspektif baru dalam memandang sejarah dalam pengalaman visual. Sebagai dokumentasi yang bercerita tentang sejarah seputar peristiwa Tjidurian 19, karya ini secara jurnalisme cukup memberikan tambahan informasi penting. Tidak bisa dipungkiri, memang ada keasikan tersendiri menonton dan membaca arsip tentang peristiwa masa lalu, melihat para pelaku sejarah yang sudah tua bercerita tentang masa lalunya. Melihat arsiap visual seakan melihat data sejarah yang langka dan mengandung nilai keniscayaan peristiwa, dan melihat pelaku sejarah berbicara seakan mendengar pengakuan-pengakuan yang asli.
Sangat disayangkan filem yang diproduseri oleh Putu Oka Sukanta dan Abduh Aziz ini belum berhasil menemukan bahasa yang tepat dan mengasikan dalam merepresentasikan sejarah. Filem membutuhkan konstruksi yang sangat bisa diperhitungkan, begitu kata Sergei Eisenstein. Namun, konstruksi itu bisa dilanggar apabila sang sutradara mampu menghadirkan cara bahasa visual yang berbeda. Usaha untuk berbeda itu tentu ada pada filem ini. Namun saat kami menonton, pada bagian pembuka filem, sudah dihancurkan oleh musik yang tidak ada bedanya dengan sinetron-sinetron yang hadir di televisi. Musik mendayu sudah menjadi stigma sendiri dalam dunia filem kita. Banyak sutradara lebih percaya kepada musik dalam membangun dramatik daripada visual yang mereka buat.


Kelahiran filem sendiri membawa semangat baru dalam memandang realitas. Kelahiran beberapa gaya sastra dan teater modern, setidaknya terinspirasi oleh perspektif kamera dalam merepresentasikan realitas. Jika demikian, maka tentu kehadiran filem sebagai medium representasi akan membawa semangat baru pula dalam cara memandang sejarah. Setidaknya filem mampu menutup celah-celah kosong yang belum terpenuhi oleh bahasa-bahasa medium lainnya, ditengah akses terhadap sejarah yang paling dimungkinkan oleh semua pihak masyarakat adalah bahasa, termasuk bahasa visual.
Filem Tjidurian 19 dapat diunduh di sini