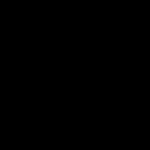“Ada patokannya ga?”
Empat kali pertanyaan ini diutarakan oleh si penelepon dalam video Jalan Tak Ada Ujung karya Maulana ‘Adel’ Pasha. Pertanyaan yang begitu penting bagi si penelepon untuk menemukan rumah ‘itu’. Transaksi tanda pun terjadi. Tawar menawar gagasan penanda subjektif antara si penelepon dengan yang ditelepon dan kemudian berakhir tanpa kesepakatan.
Suara
Video ini dimulai oleh pertanyaan basa-basi, “Apa kabar?” Pertanyaan yang tentu akan selalu dilontarkan dan selalu dijawab sebagai kesepakatan pembuka percakapan. Si penelepon kemudian melontarkan rentetan pertanyaan tentang keadaannya sekarang. Keadaan si orang yang ditelepon yang telah hilang dalam durasi pengamatan si penelepon terhadapnya. Adegan pembuka ini saya sebut sebagai monolog orang yang ditelepon, sebab si penelepon sama sekali tidak menceritakan dirinya. Ia hanya menyebut nama yang siapa saja bisa memiliki nama itu. Lalu, siapa sebenarnya si penelepon?
Perjalanan dimulai saat pembicaraan masuk kepada ‘arah’. Arah dalam video ini tidak berdasar mata angin, seperti tradisi yang hingga kini masih digunakan di sebagian masyarakat Indonesia. Arah disini lebih kepada tanda-tanda subjektif sebagai penyesuaiannya terhadap perkembangan fisik kota, terutama Jakarta, yang memiliki percepatan perubahan di tiap jengkal wilayahnya dan tidak mampu diimbangi oleh perkembangan penunjuk-penunjuk arah resmi. Melihat video ini seperti berada di sebuah labirin –oleh sebab itu saya menyebut gang-gang sempit dalam video ini sebagai lorong. Kemudian, lorong-lorong itu pun lantas berbicara. Tentang posisinya dalam sebuah pemetaan. Posisinya dalam struktur tata kota. Posisinya dalam masyarakat yang lebih luas (negara dengan sejarah terjajah). Posisinya dalam Google Earth. Dan, posisinya di dalam teknologi (video).

Kramat Jati Indah. Sebuah mal; mikrolet 19, angkutan umum jurusan Cililitan-Klender; Jalan Nusa di daerah Halim (Mandala, menurut kesepakatan sopir/kernet dan penumpang); yang diucapkan dengan jelas oleh si penerima telepon menjadi penanda umum dan subyektif yang sangat bisa dimiliki juga oleh si penelepon. Sedang kata-kata seperti: “ke kanan ke pasar, masjid, 20 meter, 10 langkah, lapangan bulu tangkis, jembatan di atas tol Jagorawi, taman kanak-kanak, pertigaan, bengkel sepeda,” hanya menjadi penanda milik si penerima telepon. Jenis-jenis penanda itu tidak memiliki spesifikasi identitas seperti nama dan ukuran —dalam kasus ini, langkah kaki yang diutarakan oleh si penerima telepon berdasar asumsi langkah kaki orang yang menelepon. Bentuk pasar yang dimaksud merujuk pada informasi faktual umum. Begitu pun dengan lapangan yang disebutkannya. Bahkan kalau mengacu pada “jembatan di atas tol Jagorawi”, hal itu dimaksudkan pada fakta tentang sebuah jembatan yang memang melintang di atas jalan bebas hambatan Jagorawi. Jenis-jenis penanda yang dimiliki oleh si penerima telepon hanya dapat dibayangkan secara umum, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan si penelepon, atau barangkali si penelepon dapat membaca karakter si penerima telepon, sehingga ia bisa membayangkan jenis-jenis penanda yang dimaksud olehnya. Begitu rumitnya membaca arah, padahal sejak awal hingga akhir video arah yang diinformasikan hanya ada dua: kiri dan kanan. Tidak ada utara-selatan atau barat-timur.
Diabaikannya arah mata angin tentu sangat berpengaruh pada lorong-lorong itu. Bagaimana bisa merasakan kesahihan arah mata angin hanya dengan mengulum jari manis kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi untuk merasakan hembusan. Atau sekadar membaca arah jatuhnya bayangan diri sedang lorong-lorong itu cukup berhasil menelan semuanya. Baiklah. Lebih baik kita abaikan perbincangan soal mata angin sebab hal itu mubazir. Lagipula, saya tidak punya kapasitas membicarakannya.
Transaksi kesepakatan antara penelepon dan penerima telepon tentang penanda terjadi berulang-ulang. Pengulangan ini tentu saja tidak hanya sekadar menjaga ritme alur video, sebagai intervensi psikologis untuk pemirsa, atau dengan kata lain membuat pusing dan seperti merasa berada di sebuah labirin dengan jalan rumit berkelok halang lintang, atau membuat video ini menjadi menarik karena menertawakan diri sendiri melalui kebodohan dan kealpaan memori si penelepon. Kita lalu bisa bertanya, tidakkah si penelepon merasa kapok mendengar pengulangan informasi kiri dan kanan, sampai ia tidak ingin mencatat secara rinci semua petunjuk itu?
Pengulangan lalu menjadi penting dari video ini. Dalam pengulangan inilah terjadi tawar-menawar selayaknya sebuah transaksi. Tawar-menawar penanda yang bisa dipahami oleh si penelepon. Seperti di akhir video ketika orang yang ditelepon memberikan identitas khusus diri dalam masyarakatnya dengan, “tanya rumah Gambit” sebagai akhir transaksi tanpa kesepakatan —mengacu dari terkaan bahwa si penelepon tahu nama panggilan orang yang ditelepon.
Menandai letak ia (masyarakat Jakarta) dengan berpijak pada tanda-tanda objek diam di suatu kawasan terutama di kota sangatlah rentan mengingat objek diam itu dapat hancur dimakan usia: dihancurkan, berpindah, bergeser, dimodifikasi atau direproduksi. Begitu pun penanda resmi yang dibuat pemerintah, meski memiliki makna sangat luas dalam kenyataan jarang diperbarui. Cara satu-satunya, dan yang paling sahih menurut saya, adalah penanda subjektif. Penanda yang terus berkembang mengikuti perkembangan pertumbuhan kota. Penanda yang diperoleh dari penyesuaian diri dengan karakter kota. Jadi bukan sekadar durasi menghuni, atau istilah, ‘gue orang Jakarta’, yang menentukan ia tidak akan tersesat. Begitupun dengan penanda bergerak seperti angkutan umum. Pemaknaan atas penanda bergerak lebih sulit ketimbang penanda diam. Secara instingtif, semua pemaknaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat yang betul-betul tahu karakter kotanya.
Dalam video ini satu angkutan umum teridentifikasi, yaitu mikrolet 19 jurusan Cililitan-Klender. Jelas sekali arah yang akan dituju oleh angkutan umum itu. Dan pemberitaan identitas nomor dan jenis kendaraan umum itu mempersempit penandaan. Mandala-Halim-Jalan Nusa, tidak akan luput dari penelusuran sepanjang jalan Cililitan-Klender dengan moto angkutan umum, PP (pulang-pergi). Kecuali terjadi perubahan karakter kota seperti si supir orang baru dan tidak mengenal detail trayek angkutan umum yang dibawanya atau telah bergesernya titik tengah wilayah yang disebut Mandala karena jalur-jalur yang menghubungkan antara masyarakat di daerah itu dengan jalan raya telah lenyap seperti dibangunnya pagar tembok beton yang tidak mungkin dilubangi sehingga masyarakat yang tinggal di Mandala harus menggeser titik turun dari angkutan umum ke tempat yang mudah diakses.
Percakapan tentang arah itu lantas dapat mengingatkan kita pada sebuah dialog imajinatif ketika hendak pergi ke sebuah acara pernikahan atau sunatan. Peta yang dibuat tidak spesifik layaknya peta yang dibeli di toko buku, yang selalu mengikuti perkembangan tata kota itu. Kita disodorkan oleh beberapa penanda yang biasanya berupa bangunan dan diberi identitas jenis bangunan dan nama yang pada saat itu masih berdiri. Lantas kita membayangkan di mana posisi kita dan di mana posisi tujuan itu, yang kemudian menelusuri titik-titik yang mungkin bisa dicapai karena pengetahuan dan pengalaman menghadapi ruang-ruang itu di Jakarta seperti kemungkinan naik sepeda motor, kemungkinan naik mobil, dan kemungkinan naik angkutan umum. Bahkan ada beberapa peta yang memberikan legenda berupa trayek angkutan umum untuk memudahkan tamu undangan.
Imaji dan ilusi ditawarkan dalam durasi percakapan video Jalan Tak Ada Ujung. Pemilihan dialog telepon, di mana percakapan berlangsung tanpa kehadiran fisik tokoh-tokohnya mempertegas dua hal yang disebut sebelumnya.

Citra
Tahun 1929, Denis Arkadievitch Kaufman yang lebih dikenal Dziga Vertov membuat Chelovek s Kino-apparatom (Man with a Movie Camera). Ia memprediksi kekuatan sinema di kemudian hari, di mana sinema akan masuk hingga ke ruang-ruang privat —tetapi sinema kemudian tidak mampu untuk masuk lebih jauh dari sinema bergerak (salah satunya layar tancap), yang kemudian dijawab oleh video —karena keberhasilannya menjelajah hingga ruang-ruang privat. Vertov melanglang buana masyarakat Rusia waktu itu. Menenteng-nenteng kamera dari jalan kaki hingga menggunakan mesin (mobil dan motor). Ia merepresentasikan bagaimana kamera berada di tengah masyarakat dengan kemilau menawannya, merekam semua kegiatan. Bagaimana ia bisa menjadi candu yang menghipnotis dengan tawaran imajinasinya, bagaimana ia begitu mudahnya menghasut massa, dan bagaimana ia bisa menawarkan kejernihan interpretasi. Kini video yang memiliki peran itu. Jarak sinema telah dihancurkan oleh video. Bayangkan seandainya video Jalan Tak Ada Ujung dibuat dengan kamera seluloid? Mungkin saja dengan teknologi sekarang seluloid mampu mengatasinya. Tapi inilah yang kemudian menjadi kelebihan kamera video yang tidak perlu berpikir panjang untuk memutuskan ambilan tangan (handheld) di jalan-jalan umum yang sempit dengan pencahayaan alakadar beserta latar-latar perekaman semua peristiwa. Memperlihatkan ruang-ruang kecil dalam rumah-rumah di selusur gang-gang tersebut. Citra itu lantas membentuk ruang tersendiri di dalam videonya. Antara penelusuran imajinatif dalam suara, tidak searah dengan penelusuran pada citra. Lorong-lorong itu bukan hanya gang-gang yang diceritakan dalam percakapan telepon. Seperti ketika terjadi percakapan:
“Dari rumah lu naik mikrolet 19 turun di Cililitan. Kalo naik ke Halim turun di Mandala. Dari situ nyebrang, masuk ke jalan besar namanya Jalan Nusa. Ketemu pertigaan, kalau ke kanan ke pasar. Jadi lu belok ke kiri. Kira-kira 20 meter belok ke kanan ada jalan kecil. Sampai ketemu masjid habis itu nanjak. Kira-kira 10 langkah ada gang di kiri. Sudah ketemu turunan yang ada lapangan bulu tangkis lu belok kanan sampai bertemu sebuah dinding, belok ke kiri sampai bertemu jembatan di atas tol Jagorawi lalu belok ke kanan sampai pada akhirnya bertemu dinding dan belok ke kanan terus naik ke atas lalu belok ke kanan langsung ke kiri dan bertemu Taman Kanak-Kanak terus pertigaan. Belok ke kiri ketemu bengkel sepeda terus belok kanan.”
Citra dalam percakapan itu tidak memperlihatkan adanya mikrolet 19, keterangan Jalan Nusa, sebuah masjid, taman kanak-kanak, dan seterusnya. Citra dan suara lalu saling mengisi untuk membentuk pencitraan dari bidang yang lebih besar yaitu tata bangunan yang berlanjut pada tata kota dan berakhir pada tata kota-kota dunia dengan sejarah terjajah. Pencitraan itulah —tidak bermaksud menunjuk pada kesalahan sistem tata kota karena sistem yang terbentuk pada lorong-lorong itu lahir dari interaksi antara karakter-karakter kotanya— menjadi bahasa verbal tentang persoalan interaksi penghuni dengan hunian.
Jalan Tak Ada Ujung kemudian menawarkan sebuah pemetaan atau perpanjangan tangan dari Google Earth dan sejenisnya. Jika saja pergerakan si pembawa kamera itu dipasangi GPS dan kita memetakannya, mungkin akan terlihat garis halang lintang di wilayah yang dimaksud dalam video itu, seperti sebuah labirin.
Kamera lantas menjadi mata (si pembuat): mata menangkap citra (pemirsa dan saya): terbentuk ruang yang disebut lorong (pemirsa dan saya): labirin (pemirsa, saya, dan pengamat yang memiliki kepentingan tersendiri terhadap soal pendataan).
Pertanyaannya, siapakah si pembawa kamera yang menghantarkan ‘mata’ kepada permirsa? Siapa yang bertugas sampai di penyajian ‘mata’ atau memberikan tawaran kepada pemirsa untuk menjadi ‘dirinya’?
Citra itu bisa milik siapa saja. Tersesat dalam ruang-ruang kota dimiliki oleh semua orang. Lenyapnya jarak si pembuat dengan pemirsa dan saya disebabkan hilangnya intervensi bingkaian dari kamera —kecuali pada adegan pembuka yaitu ambilan gambar medium sebuah pintu yang bergerak perlahan. Seperti layaknya sebuah simulasi atau permainan jaringan Medal of Honor yang memberikan kebebasan melihat bagi partisipannya, Jalan Tak Ada Ujung bergerak lebih jauh dengan memberi lebih banyak kebebasan imajinasi dalam pemilihan jalan dengan perhitungan subjektifnya. Proses penyesuaian diri yang selayaknya dimiliki oleh orang yang hidup di kota.
Kesepakatan penandaan antara si penelepon dan si penerima telepon, dan kesepakatan tanda antara suara dan citra, merupakan kesepakatan antara tanda-tanda yang dihadirkan oleh Jalan Tak Ada Ujung. Tawar-menawar posisi tanda yang berlangsung dalam enam menit durasinya. Kenyataan sosial dan kenyataan bingkaian sebagai arena transaksi tanda itu menjadi lahan pertempuran di masa sekarang dan berhasil disisipkan pada video itu. Dalam bentuk presentasinya, video ini juga mengajukan tawaran yang bisa saja diputar dalam sebuah ruang pamer dalam bentuk satu layar seperti sebuah lukisan —seperti presentasinya pada ASEAN New Media Art 2007 dan Indonesia Art Award 2008, dibuat dalam bentuk instalasi, atau ditayangkan dalam konsep sinema seperti ketika video ini diputar pada Tampere 37th International Short Film Festival tahun 2007 di sebuah gedung sinema Plevna 6.
Video ini berhasil keluar dari sakralitas modernisme. Ia bisa begitu cair, tetapi memiliki kekukuhan posisinya sebagai video. Tak heran kalau video ini dipilih sebagai salah satu pemenang ASEAN New Media Art 2007 dan Indonesia Art Award 2008. Bukan karena sifat dokumenternya —sebagai kepercayaan pembawa kebenaran yang kini juga dipertanyakan ulang, tetapi kepada pemampatan persoalan yang sedang terjadi sekarang ini baik dari sisi medianya sebagai bahasa juga lokalitas yang tidak terpusat hanya kepada subjek pengkisah.

Tentang Video Jalan Tak Ada Ujung
Video pertama Maulana M. Pasha ini merupakan salah satu video yang cukup fenomenal dalam ranah filem pendek dan seni video di Indonesia. Video yang merupakan hasil dari proyek Videopoem yang digagas oleh Forum Lenteng pada tahun 2004-2006 ini menampilkan fenomena kota dengan pendekatan mata kamera video yang berbeda dari bayangan visual naratif. Pada tahun 2007, Jalan Tak Ada Ujung menerima penghargaan Grand Prize pada kompetisi Asean New Media Art 2007 di Galeri Nasional yang diikuti oleh seniman-seniman dari negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2008, video ini juga menerima Karya Terbaik Indonesian Art Award 2008, menjadikannya sebagai karya seni video pertama yang menerima penghargaan Yayasan Seni Rupa Indonesia ini (sebelumnya penghargaan selalu didominasi oleh karya seni lukis, patung, objek, dan multi-media). Beberapa presentasi penting yang diikuti oleh Jalan Tak Ada Ujung adalah; OK.Video Militia 3rd Jakarta International Video Festival 2007, The 37th Tampere International Short Film Festival 2007—Finlandia, 5ÈME Festival Signes de Nuit 2007—Swiss, Life in Jakarta 2007 Cultural House Kanneltalo Helsinki—Finlandia, The 55th International Short Film Festival Oberhausen 2009—Jerman. Karya video ini juga dipresentasi di berbagai pameran seni media di Indonesia dan internasional, seperti; Jakarta, Surabaya, Medan, Rotterdam (Belanda), Paris (Perancis), Berlin (Jerman), Kuala Lumpur (Malaysia), Sidney (Australia), Singapura, Bangkok (Thailand) dan lain-lain.

Tentang Pembuat Video
Lahir di Jakarta pada Januari 1983. Menempuh pendidikan jurnalistik di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politk (IISIP) Jakarta, 2001-2005. Ia merupakan salah satu pendiri Forum Lenteng Jakarta. Proyek video pertamanya Massroom Project dikerjakan bersama para pendiri Forum Lenteng. Setelah menyelesaikan studi jurnalistik pada tahun 2005, seniman yang biasa dipanggil Adel ini sempat bekerja sebagai pegawai sebuah bank pemerintah sebagai marketing produk asuransi. Pada tahun 2006, memutuskan untuk serius menjadi seniman media dengan bekerja di Forum Lenteng. Sebagai seniman, Adel adalah seniman video pertama yang meneriman penghargaan Asean New Media Art dan Indonesia Art Award bersama Ari Satria Dharma. Penghargaan ini mengukuhnya menjadi salah satu seniman seni media di ranah seni rupa Indonesia. Pada tahun 2008, ia diundang untuk menjadi partisipan pada Bangladesh Bienalle 2008. Aktif mengikuti pameran dan presentasi di berbagai tempat bersama Forum Lenteng dan individu, baik nasional maupun internasional. Pada 2010, ia menjadi inisiator pameran bersama Yang Taksa di Pusat Kebudayaan Prancis Jakarta.