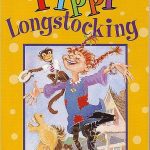Pendahuluan
Bayangkan diri kita berada dalam situasi standar kecemburuan khas chauvinisme pria: tiba-tiba saja, saya mendapati pacar saya berhubungan seks dengan pria lain. Oke, tak masalah, saya seorang pria yang rasional, toleran, saya bisa menerimanya… namun lantas, tak pelak lagi imaji-imaji mulai bermunculan merongrong saya, gambaran-gambaran konkret tentang apa yang mereka perbuat (ngapain sih pacar saya harus menjilatinya tepat di situ? Ngapain sih dia harus mengangkang selebar itu?) Saya pun lupa diri, keringatan dan gemetar, rasa tenang lenyap selamanya dari diri saya. Sampar fantasi macam ini, yang disebutkan oleh pemikir Renaissance Fransiskus Petrarchus dalam bukunya Secretum (Buku Rahasia Saya) sebagai gambaran-gambaran yang mengaburkan penalaran jernih seseorang, dihadirkan secara ekstrem oleh media audiovisual zaman sekarang. Di antara benturan-benturan antagonistik yang mewarnai zaman kita (globalisasi pasar dunia versus penegasan partikularisme etnis, dsb.), barangkali tempat pokoknya terletak pada antagonisme antara abstraksi yang kian lama kian menentukan hidup kita (dalam selubung digitalisasi, relasi pasar spekulatif, dll.) dengan banjirnya imaji-imaji pseudo-konkret. Di masa kejayaan Ideologiekritik tradisional, prosedur kritis paradigmatisnya adalah menarik diri dari gagasan-gagasan “abstrak” (religius, hukum, …) menuju realitas sosial konkret tempat gagasan-gagasan tersebut berakar. Di zaman ini, kian lama kian tampak bahwa prosedur kritis itu dipaksa untuk mengikuti jalur sebaliknya, dari imaji pseudo-konkret menuju proses-proses abstrak (digital, pasar…) yang secara efektif membentuk struktur pengalaman hidup kita.
Buku ini melakukan pendekatan sistematis, dari sudut pandang Lacanian, atas praanggapan-praanggapan tentang “sampar fantasi” ini. Bab pertama (“Tujuh Tabir Fantasi”) mengelaborasi kontur gagasan psikoanalitis tentang fantasi, dengan penekanan khusus tentang bagaimana ideologi harus menyandarkan dirinya pada latar fantasmik tertentu.

1. Tujuh Tabir Fantasi
“Kebenaran ada di luar sana”
Sekian tahun lalu, ketika tudingan akan perilaku “amoral” Michael Jackson (yakni permainan seksualnya dengan anak-anak bawah umur) terkuak dan merontokkan citranya sebagai Peter Pan yang lugu tanpa dosa, menjulang melampaui perbedaan (dan permasalahan) seksual serta rasial, beberapa pengamat yang tajam melontarkan pertanyaan gamblang: Buat apa ribut-ribut? Bukankah apa yang disebut sebagai “sisi gelap Michael Jackson” itu senantiasa terpampang untuk kita tonton bersama dalam klip-klip video yang menyertai peluncuran karya musiknya, yang penuh dengan ritual kekerasan dan gestur-gestur seksual tak senonoh (yang begitu blak-blakan dan tanpa tedeng aling-aling dalam kasus Thriller dan Bad)? Bawah-sadar itu terpampang di luar, bukan tersembunyi di balik kedalaman yang tak terselami—atau untuk mengutip semboyan X-Files: “kebenaran ada di luar sana”.
Fokus pada eksternalitas materiil macam ini terbukti sangat berguna dalam menganalisa bagaimana fantasi terkait dengan antognisme inheren suatu bangunan ideologis. Pertimbangkan dua rancangan arsitektural yang saling bertentangan antara markas lokal Partai Fasis Casa del Fascio karya Adolfo Coppede yang bergaya neo-Imperial (1928), dengan rumah kaca transparan Giuseppe Teragni yang sangat modernis (1934-1936). Tidakkah dengan jukstaposisinya itu kedua gedung tersebut mengungkap kontradiksi inheren proyek ideologis Fasisme, yang secara simultan mendorong untuk kembali pada korporatisme organis zaman pramodern, sekaligus mendorong mobilisasi seluruh kekuatan sosial yang belum ada presedennya demi tujuan modernisasi kilat?

Contoh yang lebih baik lagi tampak dalam proyek raksasa pembangunan gedung-gedung publik di Uni Soviet tahun 1930-an. Di atas gedung datar bertingkat itu biasanya diberdirikan sebuah (atau kadang sepasang) patung raksasa yang menggambarkan idealisasi Manusia Baru. Dalam rentang beberapa tahun, kecenderungan untuk kian mendatarkan atau menggepengkan bangunan kantor itu (tempat kerja aktual bagi manusia-manusia sungguhan) kian lama kian jelas terlihat, sampai-sampai gedung-gedung itu jadi tampak tak lebih dari sekadar pijakan bagi patung-patung raksasa itu. Tidakkah ciri material eksternal dari desain arsitektural ini mengungkap “kebenaran” ideologi Stalinis di mana manusia-manusia sungguhan direduksi menjadi instrument belaka, yang dikorbankan sebagai pijakan bagi momok Sang Manusia Baru di masa depan, sesosok monster ideologis yang melumat manusia-manusia sungguhan di bawah kakinya? Paradoksnya adalah: barang siapa yang berani berkata terang-terangan di Uni Soviet tahun 1930-an bahwa visi Manusia Baru Sosialis adalah sesosok monster ideologis yang melumat manusia-manusia sungguhan, jelas mereka akan langsung diringkus. Namun demikian, mengungkapkan hal ini justru diperbolehkan —digiatkan, malah—lewat desain arsitektural… sekali lagi, “kebenaran ada di luar sana”. Dengan demikian argumentasi kita bukan hanya bahwa ideologi itu menjalari strata ekstra-ideologis dari hidup keseharian, melainkan bahwa pengejawantahan ideologi dalam materialitas eksternal ini mengungkap benturan-benturan inheren yang tidak mungkin diakui oleh rumusan eksplisit ideologi itu sendiri: seolah-olah sebuah bangunan ideologis, bila ingin berfungsi “normal”, harus mematuhi sejenis “godaan kelainan” tertentu (imp of perversity), dan mengartikulasikan antagonisme inherennya dalam wujud luar keberadaan materiilnya.
Eksternalitas ini, yang secara langsung mematerialisir ideologi, juga dipampatkan sebagai “fungsi” (utility). Artinya: dalam hidup sehari-hari, ideologi bekerja terutama dalam rujukan yang tampak semata-mata sebagai fungsi—jangan lupa bahwa pada jagat simbolik, “fungsi” bertindak sebagai gagasan refleksif; yang artinya ia selalu melibatkan penegasan fungsi itu sebagai makna (umpamanya, seseorang yang tinggal di kota besar dan punya mobil Land Rover tidak semata menjalani hidup yang “membumi” dan tanpa kompromi; melainkan, ia memiliki mobil itu untuk memberi pertanda bahwa ia menjalani hidup di bawah panji-panji sikap “membumi” dan tanpa kompromi).
Empu tak tertandingi dalam analisa macam ini tentu saja adalah Claude Lévi-Strauss, yang segitiga semiotikanya dalam tata boga (mentah, dipanggang, digodok) menunjukkan bahwa makanan juga bertindak sebagai “makanan otak”. Barangkali kita semua ingat adegan dalam film Luis Buñuel The Phantom of Liberty, di mana hubungan antara makan dan berak dijungkirbalik: orang-orang duduk di atas kakus mengitari meja dan mengobrol santai, sementara bila mereka ingin makan, mereka diamdiam bertanya pada pelayan “Di mana tempat… tahu kan?” dan menyelinap ke kamar kecil di bagian belakang. Jadi untuk melengkapi Lévi-Strauss, kita pun tergoda untuk mengusulkan bahwa tahi juga bisa dipakai sebagai matière-à-penser: tidakkah tiga tipe dasar kakus bisa membentuk sejenis perbandingan korelatif ketinjaan atas segitiga masak-memasak Lévi-Strauss?


The Phantom of Liberty (1974), Luis Buñuel
Dalam kakus Jerman umumnya, lubang tempat tahi menghilang setelah kita guyur air terletak di bagian depan, sehingga tahi itu pertama-tama akan terpampang bagi kita untuk diendus dan diamati apakah ada jejak-jejak penyakit. Sebaliknya, dalam kakus Perancis umumnya, lubangnya terletak di belakang—artinya, tahi itu harus menghilang secepat mungkin. Terakhir, kakus Anglo-Saxon (Inggris atau Amerika) menghadirkan sejenis sintesis, mediasi antara dua kutub yang bertentangan tadi. Cekungan kakus itu penuh terendam air, sehingga tahinya mengambang: bisa terlihat, tapi bukan untuk diamati. Tak heran bila Erica Jong, dalam pembahasan terkenal atas berbagai jenis kakus Eropa pada pembukaan karyanya Fear of Flying yang kini sudah agak terlupakan, mengklaim dengan mengolok: “Toilet-toilet Jerman benar-benar merupakan kunci untuk menyelami horror Third Reich. Orang yang bisa membuat toilet macam ini sungguh sanggup berbuat apa saja.” Jelas bahwa tak satupun versi ini bisa diperhitungkan dalam kaidah yang murni utilitarian: adanya persepsi ideologis tertentu tentang bagaimana subjek harus berhubungan dengan buangan tak sedap yang keluar dari dalam diri kita kentara jelas di sini—lagi-lagi, untuk ketiga kalinya, “kebenaran ada di luar sana”.

Hegel termasuk orang pertama yang menafsirkan bahwa segitiga geografis Jerman-Perancis-Inggris ini mengekspresikan tiga sikap eksistensial yang berbeda: Jerman ketelitian permenungan, Perancis ketergesaan revolusioner, sementara Inggris pragmatisme utilitarian moderat. Dalam pengertian sikap politik, segitiga ini bisa dibaca sebagai konservatisme Jerman, radikalisme revolusioner Perancis, dan liberalisme moderat Inggris. Sedangkan dalam pengertian dominasi bidang kehidupan sosial, tersebutlah metafisika dan puisi Jerman lawan politik Perancis dan ekonomi Inggris. Rujukan pada kakus ini memungkinkan kita bukan hanya mengamati segitiga yang sama dalam wilayah paling intim fungsi pembuangan, namun juga melihat mekanisme dasar dari segitiga ini dalam tiga sikap berbeda mengenai tahi: keterpukauan kontemplatif yang ambigu; ketergesaan untuk menyingkirkan buangan tak sedap itu selekas mungkin; pendekatan pragmatis untuk memperlakukan buangan itu sebagai benda biasa yang harus dibuang dengan cara yang pantas.
Jadi, mudah kiranya seorang akademisi mengklaim dalam sebuah seminar bahwa kita tengah hidup dalam dunia pasca-ideologi. Tapi begitu ia masuk kamar kecil sesudah debat berapi-api, kembali lagi ia berkubang selutut dalam ideologi. Asupan ideologis dalam rujukan pada fungsi tersebut terbukti kebenarannya dari watak dialogis-nya: kakus Anglo-Saxon memperoleh maknanya hanya melalui hubungan diferensialnya pada kakus Perancis dan Jerman. Kita punya begitu banyak tipe kakus karena adanya proses pembuangan traumatis yang coba untuk diakomodasi oleh masing-masing tipe tersebut—menurut Lacan, salah satu cirri yang membedakan manusia dari binatang adalah justru karena pada manusia, pembuangan tahi itu jadi masalah.
Hal yang sama juga berlaku pada banyaknya cara orang mencuci piring: di Denmark misalnya, sederet rincian ciri-ciri mereka mencuci piring mempertentangkan cara itu dengan cara orang Swedia mencucinya. Analisa mendalam langsung bisa menguak bagaimana pertentangan itu dipakai untuk mengindeks persepsi dasar akan identitas nasional Denmark, yang dirumuskan secara berlawanan dengan identitas nasional Swedia.[1] Dan —memasuki ranah yang lebih intim lagi—tidakkah kita menemui segitiga semiotika yang sama dalam tiga model potongan rambut organ kewanitaan? Jembut yang lebat tak dipangkas mencerminkan sikap hippies atas spontanitas alamiah. Kaum yuppies (eksekutif muda) menyukai prosedur penataan taman-taman Perancis (jembut di sisi-sisi dekat pangkal paha dicukur, sehingga yang tersisa tinggal seurai di tengah-tengah dengan garis potong yang jelas). Dalam sikap punk, vagina dicukur polos dan dihiasi anting (biasanya ditindikkan ke kelentit). Tidakkah ini versi lain lagi dari segitiga semiotika Lévi-Straussian tentang jembut liar yang “mentah”, jembut yang “dipanggang” matang, dan jembut yang “digodok” habis?

Orang bisa melihat bagaimana sikap yang paling intim sekalipun terhadap tubuh seseorang dipakai untuk membuat pernyataan ideologis.[2] Jadi bagaimana eksistensi material dari ideologi ini terkait dengan keyakinan-keyakinan sadar kita? Mengenai Tartuffe karya Molière, Henri Bergson telah menekankan bagaimana Tartuffe itu lucu bukan karena kemunafikannya, melainkan karena ia terperangkap dalam topeng kemunafikannya sendiri.
Ia membenamkan diri begitu rupa dalam peran seorang hipokrit sampai-sampai ia memainkannya dengan penuh ketulusan. Dengan ini dan hanya dengan inilah ia jadi lucu. Tanpa ketulusan yang murni materiil ini, tanpa tindak-tanduk dan perkataan yang —melalui latihan panjang kemunafikan—baginya lantas menjadi sikap alamiah, Tartuffe akan jadi memuakkan.[3]
Ungkapan Bergson soal “ketulusan yang murni materiil” ini pas betul dengan gagasan Althusser tentang Aparatus Negara Ideologis—tentang ritual eksternal yang mematerialisir ideologi: subjek yang menjaga jarak dari ritual ini tak sadar akan fakta bahwa ritual tersebut telah menguasai dirinya dari dalam. Sebagaimana kata Pascal, kalau kau tidak percaya, berlututlah, bersikaplah seolah-olah kau percaya, dan kepercayaan ini akan dating dengan sendirinya. Begitu juga halnya dengan “fetisisme komoditas” Marxian: dalam kesadaran dirinya yang eksplisit, seorang kapitalis adalah seorang nominalis yang berakal sehat, namun “ketulusan yang murni materiil” dari perilakunya menampakkan “kejanggalan teologis” dari jagat komoditas.[4] “Ketulusan yang murni materiil” dari ritual ideologis eksternal inilah, bukan dalamnya keyakinan dan hasrat-hasrat diri sang subjek, yang merupakan lokus sesungguhnya dari fantasi yang menjaga sebuah bangunan ideologis.

Gagasan standar tentang cara kerja fantasi dalam ideologi adalah berupa gambaran tentang sebuah skenario-fantasi yang mengaburkan kengerian sesungguhnya dari sebuah peristiwa: alih-alih memahami sepenuhnya antagonisme yang ada dalam masyarakat, kita menceburkan diri ke dalam ide tentang masyarakat sebagai Keutuhan organis, yang dipersatukan oleh kekuatan solidaritas dan gotong-royong… Bagaimana pun, di sini juga jauh lebih produktif untuk mencari gambaran tentang fantasi ini di tempat-tempat yang paling tidak diduga akan didapati: di yang-marjinal, dan sekali lagi, dalam situasi-situasi yang tampak sepenuhnya fungsional. Cobalah kita ingat petunjuk keselamatan yang diperagakan sebelum pesawat tinggal landas-tidakkah ini dirawat oleh skenario fantasmik tentang seperti apa kemungkinan kecelakaan pesawat itu? Sesudah pendaratan mulus di air (yang ajaib, selalu dianggap terjadi di atas permukaan air!), masing-masing penumpang mengenakan pelampung penyelamat, dan sebagaimana di seluncuran pantai, merosot ke dalam air lalu berenang, ibaratnya liburan ramai-ramai di laguna di bawah pengawasan instruktur renang berpengalaman. Tidakkah “gentrifikasi” atas malapetaka ini (pendaratan yang mulus, pramugari-pramugari dengan gaya elok menunjuk ke tanda ‘Exit’…) juga merupakan ideologi dalam bentuknya yang paling murni? Meski demikian, gagasan psikoanalisa tentang fantasi tidak bisa direduksi menjadi gambaran tentang sebuah skenario-fantasi yang mengaburkan kengerian sesungguhnya sebuah peristiwa. Hal pertama dan cukup jelas yang harus ditambahkan adalah bahwa hubungan antara fantasi dan kengerian dalam the Real yang ditutup-tutupinya jauh lebih ambigu ketimbang yang kelihatan: fantasi menyembunyikan kengerian ini, namun pada saat yang sama menciptakan apa yang semestinya ia sembunyikan, titik rujuknya yang “direpresi” (tidakkah gambaran-gambaran tentang Makhluk maha seram, mulai dari cumi-cumi raksasa hingga amuk taufan badai, merupakan kreasi-kreasi fantasmik par excellence?).

[1] Baca Anders Linde-Laursen, “Small Differences-Large Issues”, The South Atlantic Quarterly, 94:4 (musim gugur 1995), hlm. 1123-1144.
[2] Kasus yang paling jelas —dan karena kejelasannya itulah tidak saya bahas di sini—tentu saja adalah konotasi ideologis yang ada dalam pelbagai posisi hubungan badan; artinya, pernyataan ideologis tersirat yang kita lontarkan dengan “melakukannya” dalam posisi tertentu.
[3] Henri Bergson, An Essay on Laughter, London: Smith, 1937, hlm. 83.
[4] Uraian rinci tentang paradoks fetisisme, lihat Bab 3 buku ini.
*Tulisan ini adalah cuplikan dari SAMPAR FANTASI. Diterjemahkan dari potongan Bab Pendahuluan dan potongan Bab 1 buku Slavoj Žižek The Plague of Fantasies (London: Verso, 1997) oleh Ronny Agustinus (2007-2008). Pernah dimuat di jurnal online Paralaks.
[/tab_item]
[tab_item title=”EN”]
(Temporarily available only in Bahasa Indonesia)
[/tab_item]
[/tab]