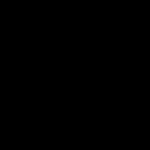Dimuat di Mingguan Siasat edisi Minggu-1950 Nopember 1950, Minggu-26-Nopember 1950, dan Minggu-3 Desember 1950. Ditulis oleh Rivai Apin
1927 adalah tahun yang sangat berarti bagi dunia filem. Tahun itu menutup periode pertama dari lahirnya filem dan tahun itu pula dimulai periode baru sampai sekarang ini [1950]. Tahun itu ialah tahun kelahiran filem bersuara. Dan peristiwa itu telah mengguncangkan konsep filem yang ada sampai pada waktu itu [1927].
Kemajuan ini telah menggoyahkan anggapan masyarakat akan teori-teori dan kepastian-kepastian, dan rumus-rumus yang diyakini saat itu sebagai ke-khas-an sebuah filem. Dilihat dari sudut estetika, orang tidak lagi mempunyai pegangan tentang pengertian sebuah filem. Dalil-dalil dramaturgi filem bisu yang juga dipakai pada filem bersuara, kini hanyalah menjadi sebuah prinsip bentuk (vormprincipe) saja dari seni filem, yaitu: gerak yang terlihat atau dinamika dari yang visual. Dengan lebih jelas —yang menghubungkan antara bentuk filem bisu dan bentuk filem bersuara, ialah gambar-gambar yang bergerak atau gambar-gambar dalam pergerakan. Cuma itu sajalah dasar-dasar yang menghubungkan kedua periode sejarah filem itu. Filem yang pada awalnya hanya bisa dilihat saja, kini dapat pula didengar. Dan persoalan yang hangat dibicarakan akan lahirnya suara di dalam filem, ialah perbandingan antara gambar dan suara di dalam konsepsi filem. Inilah inti soal dalam estetika filem pada saat kita sekarang ini. Pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat selanjutnya dalam uraian ini akan difokuskan pada inti soal di atas. Untuk itu perlu juga diperhatikan sejarah filem di dalam 55 tahun ini.

Lumière Bersaudara
Sejarah filem dimulai dengan pendapat dua bersaudara Louis dan Auguste Lumière pada tahun 1895. Mereka telah memberi lubang-lubang kecil pada pinggir rangkaian pita filem [filem negatif] yang berisi gambar dan menjalankan rangkaian filem negatif itu seperti sebuah rantai, kemudian mereka memproyeksikannya. Pada waktu pelompatan satu gambar ke gambar berikutnya, lensa pada proyektor ditutup, dan sempurnalah ilusi dari suatu gerak pada tangkapan pandangan mata kita. Pada saat itulah lahir seni filem dalam bentuknya yang paling sederhana. Waktu itu orang belum mengatakan seni filem, tetapi kinegrafi yang berasal dari bahasa Yunani, cinematograaf, yang pada dasarnya berarti pencatat gerak. Arti inilah yang menjadi prinsip dari bentuk filem dan dasar bagi seni filem.
Lumière bersaudara mempertunjukkan program mereka yang paling pertama di akhir tahun 1895 [pemutaran perdana di depan publik pada 28 Desember 1895 di Grand Café Paris]. Program itu ialah rekaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan kejadian aktual, seperti buruh keluar dari pabrik dan kereta yang masuk stasiun (L’Arrivée d’un Train à la Ciotat/The Arrival of the Train at Ciotat, 1895). Mereka juga mempertunjukkan suatu cerita lucu yang dirancang (geensceneerd): L’Arroseur arrosé (The Sprayer Sprayed-Penyiram Tersiram, 1895). Dengan pertunjukan Lumière yang pertama itu, terlihatlah dua tipe filem yang pada zaman kita sekarang ini saling berebut posisi dan menjadi bibit dari perbedaan pendapat tentang wujud seni filem. Tipe-tipe itu ialah: 1. Filem Dokumenter (factual filem) — buruh yang keluar dari pabrik dan kereta api yang datang ke stasiun. 2. Filem Cerita atau Filem Drama (fiction filem) — L’Arroseur arrosé. Sejak itu lalu orang membuat cerita-cerita pendek dan mengadaptasikannya ke dalam filem yang didasarkan atas dalil-dalil dramaturgi pada pertunjukan sandiwara. Pemakaian seorang pemain sandiwara yang terkenal seperti Sarah Bernhardt dan Henri Lavedan untuk bermain pada sebuah filem juga dimulai. Sejak saat itu lahirlah Filem d’Art di Perancis. Dalam waktu yang cukup lama, cara kerja seperti ini telah mempengaruhi produksi-produksi filem seperti di Amerika, Jerman, Inggris, dan negara-negara Skandinavia. Di Perancis, lahir pula bentuk baru yaitu cerita-cerita fantasi yang hanya dimainkan dengan bayang-bayang dan permainan bayangan tangan. Ini adalah dasar dari filem bayangan tangan.
Tetapi orang lalu tidak puas atas pendapat mengenai pemakaian teknik-teknik tersebut. Perasaan tidak puas itu muncul hampir serentak di belahan dunia, baik di Amerika, Perancis, Inggris, dan lain-lain. Svenska di Swedia dan Nordisk di Denmark merupakan produsen-produsen filem yang penting dalam menciptakan tradisi yang baru itu. Pemain-pemain seperti Olaf Fonns, Valdemar Asta Nielsen, Lars Hanson telah melahirkan seni bagi pemain filem. Dan juga sutradara pada filem mendapat tempatnya yang tersendiri dan penting. Pertama-tama yang sadar akan hal tersebut ialah Mauritz Stiller (sutradara dari Finlandia yang memulai karirnya sebagai pemain, meninggal tahun 1928) dan Victor David Sjőstrőm (sutradara dan pemain filem dari Stockholm). Mereka ini lalu memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih, yang hanya terdapat di dalam alat kinematografi. Dari mereka lalu lahir corak filem yaitu ke-alami-an dalam filem yang dirumuskan oleh George Méliés untuk seorang pemain filem: “Pertama-tama, seorang pemain filem harus bermain dengan apa adanya.” George Méliés dengan ini telah memberikan dasar estetika untuk pemain filem. Dan dalilnya sampai pada saat ini masih tetap berlaku dan masih tetap mempunyai kebenarannya.

Studio Filem Georges Méliès
Di Amerika, yang mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang disebabkan atas ketidakpuasan itu ialah David Wark Griffith [meninggal tahun 1948], Cecil B de Mille dan Thomas Ince. Griffith menjadi penting, karena dialah yang mula-mula mempergunakan close up. Di Jerman muncul Fritz Lang, yang kini telah menjadi figur internasional. Di Perancis orang tidak lagi terikat oleh studio saja. Louis Delluc melihat bahwa ada jarak antara publik [dalam hal ini penonton] yang tidak terlalu memperhatikan pertumbuhan filem dengan seniman dan teoritisi filem. Ia pun membentuk gerakan untuk mendekatkan publik, seniman, dan teoritisi. Delluc sendiri, adalah seorang kritikus. Dengan gerakannya itu lahirlah Avantgarde, yang lalu menjadi suatu pengertian, program, dan kepercayaan yang dipeluk oleh orang-orang yang bekerja pada filem dan mempunyai perhatian pada filem.
Kegiatan-kegiatan yang timbul karena ketidakpuasan itu lalu menyebabkan sineas-sineas mencari metode kerja yang sesuai dengan tempat mereka bekerja. Dan di dalam kalangan teoritisi, orang sibuk mencari rumusan agar dapat me-wajar-kan permainan dalam filem, baik prakteknya, maupun teorinya.
Di dalam studi Walter Ruttmann (Jerman, 1887 – 1941, sutradara filem Opus IV (1925)), filem dikembalikan pada dasarnya semula yaitu pada dinamikanya yang visual, pada “Nulpunkt der Sachligkeit”. Tetapi di Perancis, produksi filem sebagian besar dipengaruhi oleh pendapat bahwa filem itu dipengaruhi oleh jalannya atau seluk-beluknya cerita serta terlebih lagi oleh pikiran-pikiran yang berhubungan secara assosiatif.
Tetapi sesudah itu lalu muncul gerakan filem Rusia yang memberikan sumbangan baru bagi kemajuan filem. Gerakan filem Rusia itu terutama dilakukan oleh S.M. Eisenstein, Pudovkin, dan Dziga Vertov.
Mereka mengemukakan pendapatnya terutama dalam hal penyutradaraan pada filem. Dengan begitu mereka telah menyumbangkan bahan-bahan baru untuk kaidah dan kritik terhadap filem dunia. Eisenstein dan Pudovkin banyak memperoleh pengaruh dari Griffith. Tetapi yang lebih berarti dalam menggunakan pendapat-pendapat Griffith ialah pengaruh Ivan Pavlov dan Freud.

Dziga Vertov
Dari Eisenstein dan Pudovkin terlahir, “psikologi montase”.
Dalil dari Pudovkin mengatakan: montase ialah dasar daripada seni filem. Dan pengaruh ini lalu masuk ke ruang-ruang kerja filem di seluruh Eropa dan Amerika. Dengan montase, menyusun gambar dari satu frame hingga menjadi rentetan frame yang teratur agar dapat melihat jalan ceritanya, bisa dilihat dari berbagai arah. Cerita itu dapat diambil dari sifatnya yang menekankan pada jalannya cerita. Oleh montase kamera menjadi lebih bergerak: dengan deformasi dari gambar-gambar, dengan meleburkannya, dapat dikuasai pengertian ruang dan saat. Kemungkinan di dalam montase ini hanya dapat dikendalikan oleh seorang sutradara yang berpribadi [subyektif]. Di sinilah terletak seni filem, seni filem yang dapat dipisahkan dari seni-seni yang lain, terlebih-lebih dari seni sandiwara. Eisenstein dan Pudovkin-lah, jago-jago dari teknik filem yang baru-baru ini diakui oleh masyarakat dunia.
Tetapi Dziga Vertov lalu datang menyatakan pendapatnya. Dan pendapatnya tersebut membuat landasan-landasan yang telah diletakkan oleh Pudovkin dan Eisenstein menjadi goyah. Dziga Vertov berpendapat, biar bagaimanapun juga, filem-filem Eisenstein dan Pudovkin tidak lain daripada pertunjukan sandiwara yang di-filem-kan. Karena filem mereka itu bukan satu “pen-catat-an” yang bersih dan penuh, tapi satu cerita yang dimainkan yang sebelumnya telah direka dan dirancang.
Dengan adanya skenario, maka isi dari filem itu bukanlah satu hidup yang dicatat dengan bersih. Dia adalah hidup yang sengaja diciptakan. Kejadian-kejadian di dalam gambar-gambar itu telah dipastikan terlebih dahulu (ingat pada arti dasar dari kinematografi di atas!). Secara teori pendapat ini benar. Tapi untuk landasan awal dalam estetika filem, keinginan untuk meminta filem murni sudah tidak mungkin sama sekali. Sedangkan kelahiran suara saja (tahun 1927) di dalam filem telah menodai pendapat filem murni ini.
Dziga Vertov menerangkan, bahwa mata kamera akan memperlihatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kebenaran ini lebih nyata dan jelas daripada apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Mata kamera ini akan membuat suatu analisa, dan dia tidak akan bohong, dia akan menghadirkan kenyataan yang murni. Tetapi dia lupa bahwa di belakang kamera itu ada manusia yang berdiri dan mata manusia inilah yang menentukan kea rah mana kamera akan ditujukan. Mata manusia ini yang akan menyeleksi apa yang akan diambilnya menjadi sebuah gambar. Manusia inilah yang menentukan pada waktu penyusunan. Apa yang harus dibuang dan apa yang harus diambil untuk membangun konstruksi filem-nya. Jadi bukanlah mata kamera yang tidak punya rasa itu. Dan juga bukan mata ini yang melakukan pekerjaan analisa. Analisa dilakukan oleh orang yang memegang kamera. Dan dialah yang memberikan interpretasi.
Yang pasti di sini dan juga yang akan menentukan nilainya, bukanlah apanya, tetapi bagaimana bahan yang akan difilemkan itu. Apalagi kalau mengingat bahwa irama dari filem itu diberikan oleh pekerjaan montase, yang juga sangat tergantung pada kepercayaan dan kemauan dari orang yang membangun filem itu, yaitu sutradara-nya. Juga pekerjaan dari seorang editor mempunyai nilai yang tidak dapat dikesampingkan.

Sergei Eisenstein
Orang sangat bahagia dengan kebenaran-kebenaran estetika yang baru mereka dapat itu, sehingga pemain filem tidak lagi dianggap sebagai bahan dramatis di dalam konstruksi drama filem. Untuk mata, memang dia dianggap sama nilainya dengan kamera tetapi untuk penglihatan yang psikologis tentu sangat berbeda. Dalam hal ini perhatian tidak lagi ditujukan pada pribadi batin seorang pemain yang masing-masing mempunyai nilai keterharuan yang khas untuk dia sendiri. Tetapi kemudian “dalil” ini juga terpaksa dimundurkan.
Hasil dari penyelidikan pada “wujud” dari seni filem —lebih tepat lagi penyelidikan akan garis-garis batas dari seni ini, ialah bahwa kinegrafi dianggap sebagai landasan awal dari seni gerak yang visual, gerak yang terlihat oleh mata. Dengan ini dapat dipastikan apa yang bisa dicapai oleh filem dan apa yang tidak. Jadi filem itu bukanlah tonil (sandiwara) yang dipotret, sastra, atau seni-seni yang lain. Harus diingat di sini bahwa hal ini sudah dilihat dan ditentukan di masa filem bisu.
Jadi estetika ini didasarkan pada kinegrafi sebagai pencatat apa yang terlihat oleh mata manusia. Pengetahuan dan pengalaman ini bermula hanya dimiliki oleh lingkungan kecil yang lama-kelamaan menjadi milik umum. Sudah tentu akan meluas ke dalam kalangan produsen-produsen filem. Tetapi akibat dari pendapat Avantgarde tersebut, lahirlah epigonen-epigonen. Orang-orang ini yang menimbulkan kebekuan pada metode-metode filem. Juga di kalangan peminat-peminat filem yang lalu terlahir pula orang-orang yang snobistis, orang-orang yang berlagak mengetahui filem dengan memakai ukuran yang sudah beku tadi. Orang dari Avantgarde yang menyatakan prinsip tadi terus menyebarkan prinsip yang mereka ciptakan itu. Bagi mereka apa yang sudah diciptakan itu bukanlah suatu kepastian dari suatu pengkhususan. Mereka tidak mengikat diri dan pendapat mereka atas dalil-dalil dan rumusan yang mereka ciptakan sendiri. Karena jika hal itu telah mencapai kemajuan maka kebenarannya akan hilang. Sedangkan epigonen dan snobisten mereka ini melekat pada dalil dan rumus-rumus tersebut. Lebih lagi dari kalangan kritisi filem yang snobistis timbul kata-kata kritik yang jiwanya sudah hilang yang tidak lagi cocok dengan keadaan estetika yang dapat dipakai dalam persoalan teknis filem. Orang lalu mementingkan “bentuk” dan sangat gembira sekali dan kagum melihat pengambilan gambar-gambar pencang-pencong, yang banyak dilakukan oleh epigon-epigon dengan memperlakukan kameranya dengan tidak punya disiplin. Ini sebenarnya harus dipertanggungjawabkan kepada kaum produsen. Mereka melihat bahwa publik sangat snobistis menerima pendapat dari orang-orang Avantgarde, lalu mengeksploitasi apa yang didapat oleh mereka ini.
Teori dari Avantgarde ini memberikan pengaruh-pengaruh yang menjernihkan, juga waktu lahirnya filem bersuara dan keadaan ini telah meminta banyak perhatian sineas-sineas dan pemain-pemain filem terhadap masalah itu. Inilah yang memberikan keinsyafan yang lebih tajam akan adanya seni pada kinegrafi, dan juga pertaliannya dengan seni-seni lain, seni-seni yang lebih tua. Seni filem hanya menjadi sebuah manifestasi dari irama yang mendahului hasil seni yang juga adalah sumber dari seni-seni yang lain.
Beberapa kritisi kerap berpaling pada zaman Avantgarde filem bisu untuk membuktikan bahwa sebagian besar dari seni filem sekarang ini tidaklah mempunyai hak untuk mendapat nama itu. Mereka berpendapat, bahwa affinitiet dramaturgi filem bersuara sekarang ini telah merenggutkan “wujud” daripada seni filem yang sebenar-benarnya. Terhadap pendapat seperti itu, bisa kita bentangkan dengan menerangkan hasil kerja seorang Marcel Carné, David Lean, Vsevolod Pudovkin (1893 – 1953), dan lain-lain dari dalil-dalil Walter Ruttmann (1887 – 1941) yang abstrak atau dari studi-studi Hans Richter yang sama tidak berartinya dengan hendak menerangkan lukisan-lukisan Rembrandt, van Gogh, Titiaan, Greco dari hasil Kandinsky yang eksperimental dan abstrak, ataupun juga sama halnya dengan menerangkan sajak seorang Yeats daripada teori pembuatan sajak dari Paul Valery.

Paul Klee
Dan juga patut diingat bahwa nilai tradisi Yunani, sandiwara yang diadaptasi dari karya sastra Shakespeare dan Ibsen, pada awalnya tidaklah ter-pondasi. Juga pada intinya, pada pelaksanaan dramaturginya, atau di dalam mise-en-scene-nya. Tetapi dilihat bagaimana nilai puitisnya atau nilai literaturnya. Kita dapat menikmatinya tanpa harus melihat lebih jauh. Membuatnya bergerak di atas panggung sandiwara adalah nilai yang datang kemudian. Nilai drama pada filem kini tidak saja lagi berada di isi sejak terdapat suara di dalam bentuk filem. Dia lebih banyak terletak di dalam bagian puitis yang menjadikannya dapat didengar dan dilihat. Hal ini dilakukan karena di sini lebih ditekankan pada apa yang terlihat (visual), karena memang inilah proses filem. Filem suaralah yang menghubungkan dunia yang dapat dilihat dan dunia yang dapat didengar.
Dalam uraian di atas, segala yang mungkin dicapai oleh kamera, yang membuat gambar itu memiliki nilainya sendiri telah dijabarkan. Mungkin masih ada lagi kemungkinan lain. Tetapi sebagai garis besar yang dapat kita anggap sebagai ukuran filemis yang berlaku sampai sekarang cukuplah pengetahuan yang telah diuraikan di atas itu. Dan sekiranya nanti masih ada lagi, pendapat baru itu hanyalah tambahan dari teori-teori dan pendapat-pendapat yang sudah memperoleh kedudukannya.
Tahun 1927 muncul masalah baru akibat kemunculan penggunaan suara pada filem. Filem-filem pertama yang dihasilkan dengan memakai suara hanya melukiskan segala yang bersuara dengan adanya suara. Saat itu seakan-akan persoalan sandiwara yang difilemkan lalu timbul kembali. Kita melihat orang bersuara dan kita dengar suaranya. Kita melihat motor lewat dengan kencang dan kita dengar derunya. Pemakaian suara pada ketika itu memperlihatkan kekurangan fantasi dalam penggunaannya. Apa yang dulu mereka cela sebagai sandiwara yang dipotret, kini kembali lagi. Dan dilihat dari sudut estetika, terasa ada yang sumbang. Dan perasaan ini telah dimaafkan ketika pemakaian suara itu baru dimulai.
Orang lalu mencari jalan untuk melepaskan diri dari persoalan ini. Dan satu-satunya jalan hanyalah mencari perbandingan yang seimbang antara yang terlihat dan yang terdengar.
Pendapat pertama yang sudah saya uraikan di atas dengan mempergunakan suara di mana gambar bersuara —yang oleh R. Arnheim disebut aliran “paralisme”, lalu diganti dengan mempergunakan “contrapuntiek” antara gambar dan suara— ialah bahwa suara itu tidaklah dipergunakan bersama dengan gambarnya. Jadi tidak naturalistis, tidak paralel dengan gambar yang terlihat. Tapi suara itu dipergunakan terlepas dari gambarnya. Bahkan kadang-kadang bertentangan. Tetapi walau begitu, antara suara dan gambar itu tetap ada kesatuannya. Misalnya: orang melihat seseorang yang membuka pintu dan masuk ke dalam kamar —pintu tidak terlihat lagi hanya orang itu di dalam kamar— lalu terdengar suara pintu yang tertutup. Dengan suara ini diketahui bahwa pintu telah tertutup.
Contoh lain dari penggunaan suara yang tidak paralel dengan gambarnya, misalnya: orang melihat rel kereta api, terdengar suara peluit kereta dan deram kereta yang mendekat; dengan demikian diketahui bahwa ada kereta yang akan datang. Bisa juga misalnya di dalam suatu kamar atau di mana saja yang tidak ada orangnya, lalu terdengar suara-suara dan ini mengingatkan kita bahwa di dekat itu ada orang. Dengan suara saja yang terdengar dan suara ini berada dalam hubungan dramatisnya, sudah mempunyai pengaruh yang sangat sugestif. Maka dari itu suatu percakapan seorang diri (monolog) atau percakapan antara dua orang (dialog) tidak perlu harus paralel dengan gambarnya sehingga gambar dan suara lebih terlihat alami. Di dalam filem Snake Pit (minggu lalu diputar di Jakarta), kita melihat wajah seorang perempuan yang sedang digoda oleh pikiran-pikirannya. Dan pikiran tersebut terdengar oleh kita dikarenakan suara itu menyatu dengan “soundtrack” pita filem. Inilah satu contoh yang sangat baik dari “monologue interieur”. Begitu juga di dalam filem “Hamlet”. Kita mendengar suatu monolog dari Hamlet, sedangkan kita hanya melihat mimik wajahnya saja. Pada pemakaian cara seperti ini, kesatuan antara mimik dan suara yang terdengar sangat tergantung kepada pemain filem itu.

Brief Encounter, David Lean, 1945
Suara itu bisa juga dipergunakan hanya sebagai hiasan [ambiens]. Contoh yang sangat baik dapat kita lihat pada filem Brief Encounter (pernah dipertunjukkan di Jakarta). Pada bagian pertemuan sepasang kekasih di akhir filem, kita melihat sepasang kekasih yang diganggu oleh seorang perempuan cerewet. Ocehan perempuan cerewet itu tidaklah mempunyai tekanan arti yang besar daripada sekedar salah satu latar saja. Hampir pada semua filem-filem yang bagus saat ini kita dapat menemukan penggunaan suara dengan baik. Cara contrapuntiek ini dapat digunakan berganti-ganti dengan cara paralel tadi. Cuma yang menjadi ukuran, harus ada perbandingan yang tepat dalam pemakaiannya. Dan di sini hanya intuisi-lah yang bekerja.
Terdapatnya faktor suara pada filem juga telah membuat dramaturgi filem tidak bisa dilepaskan seluruhnya dari bentuk seni-seni yang lain yang lebih dahulu ada. Dari seni-seni yang lain itulah filem meminjam alat-alat pernyataannya dan memberi variasinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa filem itu adalah seni yang tersendiri. Memang kalau dilihat dari sudut maksudnya, seni filem itu berdiri sendiri. Bukan maksud saya menyinggung-nyinggung hubungan filem dengan bentuk-bentuk seni yang lain. Mereka hanya berbeda dalam alat ekspresinya saja, dalam pernyataan mereka kepada pernyataan voorstoffelijke levensrytme. Sejak terdapatnya suara pada filem, seakan-akan filem kehilangan tenaga pernyataannya yang khas yaitu pernyataan gerak yang visual sebagai dasarnya.
Kalau diingat-ingat bahwa bahan-bahan penciptaan seni filem itu diambil dari sifat-sifat alatnya (kamera), maka dapat pula diterima bahwa sifat-sifat alat suara atau teknik suara mempunyai arti bagi pembangunan drama filem.
Memang dahulu ada orang yang tidak suka dengan adanya dialog di dalam filem karena dia beranggapan bahwa filem itu adalah dua dimensional, seni yang harus dilekatkan pada bidang saja. Bidang dua dimensi inilah yang membatasi seni filem itu dan filem hanya boleh berbicara di dalam batas dua dimensi itu, karena dua dimensi itu saja “bahasa” bagi seni itu. Dipandang dari sudut teoritis anggapan ini ada benarnya. Tetapi sekarang muncul filem-filem yang fotografinya demikian baik sehingga dapat membangkitkan perasaan tiga dimensi pada kita. Ini adalah pandangan kita yang biasa. Kebenaran filem yang terbatas pada ke-dua dimensi-nya, tidak mungkin bisa menerima kebenaran ruang yang tiga dimensi dari pandangan kita yang biasa itu. Karena ini juga mereka tidak bisa menerima dialog di dalam filem. Tetapi untuk kesadaran penonton, hal psikologis seperti itu tidaklah demikian.
Berhubungan erat dengan teori ini, diulang kembali oleh mereka pendapat bahwa montase itu adalah jiwa bagi seni filem. Tetapi Pudovkin sendiri telah melakukan pembenaran terhadap pendapat ini. Memang benar bahwa montase sangat penting karena montase-lah yang mengatur irama jalan cerita. Tetapi montase telah ada sejak filem lahir. Tetapi pada suatu saat tertentu, di dalam sejarahnya, dia mendapat arti yang begitu besar. Ini hanya harus dipertanggungjawabkan pada keadaan bahwa montase yang dikerjakan dengan sangat baik yaitu montase yang bergerak atas dasar-dasar esensi yang dapat memberikan pernyataan perasaan. Jadi dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa selain montase terdapat pula nilai-nilai lain yang dapat menambah sempurnanya pernyataan perasaan. Diantaranya adalah suara. Jadi dapat pula kita anggap bahwa suara juga termasuk di dalam soal bentuk atau alat yang dipergunakan untuk pernyataan perasaan.
Ada pertalian yang sangat nyata di antara berbagai macam seni. Ini sebabnya juga kita tidak perlu heran jika ada orang yang mencari persamaan antara filem dengan seni-seni yang telah ada. Terlebih pada seni sandiwara. Seni filem telah memborong anasir-anasir dan nilai-nilai seni lain ke dalam bentuknya. Tentu saja apa-apa yang berguna baginya.
Antara seni filem dan musik memiliki hubungan karena keduanya mempengaruhi waktu sebagai langsungnya waktu dengan iramanya masing-masing. Tentu saja dilakukan dengan alat masing-masing seni itu. Faktor yang menghubungan antara seni filem dan seni musik juga terdapat pada seni tari. Filem juga bidang yang berlukis dan lukisan yang mempunyai ekspresinya sendiri. Dengan ini filem memiliki hubungan dengan seni lukis. Di dalam filem drama juga terdapat manusia yang menjalankan perannya dan ini pula yang menjadikannya berkaitan dengan seni sandiwara. Tiap-tiap sutradara besar menyadari hubungan antara seni-seni ini masing-masing. Hanya saja ada beberapa tipe ahli teori filem yang tidak mau percaya akan adanya hubungan tersebut. Tetapi walau begitu, mereka masih memakai anasir ini. Hanya saja di dalam perbandingan yang mereka inginkan.
Jangan hendaknya kita lupakan bahwa percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh Avantgarde dahulu hanyalah suatu pengantar saja. Pengantar bagi studi untuk pembuatan konsepsi dramaturgi filem yang besar. Seperti juga halnya dengan pengetahuan kita pada gramatika: pengetahuan ini hanya jaminan untuk mengerti dan untuk bisa menguasai bahasa, itu saja. Dan mengukur seorang seniman dengan gramatika, terlebih lagi seniman yang sedang membuat percobaan, adalah suatu perbuatan yang sangat menggelikan. Sebuah sajak yang indah tentu dapat mengharukan kita tetapi sajak itu tidak dapat kita gunakan untuk mengukur Divina Comedia karya Dante. Begitu juga sebuah lukisan Paul Klee dapat kita rasakan keindahannya tetapi lukisan ini tidak dapat kita jadikan ukuran untuk lukisannya Rubens dan keduanya sama-sama menggunakan bahasa (perbandingan yang pertama) dan sama-sama mempergunakan cat dan kuas (perbandingan yang kedua). Begitu juga kita tidak bisa samakan antara Eisenstein dan Zola atau David Lean dengan Shakespeare. Bagaimanapun sempurnanya ciptaan mereka masing-masing, sebuah filem yang abstrak atau filem yang absolut eksperimental, bagaimana pun juga sempurnanya itu, tentu sangat berlainan dengan konsepsi filem seperti Brief Encounter. Biarpun pada kedua filem itu sama-sama digunakan dasar yang sama: irama dan anasir puitisnya, dan keduanya itu adalah manifestasi daripada “leugtend (tönend) bewegte form”. Di sini terdapat perbauran antara bentuk dan isi, dan dalam kesatuannya adalah bentuk.

Battleship Potemkine, Sergei Eisenstein, 1925
Bila ada seorang sutradara yang pandai mempertunjukkan hasilnya, yang memperlihatkan adanya hubungan filem dengan hasil-hasil seni lain, misalnya dengan tonil (sandiwara), maka ada atau tidak adanya hubungan itu adalah suatu hasil pekerjaan yang berarti. Karena dia memberikan sesuatu yang lebih daripada kecekatan teknik semata-mata. Batas-batas itu akan menjadi kabur di dalam kesatuan ciptaannya. Di dalam pembatasannya, pengetahuannya atas batas-batas itu, dan kemampuannya merasakan perbandingan-perbandingan antara seni-seni itu, di sanalah terletak kekuatan dan nilai, orisinalnya dan jeniusnya (genie-nya?) sutradara itu.
Juga isi menjadi soal bentuk. Oleh pemilihan atas apa yang terlihat, orang juga akan menetapkan bentuknya. Maka juga dialog dengan suara-suaranya menjadi bentuk dan isi. Ke-isi inilah filem menunjukan alat-alatnya dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang dikandungnya. Inilah yang menjadi sasaran atau dengan itulah alat itu membuat persetujuan dengan tidak mengatasi anasir isi ini.
Kesusastraan dan filem memiliki hubungan yang sangat elementer. Persatuan antara kesusastraan dan filem ialah sesuatu yang ditulis yang sengaja diperhitungkan dengan teknik filem. Ini dinamakan permainan filem (screen play). Jadi di dalam perkataan teknik filem, termasuk juga teknik dan permainan dari pemain filem. Jadilah tradisi tonil (sandiwara) yang dimasukkan ke dalam filem. Permainan filem adalah bentuk yang asli daripada kesusastraan filem. Dengan keterangan-keterangan yang lalu maka jelaslah bahwa filem adalah hasil kerja yang sangat kolektif sekali.
Maka seorang sineas, dengan mempermainkan kameranya mungkin bisa membuat gambar-gambar yang sangat menarik dan memakaikan latar-latar yang membuat kita terperanjat. Tetapi ini belumlah bisa dikatakan bahwa dia bisa menciptakan filem yang teratur dengan mengingat pekerjaan yang sama dilakukan oleh segala anasir-anasir yang telah diterangkan di atas.
Ada suatu bentuk filem dialog yang tidak bisa diterima, yaitu filem di mana dialog itu dicatat seperti terdapat di dalam sandiwara. Kalau kita melihat filem seperti ini maka gambar yang kita lihat itu sama saja dengan dialog yang kita dengar dan di dalam hal ini sebenarnya tidak perlu lagi kita melihat filem itu. Hal seperti ini sama juga kalau kita mendengarkan seseorang yang membaca suatu sandiwara dengan sangat baik di mana kita dapat membayangkan gambar dari alur cerita itu. Di sini filem tidak lagi menjadi seni yang berdiri sendiri. Dan perbandingan antara suara dan gambar sudah tidak ada lagi. Perbandingan yang diinginkan oleh seni filem ialah jika suara atau dialog itu terpaksa dipakai harus dapat dipertanggungjawabkan secara psikologis.
Isi, tadi saya sebut juga masalah bentuk. Bila kita mengartikan isi ini sebagai substansi masalah pengertian dan keterharuan yang membentuk “cerita”, maka dialog itu hanyalah satu variasi bentuk saja, di samping nilai rohaninya (geestelijke waarde). Di samping gambar yang terlihat (visual) dan juga perbandingan-perbandingannya, maka gambar yang dimunculkan karena suara itu kini termasuk ke dalam soal bentuk. Maksud saya, gambar yang dimunculkan karena suara dalam arti yang seluas-luasnya. Pada awalnya bentuk dari filem drama bukanlah sekedar gambar visual yang asli saja dan juga bukan tergantung pada kecekatan mempermainkan kamera atau intensitas dalam pekerjaan ini. Juga bukan keaslian, kecekatan dan intensitas di dalam penyutradaraan dialog. Bentuk drama filem yang dicita-citakan (baik filem ini, filem cerita, atau dokumenter yang di-dramatisir atau filem dokumen biasa) ialah kesatuan antara gambar dan suara. Yang masing-masing bagian berpengaruh besar atas nilai seni dari hasil total seni ini.
Perbandingan antara gambar dan suara itu dipengaruhi oleh keseimbangan dari bagian-bagian bentuk itu. Oleh sesuatu yang menyebabkan bagian-bagian di mana dia berdiri dan dibentuk menjadi kesatuan. Maka dari itu suara atau dialog harus mempunyai fungsi terhadap gambar di dalam filem tersebut. Fungsi dramatisnya tidaklah disebabkan oleh banyaknya suara atau dialog yang terdapat di dalam filem itu, tetapi kualitasnya, pentingnya suara atau dialog bagi penyempurnaan kesatuan. Dan tidak ada salahnya kalau kita ingat kepentingan fungsi sesuatu kesunyian di dalam pelaksanaan dramatik yang sugestif. Di dalam filem-filem bisu hanya dengan kesunyian yang sugestif ini saja orang bekerja. Tetapi sekarang ini, kesunyian yang sugestif itu termasuk ke dalam faktor-faktor yang berfungsi sendiri di dalam filem yang kini telah muncul organ-organ lainnya.
Pada tahun 1925, Leon Moussinac berkata: “La technique est à la base de la conception”. Ucapannya ini menyebabkan —jika kita mengakui akan kebenaran ucapannya— kerapkali kita harus mempelajari kembali ajaran estetika yang telah kita dapat. Seni filem telah menjalani kemajuannya yang tergantung dari kemungkinan-kemungkinan yang dicapai oleh pembuatan visual dan akustik. Terutama sekali filem bersuara yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan alat-alatnya. Jangan terlampau menggantungkan pendapat-pendapat kita pada dalil-dalil komposisi yang sudah dari dahulu ada karena itu akan menyebabkan ketergantungan kepada teknik.
Juga filem berwarna yang mengalami kemajuan dari naturalisme ke pemakaian warna yang harus diperhitungkan fungsinya di dalam filem itu. Jangan terlampau lekas menyerahkan segalanya kepada dalil-dalil yang mungkin pada massa tertentu sangat berharga. Perbuatan semacam itu sama saja dengan memasukkan sesuatu yang hidup ke dalam kotak-kotak yang telah mati.
Pemakaian alat-alat yang dipergunakan oleh teknik pencatat kinegrafi dan akustik tidaklah selamanya pasti. Maka untuk filem-filem yang akan datang, haruslah memperhitungkan kemajuan teknik kinegrafi dengan melihat kesempurnaan alat-alatnya.