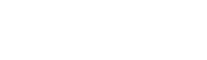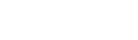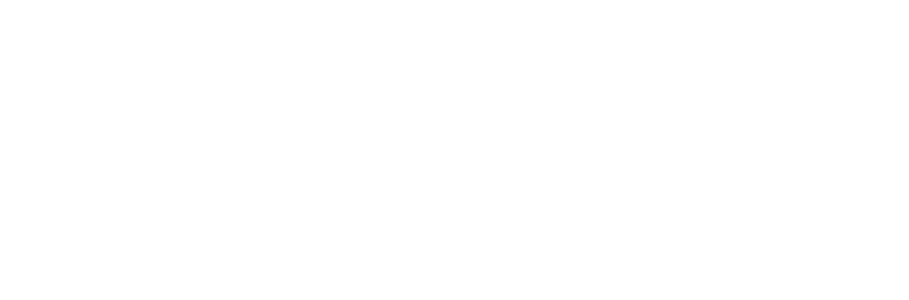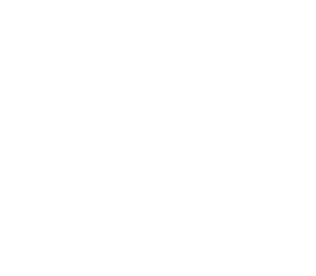SAAT MENONTON SEBUAH film, kita sering kali disergap oleh tiga elemen kunci yang saling berkelindan: (1) teks, (2) sinema, dan (3) realitas. Saya menggunakan istilah elemen alih-alih konsep karena ketiganya mengacu pada aspek struktural dalam film: teks sebagai unit material, sinema sebagai medium, dan realitas sebagai sesuatu yang dikonstruksi. Hubungan antara ketiganya tidak selalu eksplisit, bergantung pada pendekatan estetika yang diambil oleh film tersebut.
Dalam film eksperimental, misalnya, keberadaan teks sering kali subtil, bahkan nyaris tak tampak, namun justru lebih mengusik karena tersirat dalam struktur film itu sendiri. Sementara dalam film-film industri, teks bisa tampak lebih jelas, tetapi fungsinya sering kali lebih implisit—cenderung sekadar dianggap lalu oleh penonton, apalagi dipertanyakan. Tidak jarang pula, keberadaan dari ketiga elemen tersebut malah tumpang-tindih sehingga membutuhkan usaha lebih untuk mengidentifikasi bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam konstruksi sinematik.

Jika menilik pemikiran avant-garde sebelum Perang Dunia II, teks (atau tulisan—tipografis) sering kali diperlakukan setara dengan elemen visual lainnya dalam film. Ia bukan sekadar alat penceritaan (narrative bridge), sebagaimana dalam film komersial, tetapi juga bagian integral dari struktur montase yang memiliki potensi efek sinematik tersendiri. Dalam pendekatan ini, teks tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga membangun dinamika dialektis dan resonansial dalam adegan. Contoh paling jelas adalah intertitle dalam film bisu, yang bagi avant-gardis bukan sekadar alat bantu dialog atau deskripsi, melainkan bagian aktif dari susunan visual (montase) yang membentuk pengalaman sinematik secara utuh.
Dalam kajian sinema pasca-Perang Dunia II, beberapa teoretikus mulai melihat sinema itu sendiri sebagai Teks (dengan ‘T’ besar)—suatu gagasan yang menantang pemahaman konvensional tentang teks sebagai sesuatu yang eksklusif pada bahasa tertulis. Pandangan ini sungguh mempesona karena membuka kemungkinan untuk menafsirkan film sebagai pengalaman tekstual yang luas. Namun, generalisasi semacam ini juga berisiko mengaburkan posisi unik teks dalam sinema. Contohnya, hingga hari ini, intertitle dan subtitle masih lebih sering dipahami sebagai alat bantu pemahaman alur cerita, bukan sebagai bagian integral dari konstruksi sinematik.1 Selain itu, dalam banyak kasus, teks yang muncul dalam adegan—selain intertitle atau subtitle—kerap dianggap sebagai bagian dari latar, kecuali jika kamera atau frame secara aktif menyorotinya. Apalagi ketika teks hadir dalam bentuk yang bukan tulisan, perannya sebagai teks sering kali tak lagi dipertimbangkan. Misalnya, jika teks muncul dalam bentuk suara (lisan)—seperti dalam voice-over—ia cenderung langsung diasosiasikan dengan dialog atau narasi, bukan sebagai material sinematik yang memiliki peran estetis tersendiri yang bisa jadi melampaui fungsi dialog dan narasi.
Kita tahu bahwa beberapa pemikir meyakini bahwa teks adalah rezim terkuat, bahkan melebihi rezim gambar. Namun, pemahaman publik atas teks cenderung berkisar pada fakta ketercernaan serebralnya alih-alih potensi keterhayatan eksperiensialnya. Gejala inilah yang merupakan racun dalam film-film yang berorientasi hiburan—cenderung menjadi tontonan yang “mudah cerna” semata-mata. Sesuatu yang, sejauh yang saya ketahui, diperangi secara estetik oleh Hafiz Rancajale.
***

BACHTIAR, karya Hafiz, adalah salah satu contoh film yang dengan sadar menekankan perhatiannya pada persoalan teks dalam sinema. Eksperimen Hafiz menunjukkan bagaimana sinema seharusnya memperlakukan teks sebagai sesuatu yang tidak dibiarkan berlalu begitu saja, sekaligus bagaimana sinema secara elegan mengakui keterbatasannya sendiri. Dalam proses ini, film justru mengekstrak energi hidup dari teks sebagai solusi bagi keterbatasannya itu.
Menariknya, meskipun mengusung pendekatan eksperimental, BACHTIAR masih tetap mempertahankan ketercernaan naratif. Sebagian teks muncul sebagai elemen yang tetap berfungsi deskriptif dan informatif. Suara Hafiz yang bernarasi, misalnya, memainkan peran penting dalam membantu penonton mengikuti alur film. Image dari dokumen tertulis yang berisi instruksi penerbitan film-film PFN (Produksi Film Negara) tahun 1960-an, contoh lainnya, ditampilkan begitu jelas untuk menunjukkan jumlah dan judul-judul film apa saja yang boleh beredar, disensor ulang, dibekukan, dan dihancurkan oleh negara.
Akan tetapi, sebagian teks lainnya hadir dengan mencolok sebagai elemen yang memanifestasikan luasnya potensi teks itu sendiri: performatif, disruptif, dan konfiguratif sekaligus. Dari sinilah nanti kita bisa kembali ke persoalan historiografi sinema Indonesia, dan secara lebih spesifik, mencapai apa yang bisa kita persoalkan sebagai “realitas historiografis.”
***
Ave Verum Corpus belum berhenti mengalun ketika, setelah adegan di kebun malam hari,2 kamera film BACHTIAR bergerak hand-held di dalam sebuah gedung yang kita kenal sebagai Sinematek Indonesia—sebuah objek yang menjadi “protagonis” selain Misbach Yusa Biran di film Hafiz terdahulu, Anak Sabiran, Di Balik Cahaya Gemerlapan: Sang Arsip (2013). Kita melihat tiga kru film BACHTIAR—Luthfan, Pandji, dan Andra—memasuki lift menuju ruangan yang diyakini menyimpan arsip-arsip terkait Sinema Kiri Indonesia. Dari narasi Hafiz, kita mengetahui bahwa salah satu film karya Bachtiar Siagian yang dulu diduga hilang, Violetta (1964), ditemukan di gedung tersebut. Bagaimanapun, Sinematek Indonesia nyatanya tidak memiliki arsip yang lengkap tentang sinema kiri; lembaga arsip film yang konon tertua di Asia Tenggara itu menyimpan lebih banyak misteri ketimbang informasi utuh mengenai sejarah perfilman nasional.

Adegan di Sinematek Indonesia ini memperlihatkan sebuah peristiwa yang, meskipun singkat, memiliki signifikansi sebagai pangkal pembahasan kita. Ketika suara lantunan lagu klasik perlahan menghilang, ketiga kru terlihat meneliti tumpukan arsip di meja. Di tengah diskusi dengan Luthfan—tentang kecenderungan sutradara Indonesia era 1960-an yang lebih menitikberatkan aspek ideologis daripada artistik—Pandji dan Andra menemukan, lalu membaca dengan suara nyaring, halaman arsip yang mencatat daftar nama juri Festival Asia Afrika 1964. Tiga di antaranya berasal dari Indonesia, yaitu Basuki Resobowo, Sitor Situmorang, dan Bachtiar Siagian.
Selanjutnya, sebuah shot singkat sekali lagi menampilkan pemandangan kebun malam hari, sebelum adegan berpindah ke dalam bioskop mini. Di sana, Indra dan Bunga masih duduk di bangku penonton, bergantian membaca dengan suara nyaring sebuah teks karya Bachtiar Siagian. Gambar Luthfan, Pandji, dan Andra yang masih membolak-balik halaman arsip di Sinematek Indonesia sempat menyela aksi membaca teks di bioskop mini tersebut—adegan penyela ini berfungsi sebagai transisi antara aksi pembacaan Indra dan Bunga.

Sebagaimana yang dapat disimak, Indra membacakan tulisan yang bercerita tentang asal-usul Bachtiar sebagai cucu sepasang suami-istri yang bekerja sebagai buruh perkebunan tembakau di Deli, sedangkan Bunga membacakan tulisan yang menceritakan pengalaman Bachtiar ketika aktif sebagai anggota Parindra (Partai Indonesia Raya) cabang Binjai, menulis naskah teater (Doktor Darman dan Angin Berkisar), dan dijatuhi sensor oleh pemerintah kolonial. Dari sudut pandang Bachtiar, kita pun mengetahui bentuk brutalitas penjajah Jepang terhadap kaum pribumi dan peranakan.
Aksi membaca teks kemudian terjeda seiring kembalinya alunan latar Ave Verum Corpus. Suara Hafiz pun terdengar, menarasikan identitas Indra dan Bunga sebagai dua anak Bachtiar Siagian dari pernikahannya dengan Yeni—kakak-beradik yang aktif mengumpulkan arsip ayah mereka. Hafiz juga menginformasikan bahwa, sejak tahun 2012, Bunga telah menjadi anggota Forum Lenteng, organisasi yang memproduksi film BACHTIAR. Melalui peran serta Bunga dan Indra, Hafiz serta kru BACHTIAR mendapatkan akses ke arsip-arsip Bachtiar Siagian yang sangat terbatas, yang sebagian besar berupa surat-menyurat dengan keluarga dan kolega, naskah teater, draf novel dan cerpen, serta catatan harian. Sementara itu, arsip terkait perfilman Bachtiar tergolong sangat sedikit.

Adegan pun berlanjut ke sebuah ruangan tempat Indra dan Bunga menyimpan arsip-arsip Bachtiar Siagian yang berhasil mereka kumpulkan. Bersama Hafiz dan kru film BACHTIAR, mereka membuka beberapa dokumen untuk menelusuri riwayat Bachtiar, termasuk aktivitas surat-menyuratnya selama menjadi tahanan politik, seperti ketika di Pulau Buru. Salah satu arsip berupa kartu pos—sejauh yang dapat ditangkap kamera dan dijelaskan Bunga—menunjukkan sekilas mekanisme sensor kolonial terhadap persebaran teks dalam konteks kegiatan surat-menyurat.
Dalam adegan di ruangan arsip sederhana itu, juga terjadi perbincangan langsung antara Hafiz (yang berada di balik kamera) dengan Bunga dan Indra mengenai status Bachtiar Siagian sebagai sutradara kiri dan cara mereka memahami posisi tersebut. Percakapan mereka terselingi oleh adegan di sebuah bioskop mini lain—penonton yang pernah berkunjung ke markas Forum Lenteng mungkin akan mengenali bioskop tersebut sebagai Bioskop Forlen. Kamera BACHTIAR membidik ke arah layar bioskop yang menampilkan cuplikan Violetta—film karya Bachtiar Siagian yang ditemukan Forum Lenteng di Sinematek Indonesia pada 2012.

Saat adegan kembali berpindah ke ruangan arsip-arsip Bachtiar, kamera memfokuskan bidikan pada Bunga yang menjelaskan bagaimana wacana tekstual—salah satunya buku Krishna Sen—membentuk definisi pertentangan ideologis antara Bachtiar Siagian dan Usmar Ismail. Penemuan Violetta kemudian menjadi titik balik penting dalam kajian sejarah Sinema Kiri Indonesia. Menurut Bunga, fakta filmis Violetta membuka perspektif baru dalam memahami sejarah sinema kiri, sekaligus bisa menjadi titik awal untuk mendekonstruksi konsep standar tentang Kiri. Keberadaan dan pendekatan artistik Violetta juga menunjukkan hubungan erat antara ideologi LEKRA dengan visi awal negara Indonesia dalam membangun perekonomian nasional. Estetika Violetta mencerminkan komitmen sinema kiri untuk berada di garda depan pengembangan ekonomi bangsa.
Indra kemudian menambahkan—ketika kamera kembali menangkap aktivitas orang-orang di ruangan arsip yang membolak-balik beberapa dokumen—bahwa Bachtiar Siagian tetap produktif bahkan saat dia berada di penjara. Konon, Bachtiar Siagian berhasil menulis dan mementaskan sebuah naskah teater yang berjudul Janji di Batas Takdir.

Adegan berpindah sekali lagi ke bioskop mini tempat Indra dan Bunga membaca tulisan-tulisan Bachtiar Siagian tadi. Kali ini, Bunga membacakan tulisan ayahnya yang berkisah tentang pengalaman pertama membuat film. Dari teks ini, kita mengetahui bahwa dengan kamera 16mm, Bachtiar Siagian menjalankan tugas dari seorang Jepang untuk membuat film semi-dokumenter tentang Tonarigumi. Di momen itu, Bachtiar Siagian belajar langsung dari orang Jepang sekaligus menggali ilmu dari tulisan-tulisan Pudovkin. Pada 1949, dengan bantuan Adam Malik, Bachtiar Siagian mendirikan Mutiara Films dan memproduksi film pertamanya, Kabut Desember, menggunakan 35mm serta menerapkan teori-teori Pudovkin yang telah dipelajarinya.
***
Sekuen yang saya paparkan di atas—yang berlangsung sepanjang +/- 30 menit setelah sekuen pembuka—sudah cukup menjadi petunjuk awal untuk memahami bagaimana metode dan gaya sinematik Hafiz dalam mengkonfigurasi biografi historis sosok Bachtiar Siagian. Kekhasan utama dalam metode dan gayanya ini adalah memposisikan kehadiran arsip, yang berbentuk teks-teks, secara mencolok, sebagai sesuatu yang bukan hanya tidak akan, tetapi juga tidak boleh diabaikan oleh penonton.
Akan tetapi, teks-teks yang bagi Hafiz tidak boleh diabaikan itu hadir sebagai dirinya sendiri, bukan ditutur-ulangkan melalui perspektif dan interpretasi orang ketiga, dan bukan pula sekadar diobjektivasi (diamati) oleh kamera. Strateginya ialah transfigurasi teks menjadi “peristiwa aktif”, dalam arti: teks dilafalkan secara langsung oleh subjek di depan kamera. Dalam hal ini, aksi membaca dengan suara nyaring menjadi pilihan artistiknya.

Sebagaimana yang dapat diamati, motif tersebut kembali berulang pada beberapa sekuen setelahnya. Adegan Bunga membaca teks tulisan Bachtiar Siagian di ruangan arsip akan muncul di pertengahan film (di menit ke-73), yaitu adegan pembacaan surat balasan Bachtiar Siagian untuk Salim Said. Sementara itu, di bioskop mini, pada beberapa menit menjelang akhir film (di menit ke-105), Bunga akan membacakan tulisan Bachtiar Siagian lainnya yang bercerita tentang pengalamannya memproduksi film Turang (1957), mendapat kritikan sebagai “orang politik yang masuk film”, terpilih sebagai representatif Rencong Films, dan—bersama seorang revolusioner bernama Amir Jusuf (dari Radial Films) —merancang suatu program Perjuangan Film Nasional dalam rangka memboikot film-film Amerika. Di tulisan itu, Bachtiar Siagian juga bercerita tentang penyelenggaraan Festival Asia-Afrika di Jakarta pada 1964, di mana ia berperan sebagai salah seorang ketua panitia.

Di samping penghadiran aksi membaca teks dengan suara nyaring, motif lainnya dalam gaya ungkap BACHTIAR adalah intensi penghadiran—ke dalam frame—respons ekspresif orang-orang yang berhadapan langsung dengan teks arsip tersebut. Pendekatan Rouchian pun menjadi relevan: bagaimana gestur para kru ketika memegang dokumen, bagaimana ekspresi deuteragonis ketika membaca teks, dan bagaimana opini personal mereka terhadap arsip-arsip yang ada, serta bagaimana pula antusiasme-tak-sengaja dari beberapa orang ketika menyadari atau mendapati adanya arsip baru (seperti yang dapat dilihat dalam adegan di kediaman Saleh Oemar dan Daniel Irawan). Semuanya dibiarkan mengalir, sebagai peristiwa alamiah, lantas direkam untuk kemudian ditampilkan sebagai selaan-selaan “di sekeliling” peristiwa membaca teks, sehingga montase adegan menjadi sangat khas dengan adanya ulang-alik kesadaran, antara “di dalam arsip” dan “di luar arsip”. Montase semacam ini, menurut saya, justru berhasil menguraikan bagaimana dunia hari ini sebenarnya berinteraksi dengan masa lalu yang telah termediasi, di dalam suatu situasi yang jujur apa adanya.

Yang mesti digarisbawahi, saya pikir, metode dan gaya sinematik Hafiz yang semacam itu bukanlah suatu kebetulan. Sebagaimana saya meyakini bahwa gaya ini merupakan hal yang benar-benar dikonstruksi secara matang, gelagat artistik yang sama sebenarnya dapat kita temukan pula indikasinya pada karya-karya Hafiz sebelum BACHTIAR, terutama dalam kaitannya dengan cara si sutradara mempersoalkan teks sebagai material dan logika berbahasa.
***
Perlu diingat bahwa, dengan menyebut teks, saya tidak hanya mengacu pada bentuk tertulis (tipografis), tetapi juga pada bentuk lisan. Apalagi, dalam hal ini, kita bukan sedang berbicara tentang sesuatu dalam konteks sastra, dan bukan pula soal film dalam konteks era film bisu. Dengan kata lain, teks bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi juga sesuatu yang terdengar. Teks adalah kumpulan kata yang membawa makna, yang karena keterkumpulannya itulah ia menjadi bahasa. Inilah pengertian utuh dari teks (baik sebagai konsep maupun elemen karya), sebagaimana yang saya maksudkan dalam ulasan ini.
Dan jika kita meninjau karya-karya Hafiz yang lain, bukan hanya film, kita akan menyadari bahwa teks, sebagaimana pengertian di atas, memang merupakan persoalan yang penting baginya. Contoh pertama dapat kita tinjau pada karya seni video-audio Hafiz tahun 2004 yang merespons arsip audio sejarah seni rupa Indonesia. Karya ini merupakan olahan artistik atas rekaman suara S. Sudjojono, Sanento Yuliman, Toety Herati, Jim Supangkat, Oesman Effendi, Suhardi, dan D.A. Perasi.

Dalam karya tersebut, Hafiz dengan sadar menyikapi rekaman-rekaman suara itu sebagai teks, atau lebih tepatnya, ia memahami bahwa teks adalah logika yang bekerja di dalam materi audio yang diolahnya. Sebagai lisan, ada banyak elemen ungkapan dalam rekaman-rekaman itu yang tidak eksis dalam alam tertulis. Aspek itulah yang justru menjadi poin yang diproblematisir Hafiz. Saat kita menyadari poin itu, kita pun akan melihat relevansi dari transfigurasi material yang dilakukan Hafiz terhadap rekaman-rekaman suara tersebut ke bentuk audio visualizer: pemetaan terhadap ungkapan-ungkapan “non-tulisan” dapat dimungkinkan lewat tinjauan frekuensi suara sehingga logika tekstual dalam lisan tetap dapat dialami secara visual meskipun kita tidak lagi melihat mimik wajah si pengucap.
Visualisasi atas frekuensi suara, secara unik, memampangkan semacam “kodifikasi tertulis”—bagaikan scoring—yang punya kemungkinan lebih luas daripada sekadar bahasa tulis konvensional. Dengan demikian, pencernaan serebral tetap dapat dimungkinkan, tetapi cara ini sekaligus juga menciptakan visualitas bergerak yang mensyaratkan penghayatan ritmis untuk bisa menikmatinya lebih dalam. Dengan kata lain, Hafiz mempersoalkan teks di dalam karya seri tersebut bukan hanya sebagai “keterbacaan” (atau readability), tetapi juga sebagai “keteralamian” (perceptibility—atau “experience-ability”).
Sementara itu, dalam konteks sinema, kita bisa kembali mempertanyakan hal yang sudah saya singgung di awal esai ini: apakah yang dimaksud dengan teks yang “melampaui dialog” atau “melampaui narasi” di dalam film? Adegan penutup dalam film Hafiz yang berjudul Marah di Bumi Lambu (2014) bisa menjadi contoh untuk menjawab pertanyaan ini.
Kalimat ijab kabul yang berkali-kali keliru diucapkan oleh protagonis film Marah di Bumi Lambu, di dalam adegan penutupnya, memiliki fungsi yang melampaui dialog, karena keberadaannya menjadi “paparan melelahkan” yang merangsang kegelisahan pada diri penonton terhadap hubungan antara teks dan norma sosial. Teks tidak sesederhana kemudahannya untuk dibaca dan diucapkan. Dalam momen tertentu, seperti ritual pernikahan, kesempurnaan pelafalan justru menentukan kepastian dan keabsahan maknanya dalam sudut pandang konsensus.
Dengan kata lain, karena ujaran ijab kabul itu adalah teks maka “kesalahan” tidak bisa dianggap sepele. Juga sebaliknya, karena “kesalahan” itu tidak bisa diabaikan (sehingga si penghulu mengharuskan protagonis mengulanginya) maka kata-kata itu harus dipahami sebagai teks, bukan sekadar dialog. Hafiz dengan sengaja menangkap momen ijab kabul yang tidak lancar justru untuk menegaskan identitas ungkapan itu sebagai teks daripada sekadar materi percakapan.
Dan jika kita kembali ke BACHTIAR, beberapa adegan di film ini sudah pasti mengingatkan kita pada karakteristik lain yang juga muncul dalam Anak Sabiran—film yang saya anggap sebagai salah satu karya seminal Hafiz. Sehubungan dengan topik teks dalam sinema, kekhasan kedua film ini terletak pada adegan membaca teks. Kamera secara intensional merekam aksi subjek membaca dengan suara nyaring karya-karya tulis yang pernah dibuat protagonis filmnya. Di dalam Anak Sabiran, subjek-subjek yang membaca adalah Hafiz dan kru, sementara di BACHTIAR, yang beraksi membaca adalah dua deuteragonisnya (Bunga dan Indra, dua tokoh yang paling dekat dengan protagonis). Menurut saya, bagian ini merupakan aspek paling menarik dari BACHTIAR, sesuatu yang penting disoroti dalam upaya kita merefleksikan kembali hubungan antara teks, sinema, dan realitas.
***
Dalam BACHTIAR, Hafiz mengaktivasi arsip secara sinematik: teks tidak dibiarkan pasif, tetapi di-perform-kan—menjadi teks performatif—sekaligus dijukstaposisikan dengan tayangan tentang aktivitas responsif yang nyata dari manusia terhadap teks itu sendiri. Aktivasi performatif ini secara sengaja menunjukkan sifat dan identitas fragmentaris arsip, di mana teks-teks yang disandingkan adalah teks-teks yang merupakan pecahan-pecahan yang sebenarnya tidak kontinu satu sama lain.
Sementara itu, jika diamati lebih jauh, aksi membaca teks dengan suara nyaring itu berlangsung dengan khusyuk, dalam arti: Indra dan Bunga membaca tulisan Bachtiar Siagian sebagaimana mestinya, apa adanya, bukan dengan “berperan” (acting). Karenanya, gaya ungkap sinematik Hafiz ini mutlak tidak bisa disamakan dengan film-film semacam Letters from Baghdad (2016)-nya Sabine Krayenbühl dan Zeva Oelbaum—yang diproduksi dalam pengaruh wacana Hollywood—ataupun dengan film macam La Chinoise (1967)-nya Godard. Bahkan, tidak pula sama dengan Los rubios (atau The Blonds, 2003)-nya Albertina Carri yang relatif lebih dekat ke gaya dokumenter eksperimental.
Sebab, dalam konteks sinematika BACHTIAR, meskipun si pembaca sadar bahwa aksinya sedang direkam untuk kebutuhan film, gelagat subjek saat membaca terjadi secara alamiah, bukan dibuat-buat, bukan dalam suatu modus yang berupaya mengejar kesempurnaan dan kelancaran vokal. Aksi membaca teks adalah memang untuk ditunjukkan [ke penonton], tetapi bukan sebagai “pertunjukan”. Inti yang membedakannya, ialah: subjek membaca teks untuk mengalami arsip, bukan “menjadi” si penulis teks. Dengan kata lain, membaca teks dalam BACHTIAR adalah membaca sebagai performance alih-alih performing.
Di samping adanya kesadaran teks sebagai sesuatu yang performatif itu, BACHTIAR juga mendemonstrasikan teks sebagai sesuatu yang berpotentsi disruptif. Secara lebih spesifik, teks-teks dalam BACHTIAR diolah menjadi disruptif untuk beroperasi pada tiga lapisan, yakni dramatik (narasi), puitik (gaya ungkap), dan epistemik (wacana).
Pada lapisan pertama—terutama dengan adanya aspek “performans membaca teks” itu—teks sesungguhnya menjadi elemen yang bebas dari narativitas; tujuan penghadirannya memang didasarkan pada kejanggalannya dalam narasi. Ini sangat terlihat dalam adegan di bioskop mini: Indra dan Bunga ujug-ujug membaca teks di bangku penonton bioskop, tanpa alasan yang dijelaskan secara naratif. Teks yang mereka baca juga tidak punya hubungan harfiah dengan tindakan dan lokasi pembacaan. Kehadiran adegan ini, di dalam konstruksi BACHTIAR secara keseluruhan, bagaikan sesuatu yang berada di dalam tanda kurung, atau yang menjadi catatan kaki penting, yang tidak bisa untuk tidak disimak.
Kita mungkin bisa berdebat lebih jauh terkait adegan di mana Bunga—di ruangan arsip-arsip Bachtiar Siagian—membaca surat balasan Bachtiar Siagian untuk Salim Said. Bisa jadi Anda berpendapat bahwa tindakan Bunga di adegan itu merupakan konsekuensi naratif karena sebelumnya ia menyinggung dokumen tersebut saat berbincang dengan kru film BACHTIAR. Akan tetapi, kita patut bertanya: apa alasannya surat itu harus dibaca utuh? Agar berfungsi sebagai narasi? Untuk mengetahui informasi yang lebih dalam? Saya pikir, tentunya alasan Hafiz tidak sesederhana itu. Saya lebih setuju untuk menyatakan bahwa intensi BACHTIAR lebih bersifat ornamentalis—aksi membaca teks itu memainkan fungsi stilisasi, yang kejarannya adalah puitik (operasi di lapis kedua) ketimbang dramatik.

Pada adegan membaca teks di dalam bioskop, ornamentalisasi sinematik relatif lebih mudah diidentifikasi: tanpa cut, kamera bergerak perlahan ke kanan dan ke kiri, serta maju dan mundur, selama Indra dan Bunga membaca. Gerakan kamera semacam ini, di satu sisi, menciptakan suatu kesan reflektif dan meditatif, mengikat perhatian penonton pada kekhusyukan proses pembacaan yang sedang berlangsung. Tapi pada sisi yang lain, kita tidak bisa membantah keunikan situasi “staging” yang dipilih si sutradara, yang nyatanya juga tetap menghasilkan suatu jarak antara penonton dan teks yang diperformkan. Namun begitu, di sinilah poinnya: penciptaan jarak di situ bukan sebagai bentuk objektivasi, tetapi sebagai modus pengasingan (‘defamiliarisasi’) Brechtian yang justru merangsang keterlibatan intelektual. Kombinasi antara pembacaan teks secara khusyuk, dengan kamera yang bergerak “menjaga” sekaligus “mengganggu” fokus penonton, merupakan teknik aktivasi disruptif yang mengubah arsip menjadi suatu pengalaman sensorial, ketimbang objek yang dibedah-bedah seperti yang biasanya dilakukan para peneliti.

Sedangkan alasan bagi aksi Bunga membaca surat Bachtiar Siagian untuk Salim Said, saya berpendapat bahwa sasaran Hafiz lebih kepada kebenaran filmis-humanis daripada sebab-akibat naratif. Surat itu dibaca bukan sekadar untuk mengetahui informasi yang lebih dalam, yang barangkali bisa menjelaskan—atau dijelaskan oleh—hal-hal lain di luar peristiwa itu sendiri, yang muncul di adegan baik sebelum maupun sesudahnya. Alasan yang lebih mencolok bagi saya adalah untuk menyimak respons ekspresif subjek yang membaca teks arsip itu sendiri: ekspresi-ekspresi kecil dan gestur-gestur halus yang terjadi secara sadar tidak sadar tatkala si pembaca menghayati teks arsip, yang melalui ekspresi dan gestur itu pulalah penonton diajak untuk mengalami arsip sebagai peristiwa puitik yang manusiawi. Teks dalam sinema, pada adegan itu, menjelma menjadi ekspresi sinematik justru karena kepekaan konstruktif BACHTIAR terhadap ekspresi manusiawi para subjek terhadap arsip.
Dengan cara demikian, disruptivitas teks dalam BACHTIAR pun menyentuh lapisan epistemik (wacana—valid atau tidaknya suatu pengetahuan). Teks arsip, yang keberadaannya di dalam film diperlakukan secara khusus, menggugah pemahaman kita tentang wacana sinema dan arsip sekaligus. Bentuk komunikasi subjek-subjek dengan arsip tekstual, baik dengan cara menyentuh langsung materialnya maupun dengan membaca nyaring isinya, dapat menjadi suatu paparan untuk memahami bahwa apa yang disebut arsip pada dasarnya bukanlah semata-mata tentang “ketersediaan fisik”, tetapi juga tentang kapan dan bagaimana dia ditemukan, diakses, dan dialami kembali; bukan tentang bagaimana ia semata-mata eksis secara material, tetapi juga bagaimana ia hadir di dalam dan sebagai pengalaman subjektif seseorang.
Disrupsi di lapisan ketiga itu, secara bersamaan, juga menunjukkan potensi konfiguratif teks, yang mana hal ini berhubungan dengan bagaimana sinema lebih layak dipahami sebagai medium untuk mengkonfigurasi alih-alih merepresentasikan sejarah. Adegan-adegan aksi membaca teks di dalam BACHTIAR, nyatanya, merupakan bagian dari montase unik Hafiz yang memadu-padankan kesadaran “di dalam” dan “di luar” arsip, yaitu montase yang di dalamnya gambar-gambar tersusun secara dinamis, menegaskan hubungan ulang-alik, cut-to-cut, antara keadaan khusyuk saat membaca teks, keadaan riuh saat memilah-milah arsip, dan jeda refleksif saat memberikan pendapat mengenai arsip. Ini terindikasi dalam sekuen yang menunjukkan cut-to-cut antara aktivitas di Sinematek Indonesia (tempat Luthfan, Pandji, dan Andra memeriksa arsip) dan ruang bioskop mini (tempat Indra dan Bunga membaca teks), atau pada sekuen di ruangan arsip-arsip Bachtiar Siagian—antara kegiatan membuka-buka halaman dokumen, aksi membaca teks, dan percakapan mengenai arsip yang sedang ditinjau oleh para subjek di dalam film.

Montase ulang-alik yang tercermin pada sekuen tersebut merupakan satu contoh dari fungsi sinema untuk menyusun ulang fragmen-fragmen sejarah. Dengan menyusun maka yang menjadi tujuan bukanlah validasi kronologis, melainkan produksi makna yang terbuka. Potensi transformatif lebih utama dibandingkan dengan kebenaran objektif. Inilah sebuah proses di mana sejarah tidak sekadar dikukuhkan sebagai fakta yang tetap (untuk melanggengkan narasi mapan), melainkan senantiasa diinterpretasi sesuai dengan konteks dari ruang-ruang pengalaman tertentu, yang dalam konteks BACHTIAR adalah ruang pengalaman sinematik. Dengan menyasar keterbukaan ini, kita sebenarnya sedang berupaya melestarikan keberagaman possible narations/narratives.
Kesadaran sinematik atas potensi konfiguratif teks, selanjutnya, juga mencerminkan kerendahhatian sinema terhadap kedudukan teks itu sendiri. Dalam keterbatasannya—dan kesadarannya untuk tidak melulu—menangkap “kebenaran” historis, sinema justru merangkul teks sebagai sebuah pendekatan, bukan terhadap sejarah, tetapi terhadap bagaimana sejarah diwacanakan. Terkait hal itu, Hafiz menerapkan strategi artistik yang menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya ditemukan dalam jejak materialnya (dokumen, catatan, rekaman), tetapi juga dalam pengalaman pembacaannya.

Sampai di sini, kita pun patut menyadari bahwa apa yang sebenarnya sedang diurai oleh BACHTIAR bukanlah realitas historis, melainkankan realitas historiografis. Dalam BACHTIAR, montase ulang-alik antara subjek (si pembaca) dan arsip (teks yang dibaca) tidak sekadar menampilkan hubungan linear antara masa lalu dan masa kini. Sebab, sebagai suatu realitas historiografis, sekuen-sekuen aksi membaca teks justru menciptakan suatu ketegangan produktif yang membuka pemaknaan alternatif atas sejarah berdasarkan pada bagaimana ia dihadirkan, dialami, dan ditafsirkan kembali di dalam film. Posisi pembuat film bukan dalam kedudukannya sebagai sang-maha-tahu, melainkan sebagai subjek yang berproses. Dengan demikian, sinema bukan lagi alat afirmasi kebenaran sejarah, tetapi medium konfigurasi yang memposisikan sejarah sebagai pengalaman dalam keberlanjutan dialogisnya dengan masa kini. []
Endnotes