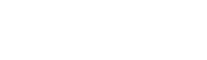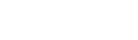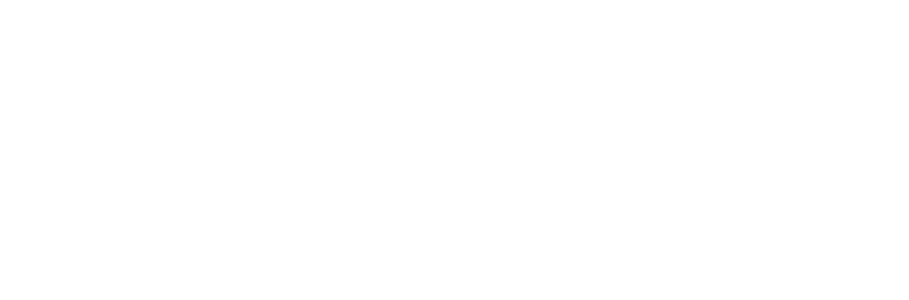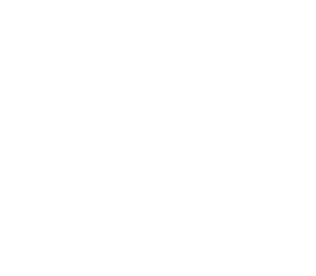Bagi seorang sutradara yang memandang sinema sebagai bentuk pengetahuan, menyatakan falsafah sinemanya di dalam film sejak cerita baru akan dimulai, kadang kala, menjadi hal yang esensial. Falsafah itu mendasari estetikanya tapi sekaligus menjadi simpulan atas watak artistik yang ia realisasikan dalam konstruksi filmnya secara keseluruhan. Dan memang, kesimpulan tidak selalu harus hadir di penghujung film; yang lebih penting adalah bagaimana ia berdinamika di benak penonton. Pendekatan film esai pun menjadi pilihan yang masuk akal, mengingat sifatnya yang terbuka, intertekstual, dan dekonstruktif. Karakteristik tersebut memungkinkan pernyataan atau simpulan tematik terus diurai kembali oleh penonton seiring mereka menyimak sekuen demi sekuen di sepanjang film.
Pendekatan itulah yang dilakukan Hafiz dalam BACHTIAR, film terbarunya yang menelusuri jejak kehidupan, pemikiran, dan aktivitas kesenian dari seorang sutradara kiri Indonesia: Bachtiar Siagian. Diproduksi tahun 2025, film berdurasi lebih-kurang dua jam ini rilis perdana secara internasional di International Film Festival Rotterdam ke-54, Belanda, dalam program penayangan Cinema Regained—kumpulan film dengan “suatu lingkup kenangan dan imajinasi kolektif yang menawarkan karya klasik yang telah dipulihkan, dokumenter tentang budaya film, dan eksporasi warisan sinema.”1
Mungkin ada yang berpendapat bahwa Hafiz, seperti kebanyakan sutradara lainnya, mencoba menghadirkan hook—adegan pembuka yang dirancang untuk memikat dan mempertahankan perhatian penonton hingga film berakhir—di awal filmnya. Namun, bagi saya, sekuen pembuka BACHTIAR terasa sangat istimewa karena daya pikat yang dimaksud merupakan efek dari fungsinya sebagai pewujudan ringkas dari kerja audiovisual dokumenter yang ideal: gambar dan suara, baik sebagai konten maupun bentuk, bukan untuk mempercantik narasi, melainkan beroperasi sebagai elemen-elemen montase yang memiliki relevansi mendasar dalam keterkaitan mereka satu sama lain, baik keterkaitan dari segi substansi maupun struktur/accident mereka masing-masing. Yang juga memukau dari sekuen berdurasi lebih-kurang lima menit ini adalah, selain tampil begitu puitik, gaya ungkapnya bersifat self-reflexive—secara sadar merefleksikan keberadaan BACHTIAR sendiri sebagai medium film—dan sekaligus meta-reflexive, karena melangkah lebih jauh dengan mengajukan posisi kritis terhadap proses refleksi itu.
Secara khusus, sekuen tersebut mempertanyakan keterkaitan antara film sebagai medium—yang sering berguna untuk merekam peristiwa—dengan historiografi sinema Indonesia, yakni bagaimana sejarah sinema itu sendiri dituliskan/diwacanakan. Oleh karena itu, bagi saya, memahami hook dalam BACHTIAR bukan sekadar persoalan mengapresiasi pembukaannya, melainkan sebuah langkah awal untuk menelusuri kontekstualitas film ini, baik sebagai “film tentang Bachtiar”, pada satu sisi, maupun “film tentang sejarah sinema Indonesia”, di sisi yang lain.

Sebagaimana yang dapat disimak pada adegan pembuka film itu: Ave Verum Corpus-nya Mozart mengalun lembut saat kamera bergerak maju perlahan, merekam pemandangan hamparan kebun di malam hari. Cahaya-cahaya gemerlap di kejauhan tampak seperti kumpulan titik yang membentuk garis lurus horizontal, membelah kegelapan (bidang hitam di dalam frame).

Musik terus mengalun ketika shot berpindah ke dalam sebuah bioskop mini yang hampir kosong; kamera mengarah ke deretan bangku penonton yang berwarna merah tua. Hanya ada tiga orang yang tampak di ruangan itu: Bunga Siagian dan Indra Siagian—dua deuteragonis di film ini, karena protagonisnya tentu saja adalah sosok Bachtiar Siagian—serta Hafiz. Tak terdengar jelas percakapan mereka, tapi berdasarkan gesturnya, kita bisa menerka bahwa Hafiz sedang memberikan instruksi tertentu kepada Bunga dan Indra. Hafiz lalu berjalan mendekati kamera dan kita pun mendengar suaranya berkata, “Oke…?! Sound…?! Dah…! Mulai!” Setelah itu, kamera sekali lagi bergerak maju perlahan, memperlihatkan Bunga dan Indra yang duduk agak berjauhan—Bunga di posisi kiri kamera, sedangkan Indra di kanan. Dalam keheningan, sekilas terlihat mereka sedang memegang kertas.

Visual bangku penonton bioskop tersebut kemudian disuperimpos dengan shot yang kembali menampilkan pemandangan di kebun malam hari, yang kali ini dari sudut ambilan berbeda. Ave Verum Corpus masih mengalun. Kumpulan titik cahaya, yang tadinya tampak tersusun rapi dalam garis horizontal, kini terlihat lebih jelas—ternyata, mereka adalah pendaran cahaya dari tiang-tiang lampu yang tersebar di area kebun. Karena kamera membidik lebih dekat, formasi titik-titik cahaya itu sekarang terlihat berantakan. Namun, keacakannya justru menghadirkan kesan yang tak kalah puitik dan sakral dibandingkan dengan shot sebelumnya.
Lalu shot berganti lagi, kini dari pinggir jalan, dan agaknya kamera merekam ke arah yang berlawanan dari shot pertama di awal film. Alunan Ave Verum Corpus menjeda sejenak ketika suara Hafiz sebagai narator terdengar. Ia berujar:
“Jika kita masih percaya bahwa film adalah pendaran-pendaran cahaya yang menghadirkan gambar, maka ruang gelap, hakikatnya: kenyataan yang harus kita terima dalam dunia sinema. Kegelapan dalam sinema menghadirkan cerita-cerita yang beragam: cinta, tragedi, perjuangan, komedi, dan rekaman realitas kita dalam imajinasi film. Sering kita diam dan tersihir oleh ruang gelap yang penuh misteri ini. Misteri dalam sinema juga mengitari orang-orang di belakangnya.”
Kelanjutan ujaran Hafiz itu mengungkapkan—saat bidikan kamera fokus pada sebuah lampu yang berkelap-kelip cepat, diiringi alunan Ave Verum Corpus yang kembali terdengar pelan, menjadi transisi menuju sekuen berikutnya—bahwa sosok yang dimaksud sebagai salah satu figur di balik dunia sinema adalah Bachtiar Siagian. Seiring berjalannya cerita dalam film, kita nantinya akan mengetahui bahwa Bachtiar Siagian adalah ayah dari Bunga dan Indra. Konon, hampir seluruh karya Bachtiar Siagian dalam dunia perfilman telah dibumihanguskan oleh negara dengan dalih keterlibatannya dalam LEKRA.
Karena begitu mencolok melatari sekuen pembuka BACHTIAR, kita tidak bisa mengabaikan penghadiran Ave Verum Corpus-nya Mozart oleh Hafiz. Musik latar itu adalah sebuah motet pendek berkandung teks liturgis Latin mengenai keberadaan tubuh hakiki; komposisi yang terdengar lembut dan halus lewat suatu harmoni sederhana yang mengesankan ketenangan, yang karena ketenangan itulah ia justru begitu kuat mengekspresikan kebaktian, spiritualitas, dan misteriusitas yang mendalam. Cukup beralasan mengaitkan pemilihan ini dengan kepercayaan Hafiz tentang sakralitas sinema. Pelekatan komposisi musik tersebut ke dalam visual di adegan pembuka, secara khusus, yaitu bidikan panjang yang bergerak tenang perlahan, memperkuat impresi dari pengalaman kontemplatif dan reflektif. Sementara itu, tampilan yang minim informasi pada visual (karena yang tampak jelas hanyalah barisan titik cahaya di tengah kegelapan) secara bersamaan membangun keterlibatan spasial yang ambigu, membangkitkan sensasi tentang misteri dan ketidakpastian.
Pendekatan komposisi Ave Verum Corpus diyakini lebih sederhana dibandingkan dengan karya-karya Mozart lainnya yang lebih megah, seperti Requiem in D Minor.2 Konon, Mozart menciptakan karya ini untuk kelompok paduan suara yang tinggal di lingkungan masyarakat kota kecil.3 Menurut saya, hal ini mencerminkan penciptaan estetika yang lebih merakyat. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Ave Verum Corpus dibuat dengan sedikit menerabas lingkup selera aristokrat dan gereja yang cenderung elitis, sekaligus memancing pengalaman transenden yang melampaui hierarki sosial. Meskipun Mozart diketahui mengalami peningkatan keyakinan spiritual pada masa ia mengomposisi karya ini,4 pendekatan yang ia pilih dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan estetik terhadap kemegahan yang menegaskan batas-batas kelas. Dengan kata lain, Mozart menyasar telinga yang lebih demokratis.
Kita boleh-boleh saja menginterpretasi bahwa konteks di atas terasa sejalan dengan subject matter dalam film BACHTIAR: tentang tokoh yang pemikiran dan praktik keseniannya berupaya membawa film lebih dekat dengan rakyat. Namun, pertimbangan analitik saya, sebenarnya, lebih menjurus ke persoalan formal—didorong oleh pemahaman saya pribadi mengenai Hafiz sebagai seniman yang sangat disiplin terhadap bentuk seni.
Struktur penggayaan sinematik pada sekuen pembuka BACHTIAR bekerja sebagai metafora historis lewat sejumlah modus. Pertama, Hafiz memainkan elemen visual gelap dan terang untuk memancing pembicaraan tentang—antara lainnya—fragmentasi sebagai antitesis terhadap linearitas; atau kaos terhadap keteraturan; serpihan terhadap keutuhan; dan polisentrik terhadap monosentrik. Sementara itu, pancingan visual ini secara puitik juga berkonsekuensi pada penciptaan titik temu antarkonsep, yaitu antara yang spiritual dan yang material, yang temporal dan yang transendental, yang tampak dan yang tersembunyi, yang ada dan yang tiada/hilang.
Amatilah sekali lagi pergantian shot pemandangan kebun itu dan bagaimana garis cahaya berubah komposisi! Dari situ kita bisa menangkap metafor tentang sejarah: yang sering dianggap bergerak/tampak lurus, bisa jadi adalah kumpulan fragmen, titik-titik yang tersebar acak jika dilihat dari sudut pandang lain—terikat secara longgar, spasial, dan elastis. Dengan demikian, sejarah sebenarnya dapat disusun ulang menjadi garis yang baru—tidak harus lurus—berdasarkan pemahaman yang berbeda dari narasi resmi. Sehubungan dengan ‘kebenaran’ dalam sejarah, sesuatu yang tidak tampak bukan berarti tidak ada. Sedangkan persoalan terkait arsip sejarah, apa yang dianggap hilang bisa jadi ditemukan kembali dengan cara dan bentuk yang lain.

Kedua, gaya ungkap (montase) dalam sekuen pembuka film ini mengindikasikan adanya eksperimen terhadap bahasa sinematik, yaitu dengan menolak dramatika konvensional yang biasanya berkutat dengan kejutan-kejutan informatif, cenderung membangun atau mempersiapkan klimaks tertentu, serta berupaya mencari resolusi yang eksplisit. Dalam hal ini, patut dicermati bagaimana unsur atemporal dalam Ave Verum Corpus—baik dari segi struktur musikalnya yang, meskipun berbasis progresi harmonik, memanfaatkan sentuhan karakter modal untuk menyuntikkan rasa spiritualitas abadi, maupun dari segi substansi tekstualnya yang merepresentasikan gagasan bahwa “kematian adalah awal kehidupan kekal”—bergema dengan visualitas “keadaan mengambang” yang dapat diimpresi dari pemandangan kebun malam hari yang dipenuhi pendaran cahaya itu. Kombinasi kedua elemen ini (musik dan visual), dalam konstruksi adegan tersebut, memainkan fungsi metaforis dalam mengungkapkan hal-hal yang melayang di luar waktu linear, yang pada dasarnya tidak dapat dijabarkan dalam kerangka kronologis (dari “awal yang jelas” menuju “akhir yang tegas”).
Sebagaimana halnya dalam pengertian nonkronologis itulah sejarah semestinya dipahami, konstruksi ini pun mewakili standpoint dari filmnya sendiri: menghadirkan atau menemukan kembali Bachtiar Siagian yang “hilang” bukan dengan kedudukannya sebagai individu dalam sejarah yang sudah selesai, tetapi sebagai suatu keberadaan yang gigih mengusik hari kini. Hingga akhir cerita, film ini tidak berniat menutup atau menyudahi sengkarut simpang-siur kisah tentang Bachtiar Siagian. Ketika saya menyebut di awal esai ini bahwa Hafiz menyajikan sebuah kesimpulan, itu adalah kesimpulan dalam konteks formalitas sinematik alih-alih narativitas historis. Sementara, yang ingin saya tekankan di bagian ini, sejarah menurut pengertian BACHTIAR adalah pengalaman yang berlangsung terus-menerus; ia penting bukan karena merupakan sebuah kepastian, melainkan teka-teki; ia bukan semata apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga masa kini yang menggelisahkan, yang “lengkap” dengan ketidaklengkapan definitifnya akan peristiwa-peristiwa lampau, di mana lubang-lubang tersebut justru berpotensi disprutif dan merupakan celah bagi kita untuk bisa meramu masa depan.
Ave Verum Corpus, dalam sekuen pembuka itu, membangun atmosfer sinematik yang menguatkan gagasan tentang peran film (atau peran BACHTIAR secara lebih spesifik) sebagai media yang di dalamnya kisah-kisah yang terlupakan dan dilupakan dapat bergaung dalam bentuk yang tidak sepenuhnya hadir tapi juga tidak sepenuhnya hilang, sebagai kumpulan fragmen atau jejak yang tidak mesti runut dan runtut satu sama lain, tapi selalu dapat ditinjau kembali dan dipertanyakan tanpa henti. Karena mengemban ide tentang suatu pengorbanan yang kudus dan luhur, serta kekhusyukan untuk memahami kebenaran yang hakiki, tentunya Ave Verum Corpus relevan sebagai elegi bagi sosok Bachtiar Siagian yang telah mengalami penghapusan sistematis dalam historiografi resmi sinema Indonesia; ia menjadi korban dari kekerasan epistemik yang menyebabkan ingatan-ingatan tentangnya berserakan dan tidak lagi utuh. Karena keterkaitannya dengan poin inilah, refleksivitas sekuen pembuka BACHTIAR—yang saya sebut bersifat swasadar (self-reflexive) dan berlapis (meta-reflexive) itu—mengemuka menjadi topik yang penting.

Dapat kita kategorikan sebagai modus ketiga yang dimainkan Hafiz dalam hook-nya, voice-over Hafiz tentang ‘cahaya’ dan ‘kegelapan’ berkaitan erat dengan konsep sinema sebagai suatu epistemic field. Hal ini mencakup aspek proyeksi dalam ruang gelap bioskop serta sifat medium film itu sendiri, yang mengandung dikotomi negatif/positif. Adegan voice-over ini bersifat swarefleksif (self-reflexive) karena mengingatkan kita pada sifat dasar film dalam bioskop: citra yang diproyeksikan ke layar menjadi pengalaman visual yang maksimal justru karena area gelap di sekitarnya.
Jika kita melihat dari aspek materialitas film, misalnya film analog (seluloid), cetakan negatif (yang tidak diputar di bioskop) merupakan bentuk mentah yang berisikan inversi dari realitas—di mana area terang dalam dunia nyata tampak gelap, dan sebaliknya. Keunikan ini menjadikan negatif lebih unggul dibandingkan cetakan positif (yang diputar di bioskop) karena menyimpan lebih banyak detail gambar, memiliki daya tahan lebih lama, serta lebih fleksibel sebagai master untuk koreksi dan pembuatan cetakan positif yang didistribusikan ke publik. Dengan demikian, konsepsi ini menegaskan bahwa kegelapan bukan sekadar elemen teknis, tetapi juga bagian dari realitas sinema/film yang tak bisa ditolak.
Kalaupun Anda ingin memperpanjang diskusi dengan membawa topik ini ke konteks situasi masa sekarang, era digital, refleksinya menjadi lebih kompleks dan menarik. Dalam logika digital, yang tidak lagi bersifat fisik, “kegelapan” dalam citra visual berhubungan erat dengan fenomena kebisingan (noise), gangguan teknis (glitch), serta kehilangan atau kerusakan data (file corruption). Berbeda dengan film analog, dalam konteks digital, citra yang mengalami degradasi—misalnya akibat kompresi berulang atau kesalahan pemrosesan data—justru dapat mengungkap kerentanan historiografis. Dengan kata lain, ketidakmaksimalan visual dalam ranah digital bisa berfungsi sebagai pengingat akan keterbatasan dan kerentanan teknologi dalam merekam dan menyimpan sejarah. Pada tahap ini, kita pun memasuki refleksi lapis kedua (meta-reflexive), yaitu refleksi atas proses merefleksi medium film; kesadaran akan bagaimana medium film, baik analog maupun digital, selalu memengaruhi cara kita memahami dan merepresentasikan realitas.
Sebelumnya telah saya singgung bahwa dalam bioskop, kegelapan di sekitar citra yang terproyeksi mengondisikan pengalaman melihat yang maksimal. Secara epistemik, kegelapan berfungsi sebagai wadah bagi ketiadaan. Dalam konteks sinema, justru ketiadaan inilah yang mendefinisikan keberadaan. Hafiz agaknya mengadopsi kerangka teoretik ini—yang berkaitan dengan konsep cinematic absence—ke dalam BACHTIAR melalui dua bentuk kesadaran.
Pertama, kesadaran aktif dalam menyusun ulang bagian-bagian dari materi arsip yang telah mengalami penghapusan, baik sebagian maupun keseluruhan. Penghapusan ini bisa terjadi secara alami akibat faktor waktu maupun secara institusional akibat intervensi kekuasaan. Dengan demikian, Hafiz menekankan bahwa “sinema sejarah” tidak hanya sekadar bagaimana merepresentasikan sejarah, tetapi juga tentang bagaimana menyusunnya kembali dengan perspektif yang baru.
Kedua, kesadaran diskursif dalam menggugat hubungan oposisi biner antara ‘terang’ (pengetahuan, arsip, historiografi) dan ‘gelap’ (pelupaan, penghapusan, misteri). Di sini, Hafiz menunjukkan bahwa ‘penggelapan’ atau absensi atas sesuatu yang semestinya ‘terang’ (yaitu, pengetahuan) tidak selalu berarti kehilangan; sebaliknya, ia dapat menjadi petunjuk yang lebih jelas, yang ‘menerangkan’ bagaimana sejarah sinema di Indonesia berkembang dan direkonstruksi. Artinya, setiap penghapusan atau pemusnahan arsip justru mengungkapkan pola bagaimana kekuasaan dan waktu membentuk historiografi sinema.
Kalau diamat-amati dari sisi naratif, BACHTIAR tidak menampilkan wujud nyata Bachtiar Siagian. Ia hadir hanya sebagai serpihan ingatan, sebagai arsip yang tidak lengkap dan terputus-putus. Hal itu sebagaimana kenyataannya di luar film: keberadaan sosok Bachtiar di dalam wacana perfilman kita pun memang terasa samar, penuh kabut misteri. Identitasnya sebagai orang kiri semakin memperumit jejaknya dalam historiografi sinema Indonesia, karena kisah tentang dirinya telah dinarasikan oleh rezim Orde Baru—dan diwariskan kepada generasi berikutnya—sebagai sesuatu yang tabu, seperti cerita hantu yang harus dihindari dan dilupakan. Namun, Bachtiar juga ‘bergerak’ dan ‘berfungsi’ sebagai “hantu ideologis”, sebagaimana komunisme “menghantui” masyarakat kapitalis. Ia mengganggu dan berbisik di balik catatan sejarah dan keyakinan-keyakinan yang sudah dianggap mapan. Tidak hadir secara langsung, Bachtiar bersemayam di celah-celah historiografi sinema Indonesia yang dipenuhi dengan praktik penghapusan dan pelupaan. Konsep ‘hantu’, ‘kehantuan’, dan ‘menghantui’ inilah yang saya pikir juga melandasi gaya artistik BACHTIAR. Konsepsi itu paling jelas terasa, terutama, dalam sekuen pembuka yang sedang kita bahas. Bagian pendek ini, menurut saya, membuat BACHTIAR masuk ke dalam daftar karya-karya sinema spektral, atau setidaknya mengindikasikan bahwa film ini turut merayakan gagasan tersebut.
Spektralitas dalam BACHTIAR mencuat bukan karena sekuen pembuka film yang kita bahas panjang lebar di sini merepresentasikan entitas supranatural. Bahkan, pembacaan paling liar sekalipun agaknya tidak akan mengarahkan kita ke sana. Jika kita meminjam pengertian yang ditawarkan oleh Jeffrey Andrew Weinstock—sebagaimana dikutip dalam artikel pengantar untuk aplikasi terbuka jurnal Cinergie – Il cinema e le altre arti edisi ke-275— kita bisa mengetahui bahwa, studi-studi spectral cinema berfokus salah satunya pada bagaimana hantu (phantom) dikemas sebagai metafor konseptual untuk mengekspresikan spektralitas sebagai “…gestur yang secara paradigmatik bersifat dekonstruktif, atau sebagai the ‘dark third’… yang mengacaukan ketetapan oposisi biner6 dengan melanggar dimensi kronologis waktu dan sejarah.”
Namun, di dalam BACHTIAR juga tidak ada hantu sebagai representasi, dan film ini nyatanya memang tidak berkisah menggunakan gaya ala-ala film Thailand yang sering menjadi langganan festival. Maka, di manakah letak spektralitasnya?
Yang lebih pasti bagi saya: BACHTIAR spektral karena kepekaan Hafiz dalam mendekonstruksi identitas Bachtiar Siagian serta ingatan kolektif tentang dirinya. Film ini merupakan respons sinematik terhadap bagaimana sosok sutradara kiri itu diwacanakan sebagai ‘hantu’ oleh penguasa; terhadap bagaimana historiografi resmi ala Orba terus ‘menghantui’ masyarakat perfilman Indonesia hingga hari ini; dan juga sebaliknya, terhadap bagaimana pula bayang-bayang Bachtiar, dalam cara tertentu, mengganggu narasi sejarah yang telah terlanjur mapan.

Dengan mengingat konteks-konteks di atas, kegelisahan dan kengerian tentang masa tergelap dalam sejarah Indonesia—khususnya dalam konteks sinema—menjadi kesan yang tak terhindarkan saat menghayati sekuen pembuka BACHTIAR. Namun, kengerian ini bukan ketakutan terhadap masa lalu, melainkan kengerian yang bersifat kini; ketegangan yang masih ada hingga hari ini. Sejarah adalah pengalaman yang terus-menerus, berulang-ulang.
Cermati kembali bagaimana Hafiz, sejak awal, telah menciptakan pengalaman sinematik yang haunting melalui montase pemandangan kebun di malam hari, yang diiringi musik Ave Verum Corpus. Alih-alih mempersiapkan penontonnya untuk menyimak rentetan informasi-informasi dengan ungkapan selugu “Bachtiar Siagian adalah…”, Hafiz melalui formalitas sekuen pembuka tersebut justru sedang memulai pembangunan strategi sinematik yang lebih subtil. Lebih dari sekadar pengantar menuju dokumentasi langka tentang seorang sutradara legendaris yang terlupakan, sekuen pembuka ini adalah basis filosofis untuk memahami cara historiografi sinema Indonesia itu bekerja—penuh dengan zona abu-abu, ingatan yang kabur, dan apa yang disebut ‘terang’ nyatanya hanya muncul dalam kilasan cahaya kecil di tengah kegelapan yang dominan.
Masih dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, adegan kedua dalam urutan sekuen pembuka—yakni adegan di dalam bioskop—menjadi sangat penting untuk dibahas. Mengantisipasi ungkapan verbal-filosofis dalam adegan voice-over yang muncul setelahnya, penampakan di bioskop tersebut mendemonstrasikan sifat swarefleksif medium film secara performatif. Perlu dicatat bahwa apa yang kita lihat pada adegan ini merupakan signature Hafiz—suatu gelagat dan gaya penyutradaraan dokumenter yang juga muncul di Anak Sabiran, Di Balik Cahaya Gemerlapan: Sang Arsip (2013) dan Marah Di Bumi Lambu (2014): Hafiz dengan sengaja membiarkan kamera mengungkap proses produksi filmnya, khususnya ketika kamera itu sendiri sedang merekam peristiwa beserta subjek-subjek di dalamnya (narasumber dan pembuat film). Gaya semacam ini jelas berkebalikan dengan pemahaman dokumenter feature konvensional yang biasanya menyembunyikan proses produksi demi kemulusan kontinuitas penceritaan.
Dalam logika perfilman Indonesia yang berkembang di ranah industri, termasuk genre dokumenter, kebocoran adegan masih sering dianggap sebagai elemen yang tidak memiliki nilai informasi utama—sebuah “area negatif” yang tidak patut ditunjukkan kepada penonton. Kalaupun ingin ditampilkan, biasanya dikemas dalam bentuk behind-the-scenes, yang bukan bagian dari konstruksi film utama, melainkan sebagai trivia atau alat promosi demi mendukung popularitas film di pasar.
Sementara itu, dalam tren dokumenter “kekinian” di industri platform digital dan media sosial, seperti vlog, kita melihat kecenderungan untuk memasukkan cuplikan proses produksi sebagai bagian dari konten. Namun, kita bisa berargumen bahwa, alih-alih sebagai strategi sinematik, fenomena ini lebih banyak didorong oleh pertimbangan praktis, yakni sebagai respons euforia terhadap perkembangan teknologi produksi audiovisual—“teknologi handy”—yang semakin mudah diakses dan digunakan secara instan. Lagipula, siapa yang tak membantah bahwa motif lainnya adalah untuk meningkatkan ekonomi perhatian (attention) dan keterlibatan (engagement)?

Film-film Hafiz, contohnya BACHTIAR ini, mentalitas yang berkerja di dalamnya sama sekali berbeda. Dengan pendekatan Rouchian, Hafiz membiarkan rekaman kejadian berlangsung tanpa banyak pemotongan, termasuk membiarkan bagian-bagian yang memperlihatkan proses produksi. Ia menggunakannya dengan kesadaran estetika—di satu sisi, untuk menggugat stereotipe sinema dokumenter yang sering diasosiasikan dengan objektivitas, dan pada sisi yang lain, untuk menegaskan dan secara langsung menampilkan watak film sebagai alat perekam yang pasti terikat pada bias dan kepentingan tertentu. Dengan sekali lagi kita menggunakan metafora ‘terang-gelap’ itu, sebagaimana Hafiz menggunakannya, maka semakin jelas bahwa sifat dasar medium film (termasuk cara produksinya) hanya dapat dipahami dengan mengakui ‘hal-hal gelap’ yang mengitarinya. Pada poin ini, Hafiz justru menegaskan yang ‘gelap’ itu dengan menampilkan langsung apa-apa yang biasanya disembunyikan; dia tidak lagi menunggu pengkaji media menyelidiki sesuatu ‘yang tak terlihat’ dari film. Dalam hal ini, ia mengajak kita untuk secara sadar mengalami ‘gelap’ itu secara visual, layaknya melihat bidang hitam yang mengelilingi pendar cahaya dalam pemandangan kebun malam hari.
Namun, penegasan yang dilakukan Hafiz bukanlah dengan modus “raw is a style” ala-ala film indie—di mana tangan clapper loader muncul di frame, diikuti teriakan “Sound rolling!”, “Rolling!”, dan “Action!” sebelum adegan sesuai “skrip” dimulai. Di sekuen pembuka BACHTIAR, tidak ada dramatisasi semacam itu.
Perhatikan kembali adegannya: setelah memberikan instruksi singkat kepada Bunga dan Indra, Hafiz mendekati kamera dan dengan santai menyuarakan, “Oke…?! Sound…?! Dah…, mulai!” Sederhana dan lugas.
Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa adegan tersebut bukanlah hasil dari proses yang dipaksakan untuk tampil “mentah” atau dimanipulasi sebagai gimmick. Melalui adegan itu, Hafiz menunjukkan perlakuannya terhadap rekaman kenyataan sebagai material yang harus dipertahankan kejujurannya. Menurut saya, nuansa dalam adegan tersebut jelas mencerminkan komitmen terhadap kejujuran proses produksi, bukan sekadar teknik “estetik” untuk menarik perhatian.
Namun begitu, keautentikan materi visual mentah dalam BACHTIAR bukanlah hasil dari kebetulan semata atau kecerdikan dalam menyeleksi rekaman acak. Misalnya, dalam adegan di mana Hafiz memberikan instruksi, rekaman itu tidak muncul karena operator kamera secara tidak sengaja menekan tombol record lebih awal, atau karena Hafiz secara kebetulan menemukan klip menarik dalam folder dokumentasi syuting dan memutuskan untuk menggunakannya. Saya yakin bukan itu yang terjadi—karena Hafiz jelas bukan seorang hollywoodist. Sebaliknya, setiap peristiwa yang terekam dalam film-film Hafiz adalah peristiwa yang telah dikonstruksi secara sadar. Hafiz telah menetapkan dari awal bahwa ia akan merekam Bunga dan Indra, dan kamera pun sudah diatur untuk mulai merekam sejak saat instruksi diberikan. Justru kegiatan persiapan dan pemberian instruksi itulah yang menjadi inti rekaman, menegaskan kejujuran proses produksi yang terencana.
Dengan kata lain, konsep terkonstruksi yang saya maksud tidak sama dengan ‘pengadeganan’ yang sering kita jumpai dalam dokumenter TV. Adegan tersebut dibangun atas dasar pertimbangan matang—terlepas dari adanya skrip atau tidak. Hafiz, sebagai sutradara, dengan sengaja tampil di depan kamera untuk turut beraksi dan berinteraksi dalam peristiwa yang sebenarnya terjadi. Artinya, ia tidak hanya merekam narasumber saat sedang diwawancarai, tetapi juga menunjukkan proses perekaman itu sendiri, dan juga cara dia melakukan perekaman. Lebih dari itu, Hafiz berupaya menangkap momen produksi dan meta-produksi secara simultan. Kamera tidak hanya merekam peristiwa di depan lensa, tetapi juga merekam situasi-kondisi kamera dan kehadiran orang-orang di belakangnya yang sedang mengoperasikannya. Hal ini kemudian dikemas menjadi sebuah peristiwa filmis, untuk mencapai kebenaran filmis—alih-alih menyajikan film tentang kebenaran, Hafiz menghadirkan kebenaran tentang film yang sedang Anda tonton. Ringkasnya, BACHTIAR adalah film tentang Bachtiar Siagian sekaligus tentang bagaimana Hafiz—bersama kawan-kawannya, termasuk Bunga dan Indra—secara sadar dan konstruktif memfilmkan sosok Bachtiar Siagian.
Refleksi tentang watak medium film yang telah kita bahas sebelumnya secara tidak langsung turut mendiskusikan watak BACHTIAR secara keseluruhan. Adegan voice-over yang menyusul adegan di dalam bioskop semakin menguatkan wacana historiografis sinema—bahwa produksi sinema selalu terikat oleh kepentingan tertentu, demikian pula penulisan sejarahnya. Sebagaimana yang akan kita lihat nanti, tema ini diurai secara bertahap sepanjang film.
Terkait hal tersebut, ada dua alasan mengapa saya sengaja mengulas panjang lebar adegan bioskop di sekuen pembuka. Alasan pertama, saya yakin bahwa, di mata penonton terpelajar yang sudah terbiasa dengan disiplin film dan wacana gerakan kiri, sekuen pembuka ini sangat memukau. Adegan bioskop di sini berfungsi referensial; ia menyampaikan kode penting mengenai politik estetika yang secara sadar dianut oleh Hafiz, sutradara BACHTIAR. Dalam sekuen-sekuen berikutnya, akan semakin terkonfirmasi bahwa “sinematika” Hafiz dan Bachtiar ternyata lahir dari akar pemikiran yang sama. Dengan kata lain, pendekatan Rouchian dalam film ini bukanlah sesuatu yang sekonyong-konyong; bukan dilakukan secara sembarangan.
Alasan kedua, bagi penonton awam yang tidak mendalami sejarah gerakan kiri ataupun film eksperimental, sekuen pembuka ini agaknya akan menjadi titik untuk kembali—setelah menuntaskan menonton film—dalam rangka memahami lebih jauh bahwa, bahkan ternyata, sutradara BACHTIAR juga memilih aktif terlibat dalam pertarungan wacana historiografis sinema Indonesia. Keterlibatan itu tampak melalui tiga modus yang telah kita bahas: penggunaan metafora audiovisual (adegan pertama), deklarasi verbal (adegan ketiga), dan aksi nyata dalam proses produksi (adegan kedua, yaitu adegan di bioskop).
BACHTIAR, yang dalam konteks pembahasan di artikel ini diwakili oleh sekuen pembukanya, begitu kentara mencerminkan gagasan yang memandang film sebagai metode aktif dari historiografi—bukan sekadar dokumen pasif tentang masa lalu. Sekuen pembuka yang juga bersifat meta-refleksif ini membekali penonton dengan pemahaman bahwa film adalah perangkat historiografis, yang tidak melulu hanya diperlakukan sebagai sumber sejarah, tetapi juga sebuah medium untuk menciptakan-nya.
Pendekatan yang dipilih Hafiz untuk BACHTIAR selaras dengan ide bahwa sejarah tidak hanya ditemukan, melainkan dikonstruksi. Dengan menyadari bahwa sejarah selalu merupakan hasil konstruksi—di mana film juga memainkan peran signifikan dalam pengkonstruksian tersebut secara politik, sosial, dan kultural—maka film itu sendiri, sebagai medium visual dan temporal, berpotensi pula menjadi alat disruptif, untuk mengkonstruksi sejarah tandingan; film harus menjadi suatu perangkat yang memungkinkan intervensi historiografis yang unik, yang tidak dapat dicapai oleh sejarah tertulis dengan cara yang sama.
Begitu canggihnya BACHTIAR sehingga saya pribadi masih terpukau oleh sekuen pembukanya yang hanya berdurasi lima menit! Sekuen ini tidak hanya menarik, melainkan juga mampu membuka ruang perbincangan yang panjang lebar seperti yang kita alami sekarang. Kedalaman-kedalaman lainnya, tentu saja, akan terus terungkap seiring kita mengupas sekuen-sekuen berikutnya dalam film ini. []
Bersambung ke Watak BACHTIAR (Bag. 2)
Endnotes